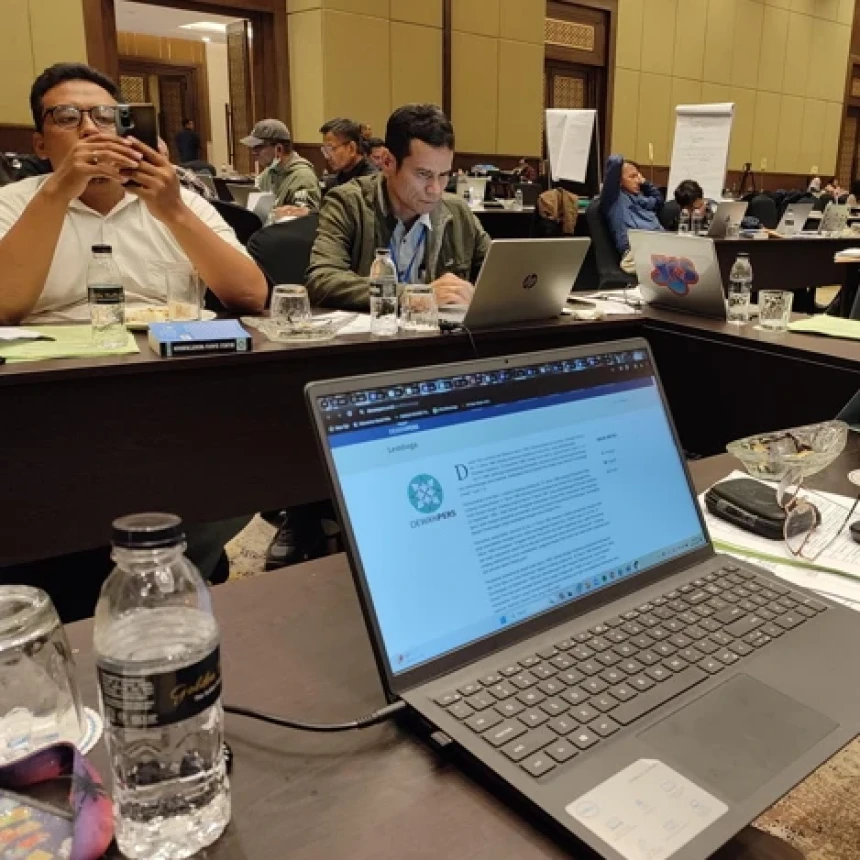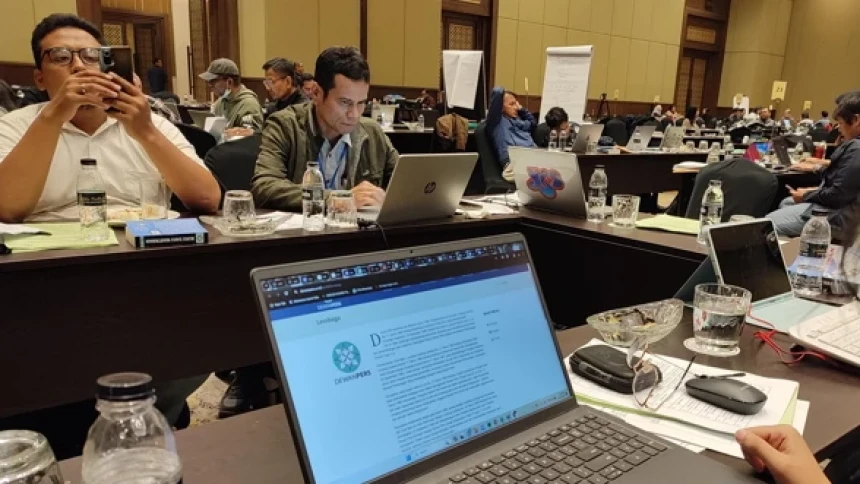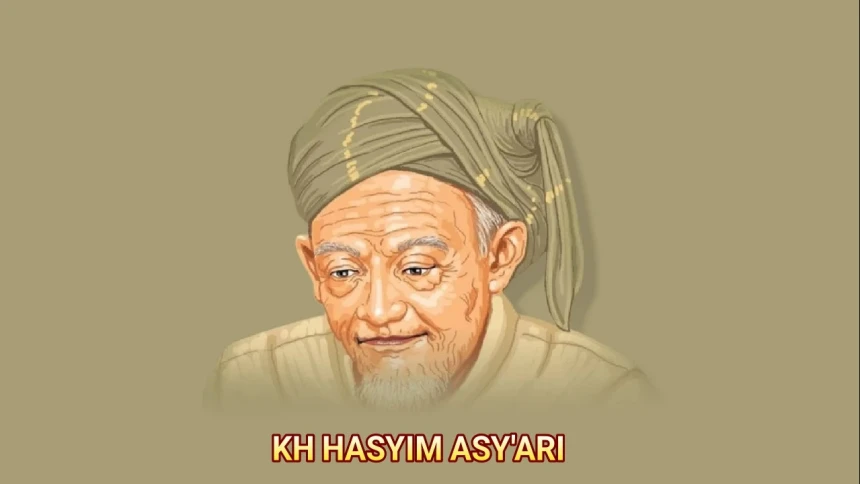Hakikat pendidikan adalah mengubah kondisi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak sadar menjadi sadar, dari statis menjadi dinamis, dari apatis menjadi peduli dan inovasi lainnya. Perubahan positif yang ditimbulkan juga diharapkan berjalan sistematis dan terus-menerus. Pada posisi kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam kontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Maka dalam konteks kebangsaan, sistem pendidikan idealnya selaras dengan arah pembangunan bangsa dan negara, serta cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
Spirit cita-cita kemerdekaan yang hakiki juga telah mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan rumusan Pasal 3 "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".
Sedikit membuat analisisa dari kedua rumusan tersebut, jika hakikat pendidikan untuk perubahan lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan, maka seakan ada aspek yang butuh proses yang cukup panjang untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut. Satu contoh, kata adil dalam cita-cita kemerdekaan, dengan kata apa tujuan pendidikan nasional menjawab untuk mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara pada sistem pendidikanlah, harapan masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan.
Pertanyaan mendalamnya, benarkah sistem pendidikan nasional dengan ketimpangan rumusan tujuan, akan dapat menghantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan yang hakiki? Bagi kaum behaviorisme jawabannya "pasti bisa" dengan tetap membangun romantisme masa lalu. Tapi bagi kaum konstruktivisme jawabannya "on going process", tapi tak tahu proses itu akan mencapai atau mendekati tujuan utama.
Secara taktis untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional telah diterapkan dan dikembangkan berbagai model kurikulum pendidikan. Mulai kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013. Mulai dari penekanan pada kompetensi kongnitif, psikomotor, hingga afektif. Mulai dari transfer pengetahuan, pengalaman, pengamalan hingga karakter. Tapi alih-alih mendekati mencapai tujuan pendidikan atau tujuan kemerdekaan. Faktanya indeks korupsi semakin naik, budaya baca semakin lemah, tradisi dan budaya yang mencerminkan nilai Pancasila semakin luntur. Padahal mestinya proses yang berjalan itu bergerak mendekati tujuan. Tentu tidak bisa dinafikan bahwa memang ada faktor global yang mempengaruhi laju mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Mengutip pidato yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dalam Pengukuhan Pimpinan Pusat dan Rapat Kerja Nasional di Lombok, NTB, (25/02) bahwa orientasi pendidikan nasional harus diluruskan kembali sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang diberitakan oleh media NU Online, bahwa "pendidikan selama ini, bisa dikatakan gagal. Sebab, pendidikan selam ini tidak mampu mewujudkan cita-cita luhur kemerdakaan. Tanda-tanda adil secara merata, kesejahteraan, masih jauh karena pelaku keadilannya belum berorientasi sejak menjadi pelajar. Orientasi pendidikan saat ini, hanya memproduksi murid yang menjadi pegawai, baik negeri maupun swasta; buruh pabrik. Oleh karena pendidikan berorientasi pegawai, maka jadinya, hanya menjadi pegawai saja. Mereka yang menantikan tegaknya keadilan dan kesejahteraan hanya terus menanti. Orientasi pendidikan yang dimaksudkan adalah menciptakan peserta didik yang kreatif dan berdaya saing tinggi, serta memiliki akhlak yang baik. Orientasi pendidikan, lembaga pendidikan harus melahirkan cendekiawan yang menerangi, anak didik pemimpin dunia dan bangsanya yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Pendidikan yang menggerakan anak didik menjadi konglomerat yang berorientasi kepada kesejahteraan".
Sejalan dengan itu, menurut Paulo Freire, dengan konsep pendidikan alternatif mencoba mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan, atau bisa disebut dengan usaha untuk "memanusiakan manusia" (humanisasi). Dengan menggunakan pendekatan humanis, ia membangun konsep pendidikannya mulai dari konsep manusia sebagai subyek aktif. Manusia adalah makhluk praksis, yakni makhluk yang dapat beraksi dan berefleksi dengan menggunakan pikirannya.
Analisa dari pandangan tokoh Pergunu, Asep Saifuddin Chalim dan Sang Inisiator gagasan pendidikan alternatif, Paolo Fiere adalah adanya spririt memerdekakan dalam setiap paradigma pendidikan menjadi sangat penting. Karena disitu nilai luhur kebangsaan akan terus terjaga, serta akan maju dan berkembang bersama atas nama bangsa dan negara. Bukan pendidikan yang justru menimbulkan kesenjangan antara di kaya dan si miskin, si birokrat dengan rakyat jelata. Jika orientasi pendidikan tidak didasari cita-cita kemerdekaan yang berkelanjutan, maka selamanya akan terbawa kedalam jurang ketidakadilan.
Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk menggerakkan ruh cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam orientasi pendidikan nasional. Pemerintah selaku pemegang kebijakan harus konsisten dan adil terhadap paradigma pendidikan yang akan dijalankan. Berikan kepercayaan kepada masyarakat untuk tumbuh dengan karakteristik unik yang dimilikinya.
Indonesia pernah memiliki sejarah sukses dalam mengembangkan pendidikan kerakyatan, yang mampu menjelma menjadi kekuatan kebangsaan sebagai paradigma pembebasan dari belenggu kolonialisme. Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, memiliki orientasi khas keindonesiaan, dengan ciri pendidikan karakter dan kemandirian. Sekolah Kartini, mampu membangun spirit perjuangan emansipasi perempuan, tapi tetap menjujung nilai budaya keindonesiaan. Tak kalah hebatnya, Pendidikan pesantren yang sampai saat ini telah memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan bangsa dan negara. Sudah sajauh mana sistem pendidikan kita, berkontribusi pada upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan? Wallahu'alam.
Penulis adalah salah satu Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)
Terpopuler
1
Khutbah Idul Adha 1445 H: Haji dan Kurban, Barometer Keimanan dan Ketakwaan
2
Khutbah Jumat: Tiga Siasat Nabi Ibrahim Memperjuangkan Agama Tauhid
3
Khutbah Jumat: Anjuran dan Keutamaan Puasa Tarwiyah dan Arafah
4
Menag: Murur Sudah Dikaji Secara Fiqih dan Pertimbangkan Keamanan Jamaah
5
Kemendikbud Umumkan Hasil UTBK SNBT 2024, Cek di Sini
6
Kata Ketua Umum PBNU soal Fatwa Larangan Salam Lintas Agama
Terkini
Lihat Semua