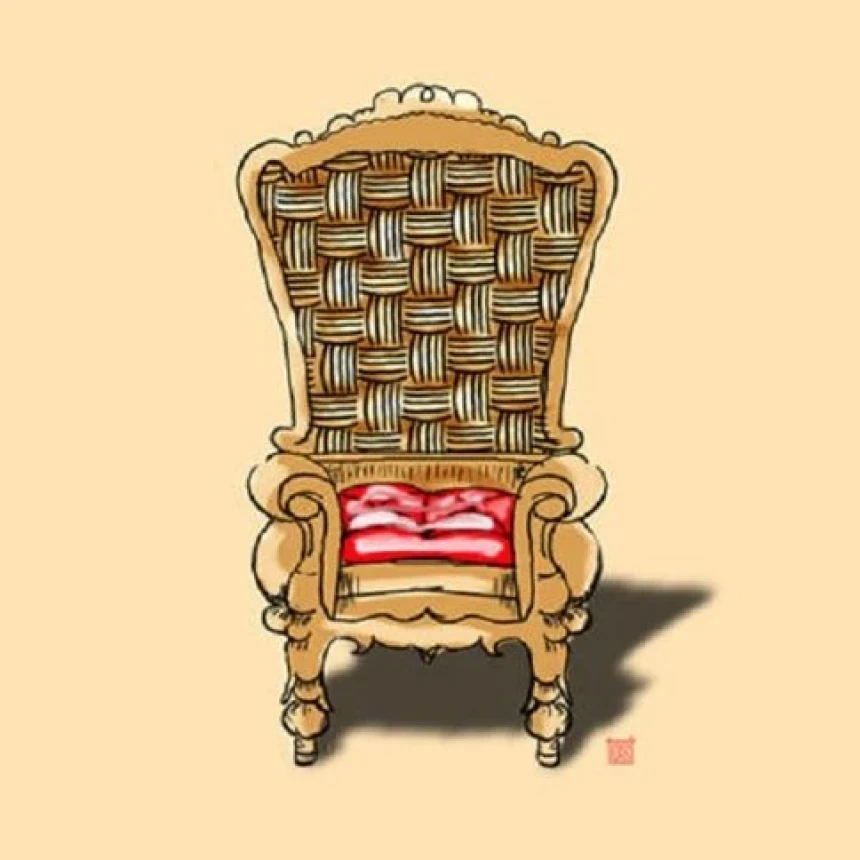Kisah Mbah Ma’shum dan Kiai Bisri Mustofa: Imbas Kehancuran PKI atas Kekalahan NU di Pemilu 1971
Sab, 30 September 2023 | 20:45 WIB
Hamzah Sahal
Kolomnis
Pada 1970-an, ada banyak kiai dari Rembang yang terkenal, antara lain Kiai Ma’shum Ahmad dan Kiai Bisri Mustofa. Nama yang disebutkan pertama diperkirakan lahir pada 1868 (kalau benar dilahirkan di tahun itu, berarti ia lebih sepuh dari Kiai Muhammad Hasyim Asy’ari), pendiri Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang sekaligus salah satu penanda tangan pendirian NU di Surabaya pada 1926. Pesantren Lasem di bawah asuhan Mbah Ma’shum (w. 1972) melahirkan ulama-ulama pesantren yang mumpuni dan kader-kader NU pilih tanding.
Nama kedua jauh lebih muda. Ia dilahirkan di Rembang pada 1915 (tahun yang sama ketika Kiai Ali Maksum, putra Mbah Ma’shum, dilahirkan). Kiai Bisri Mustofa (w. 1977) adalah pendiri Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang; ulama dengan belasan karya kitab/buku—yang paling terkenal adalah tafsir dan terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Jawa,Tafsir al-Ibriz; aktivis partai (anggota Konstituante dari Partai NU); dan orator ulung.
Baca Juga
Akal-akalan Kiai Bisri Mustofa
Kedua tokoh kita ini, meskipun secara umur seperti ayah dan anak, berelasi layaknya sahabat. Uniknya, mereka punya karakter dan sikap yang nyaris bertolak belakang, misalnya dalam menyikapi modernisasi. Mbah Ma’shum hampir antiradio; sementara Kiai Bisri Mustofa bukan saja pendengar setia, tetapi juga penikmat musik-musik yang mengalun dari radio. Perbedaan semacam ini tak menyurutkan kehangatan hubungan para kiai pada waktu itu.
NU dan Pemilu 1971
Kiai Masyhuri Malik, Ketua PBNU dan santri Mbah Ma’shum asal Batang, Jawa Tengah, yang mondok di Lasem pada 1969-1974, bercerita jika Mbah Ma’shum butuh teman bicara atau butuh hiburan, maka Kiai Bisri akan diundang untuk datang ke Lasem. Jarak dari Leteh ke Lasem sekitar 15 kilometer.
Alkisah, tidak lama setelah Pemilu 1971, Kiai Bisri sowan ke Lasem memenuhi panggilan sahabatnya itu. “Mbah Ma’shum bertanya kepada Kiai Bisri mengapa NU dikalahkan Golkar?” demikian kisah Kiai Masyhuri Malik kepada saya dalam sebuah perbincangan.
Pemilu 1971 dimenangkan oleh Golkar, organisasi politik baru yang sangat populer di masa itu. Secara legal, Golkar sebenarnya bukan partai politik meskipun menjadi peserta pemilu. Memang aneh. Ketika didirikan pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), organisasi ini pada mulanya adalah konfederasi dari berbagai organisasi kekaryaan yang didukung tentara. Tujuannya utamanya cuma satu, yaitu melawan pengaruh
Partai Komunis Indonesia (PKI). Kala menjadi presiden, Soeharto mengambil Golkar sebagai kendaraan politiknya.
Pada pemilihan umum pertama di zaman kepresidenan Soeharto itu, Golkar mendapatkan 238 kursi, sedangkan Partai NU yang ada di urutan kedua hanya bisa meraih 58 kursi (18 persen dari 50 juta pemilih). Pemenang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan cuma 20 kursi.
Atas pertanyaan Mbah Ma’shum, Kiai Bisri tidak menjawab fakta sebenarnya mengapa NU kalah dan hanya mendapatkan 58 kursi—jauh sekali di bawah Golkar. Kiai Bisri tentu saja dapat memahami dan menganalisis bahwa Pemilu 1971 adalah pemilu yang semata-mata licik, brutal, dan penuh kekerasan dengan Partai NU sebagai sasaran utama, selain PNI. Sekadar contoh, di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, terjadi pembakaran kampung oleh aparat karena Partai NU menang 100 persen. Intimidasi oleh pemerintah kepada kaum santri terjadi di hampir seluruh basis Partai NU.
Lalu, apa jawaban Kiai Bisri atas pertanyaan Mbah Ma’shum?
“Enak betul NU, Mbah, habis ikut nggebuki PKI, lalu pemilu juga menang? Kok, NU seperti disayang Gusti Allah? Enak betul.”
Demikian jawaban Kiai Bisri, sebagaimana diceritakan Kiai Masyhuri Malik.
Gaya bercerita Kiai Bisri Mustofa yang ringan dengan intonasi bicara dan gerakan tubuh yang khas membuat Mbah Ma’shum tertawa terkekeh-kekeh. Keahlian Kiai Bisri bercerita inilah, dan juga keberaniannya, yang disukai Mbah Ma’shum.
Unsur mengejutkan dari jawaban ini juga menjadi bahan refleksi Kiai Bisri yang waktu itu berumur 50-an. Tetapi memang, jawaban tersebut bukan sekadar gurauan. Menurut Kiai Ahmad Mustofa Bisri, Kiai Bisri adalah “kiai politik” yang sebenarnya. Ia paham betul seluk-beluk politik, termasuk gonjang-ganjing 1965-1966.
“Keterpurukan/keterkucilan NU selama 32 tahun di bawah rezim Soeharto, menurut almarhum Kiai Bisri, adalah kualat oleh perlakuannya dalam pengganyangan PKI yang membabi buta dan tanpa pandang bulu,” tutur Kiai Ahmad Mustofa Bisri, yang tak lain adalah putra Kiai Bisri, kepada saya, Jumat (29/9/2023).
Kiai Ahmad Syakir Ma'shum, putra Mbah Ma’shum yang waktu itu ikut dalam pembicaraan, mengutarakan ketidaksetujuan atas jawaban Kiai Bisri dengan mengatakan PKI itu bughat atau pemberontak. Kiai Bisri tetap pada pendiriannya bahwa orang NU yang ikut menghantam PKI tetap salah. "Banyak anggota PKI itu syahadat, kenapa harus digebukin?" cerita Masyhuri Malik menirukan Kiai Bisri.
Mendengarkan putranya berdiskusi serius dengan Kiai Bisri, Mbah Ma'shum lagi-lagi gemujeng (tertawa) saja. Entah, apa makna tertawa Mbah Ma’shum ini.
Hamzah Sahal, Sekretaris LTN PBNU
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menjadikan Diri Pribadi Taat melalui Khutbah dan Shalat Jumat
2
Khutbah Jumat: Anjuran Berbakti kepada Orang Tua dalam Islam
3
Khutbah Jumat: Inspirasi Al-Fatihah untuk Bekal Berhaji ke Baitullah
4
Kajian Hadits: Kawin Kontrak di Zaman Rasulullah
5
Lolos Semifinal Piala Asia U-23, Timnas Indonesia Menuju Olimpiade Paris 2024
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Kathah Cara Kangge Sedekah
Terkini
Lihat Semua