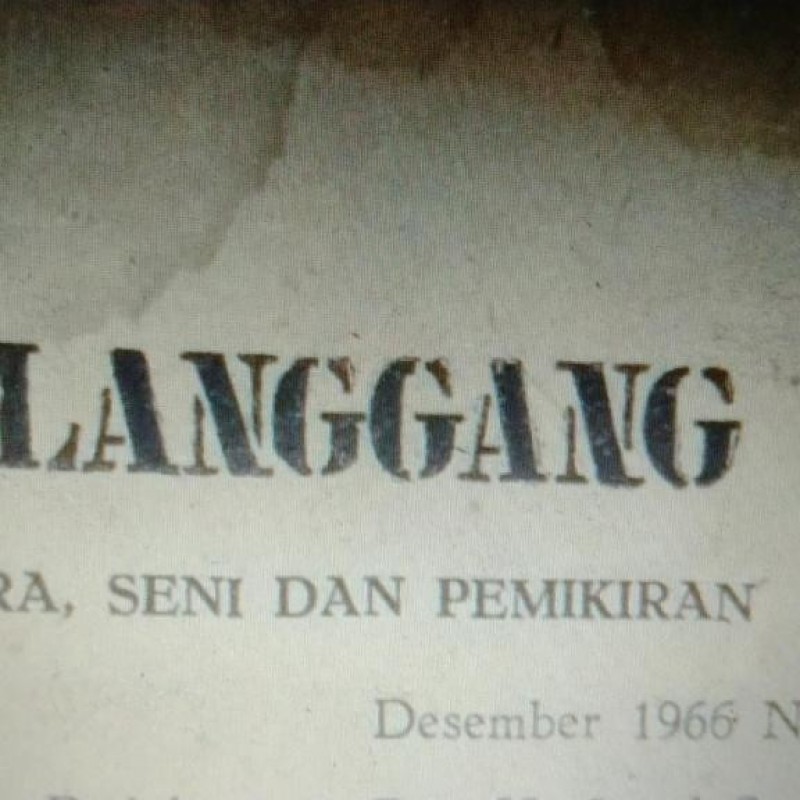Achmad Murtafi Haris
Kolomnis
Seorang profesor Studi Lintas Agama pada Indonesian Consortium for Religious Studies Yogyakarta saat presentasi di Georgetown University Amerika tentang kehidupan beragama di Indonesia: “Living in the Sacred Cosmos: Religion and Democracy in Indonesia”, ditanya oleh peserta seminar: “Apa yang menarik bagimu dari Indonesia?
Bernard Adeney Risakota, sang profesor itu, menjawab: “Yang menarik dari Indonesia adalah apa yang mereka pakai di kepala mereka”, yang disambut tawa hadirin. Pak Bernie, begitu dia biasa dipanggil di Universitas Gadjah Mada mengatakan, bahwa ada banyak jenis topi atau tutup kepala yang digunakan oleh orang Indonesia yang menarik perhatiannya sejak awal kedatangannya ke Indonesia. Tentu topi di sini adalah topi tradisional bukan topi modern yang berasal dari Barat. Tiap suku di Indonesia memiliki topi tradisional yang menjadi identitas budaya lokal. Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Betawi, Minang, Bugis, Banjar, Lombok, Sumba, Bali dan lain-lain, masing-masing memiliki topi dan baju daerah masing-masing. Selain itu terdapat topi nasional dan topi kaum santri yang juga beragam. Walhasil, apa yang orang Indonesia gunakan di kepala mereka adalah sesuatu yang unik artistik yang menarik perhatian Bernard Adeney tentang Indonesia.
Di antara topi yang khas Indonesia adalah Songkok dan Belangkon. Yang pertama menjadi identitas Nasional Indonesia, sedang yang kedua adalah identitas Jawa. Dibandingkan dengan songkok (Inggris: skullcap) atau kopiah (Arab: khufyah/kafiyeh) atau peci (Belanda: petje), belangkon lebih tua. Belangkon menggabungkan antara budaya Hindu-Budha dan Islam. Konon ia merujuk pada kisah Aji Saka saat pertama masuk tanah Jawa dan mengalahkan makhluk raksasa Dewata Cengkar dengan cara menyebarkan untaian kain penutup kepalanya hingga menutupi tanah Jawa. Sementara itu disebutkan bahwa belangkon juga berasal dari Muslim Gujarat yang datang ke Indonesia dengan menggunakan ikat kepala dari kain yang kemudian ditiru oleh orang Indonesia hingga menjadi seperti sekarang. Belangkon asalnya bagian atasnya tidak tertutup kain. Namun, karena pengaruh budaya Islam, bagian atasnya ditutup. Ia juga bisa jadi untuk memperingkas dari yang semula selembar kain diikat atau dililitkan di kepala dibuatlah bentuk topi sehingga tanpa mengikatnya di kepala tapi langsung memakainya, kata Ranggajati Sugiyatno, ahli blangkon.
Sumber Yahudi yang notabene representasi budaya Timur-Tengah selain Islam dalam Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge juga menyebutkan bahwa sebagian orang Yahudi tidak menggunakan tutup kepala, sebagian menggunakan sekadar kain pengikat agar rambut tidak berserakan dan sebagian terutama kaum petani menggunakan serban sebagai penutup kepala. Serban yang segi empat itu dilipat jadi dua sehingga menjadi segitiga. Dari depan kepala ditarik ke belakang dan diikat. Sisa kain dibiarkan menjuntai ke dua bahu atau seperti kafiyeh sekarang.
Arab di zaman Rasulullah juga demikian halnya. Apa yang tampak dalam televisi sejarah perjuangan Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab yang diproduksi oleh produsen film Arab, yang menampakkan cara berbusana orang Arab dahulu adalah seperti itu adanya. Mereka menggunakan udeng atau tutup kepala dari kain panjang yang diputar dan diikatkan di kepala membiarkan sisanya jatuh ke bahu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah disebutkan bahwa tatkala Penaklukan Makkah (Fathu Makkah) seorang sahabat melihat Rasulullah menggunakan tutup kepala serban (‘imamah) berwarna hitam yang buntutnya jatuh ke bahu.
Dengan demikian headdress atau tutup kepala adalah budaya manusia semenjak dahulu kala lebih dari empat ribu tahun yang lalu pada zaman Firaun, Romawi, Yunani, Yahudi dan India. Dunia modern yang lebih egaliter dan praktis yang mereduksi hal itu. Jikalau pada zaman dahulu topi mengandung makna status sosial seperti keluarga istana, agamawan, petani, pada era kini di mana manusia hidup dalam sistem egaliter dan tidak menampakkan strata sosial dalam busana, maka topi hanya menyisakan aspek fungsionalnya. Ia kemudian menyatu dalam bentuk yang sama seantero jagat. Yaitu topi yang banyak beredar di mana-mana dengan sosoran depan penahan panas terik matahari. Atau dikenal dengan topi distro, baseball, converse yang aslinya banyak digunakan oleh supir truk Amerika.
Indonesia beruntung memiliki kekayaan budaya dalam bentuk topi khasnya. Ia adalah songkok atau kopiah atau peci yang berwarna hitam yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Adalah Soekarno Presiden RI pertama yang memperkenalkannya yang kemudian diikuti oleh yang lain. Songkok yang berasal dari budaya Turki Ottoman, tarbus, berbentuk tabung berwarna merah dan rumbai hitam, diubah bentuknya menjadi lebih pendek dan bisa dilipat. Postur Soekarno yang tinggi dan tampan menjadikan songkok yang dipakainya memikat. Ia memberikan arti tersendiri bagi Indonesia yang merdeka dari pengaruh budaya asing. Ia menjadi identitas bangsa yang hadir saat dibutuhkan. Identitas yang mampu membedakan siapa kita dan mereka (self and other).
Setelah menjadi identitas nasional, ia kemudian banyak diadopsi kaum santri dan dipadupadankan dengan baju koko (taqwa) dan sarung. Setelah era Soekarno, songkok tidak banyak tampak digunakan kaum nasionalis. Kaum santri yang paling melestarikannya saat itu dan hingga kini.
Belangkon, apalagi, ia hanya ada di keraton dan selainnya hanya dalang wayang kulit serta pengantin Jawa yang memakainya. Setahun sekali muncul di karnaval Kartinian oleh anak Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak. Setelah raib oleh arus modernisasi, Belangkon baru muncul lagi saat Gus Dur menjadi presiden di mana sekretaris pribadinya Sastrouw Elngatawi selalu memakainya. Baru saat itu blangkon tampil ‘vulgar’ di tengah istana kepresidenan. Ini seolah menunjukan bahwa sistem republik bukanlah tempat yang menjanjikan bagi busana tradisonal seperti blangkon untuk lestari. Tempatnya adalah di sistem kerajaan seperti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kasunanan Surakarta. Republik Indonesia memunculkan budaya nasional dengan songkok sebagai identitasnya sedangkan belangkon adalah identitas lokal Jawa yang hanya ada di pusat kebudayaannya. Orang Jawa meninggalkan belangkon karena kedekatan mereka dengan budaya nasional lebih tinggi daripada budaya daerah.
Mas Didi Kempot almarhum adalah yang kembali mampu menarik identitas Jawa yang lokal itu ke pusat peredaran nasional. Menggesernya dari posisi marginal ke sentral. Belangkon yang dipakainya tampil dengan penuh percaya diri dan menaklukkan dominasi budaya nasional yang modern dan pop. Apa yang dianggap ndeso dan kampungan ternyata mampu merebut panggung utama setelah lebih setengah abad tiarap oleh stigma ketinggalan zaman. Ternyata dominasi budaya nasional atas budaya lokal mampu dilawan oleh Didi Kempot, the Godfather of the Broken Heart. Semoga sang maestro bahagia di sisi-Nya, amin.
Achmad Murtafi Haris, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
Terpopuler
1
Innalillahi, Nyai Nafisah Ali Maksum, Pengasuh Pesantren Krapyak Meninggal Dunia
2
Sosok Nabi Daniel, Utusan Allah yang Dimakamkan di Era Umar Bin Khattab
3
Cerita Pasangan Gen Z Mantap Akhiri Lajang melalui Program Nikah Massal
4
Asap sebagai Tanda Kiamat dalam Hadits: Apakah Maksudnya Nuklir?
5
3 Pesan Penting bagi Pengamal Ratib Al-Haddad
6
Mimpi Lamaran, Menikah, dan Bercerai: Apa Artinya?
Terkini
Lihat Semua