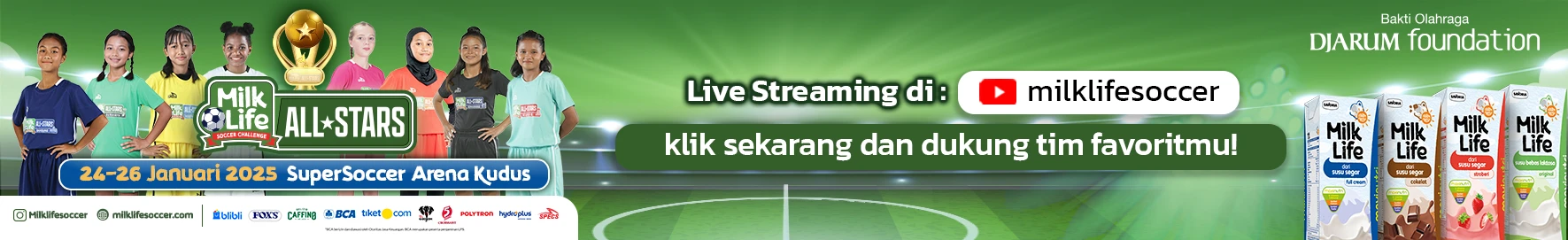Oleh: Joko Priyono
Narasi keberagaman di perguruan tinggi acap kali menyita perhatian. Ia terdiri dari komunal yang berangkat dari latar belakang yang berbeda—suku, agama, budaya, ras maupun bahasa. Keseluruan dari berbagai elemen yang ada kemudian menjadi satu—atas nama sivitas akademik. Dari sana, kemudian kampus menjadi ruang yang inklusif atas kehadiran berbagai pemahaman maupun ajaran—ideologi, tak terkecuali dalam ranah pendidikan agama. Fenomena yang kemudian terjadi adalah perkara akibat dari penyalahgunaan dari regulasi kebebasan akademik.
Seorang guru besar Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Budi Santosa, sebelumnya tidak mungkin jika tak merasakan keluh maupun kesah hingga menuliskan esai yang cukup panjang—termuat dalam Harian Kompas edisi 11 Agustus 2017. Tulisannya berjudul Kebebasan Akademik Tercemar mengetengahkan hal-ihwal peristiwa maupun fenomena dari penyalahgunaan kebebasan akademik. Misalkan, satu diantaranya ia menyebutkan—di kampus-kampus universitas umum, kajian ilmiah keilmuan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi kadang kalah dominan dibandingkan kajian agama yang diselipi pesan kelompok.
Fakta tersebut, tak bisa dipungkiri terjadi di banyak universitas umum yang ada di Indonesia. Ketakutan yang kerapkali muncul adalah bukan pada persoalan—ada, tidaknya pendidikan agama di dalam kampus. Melainkan dari itu, ketika yang terjadi adalah upaya yang tersistematis dan terstruktur—justru melahirkan ancaman dalam kehidupan bernegara, berbangsa maupun beragama. Frasa yang mewakili pada persoalan tersebut berupa kemunculan gerakan radikalisme, ekstremismemaupun fundamentalisme di dalam kampus. Sikap yang terjadi seperti diantaranya adalah anti NKRI hingga penolakan terhadap kehadiran Pancasila.
Lebih celaka lagi adalah ketika oknum yang terlibat di sana, berupa merekayang berasal dari kalangan pengajar atau dalam hal ini adalah dosen. Tanpa bermaksud untuk menyudutkan nama perorangan, penulis yang menjadi bagian pengkaji ilmu fisika di salah satu perguruan tinggi hingga saat ini—pernah juga mendapatkan pengalaman yang membuat penat kepala. Seperti di antaranya, dalam sebuah kesempatan presentasi, seorang dosen pernah terjadi penyelipan bendera Palestina di bagian awal pada slide presentasi, penyelipan pesan-pesan yang menyudutkan salah satu agama dalam sesi ceramah—penyampaian materi di dalam kelas hingga penokohan tokoh agama tertentu—sedang populer di berbagai jenis media sosial.
Inklusif ke Eksklusif
Mahasiswa baru paling mudah terbujuk dalam forum maupun kegiatan—tak terkecuali padakajian keagamaan yang ada di dalam kampus. Sebenarnya tak ada yang salah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah saat mahasiswa tidak berangkat dengan fondasi yang kuat. Apalagi, dalam waktu-waktu awal di perguruan tinggi maupun kampus, para mahasiswa disibukkan dengan kegiatan, yang diantaranya adalah upaya untuk melakukan penyesuaian dengan habitat di lingkungan barunya—adaptasi. Selain itu pula, terkadang yag terjadi, memang, mahasiswa yang berada di kampus umum adalah mereka yang berasal dari sekolah menengah berlatar belakang umum juga. Memahami dan mempelajari agama sangat mengharuskan sikapkehati-hatian.
Pola yang terbentuk—biasanya dimulai pada bentuk yang bersifat inklusif. Dalam hal ini adalah memberikan pemaknaan yang menjadikannya pada sebuah kesadaran umum akan kebutuhan memahami agama di kampus-kampus umum. Di beberapa kampus, terutama kampus negeri hingga hari ini yang terjadi adalah adanya program pendampingan yang memiliki ranah kerja sebagai suplai tambahan dari adanya mata kuliah pendidikan agama—yang biasanya wajib di semester pertama bagi mahasiswa. Kita perlu mempertanyakan kredibilitas dan kapasitas dari program pendampingan tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah para pendamping atau biasa disebut asisten tersebut biasanya juga berasal kalangan mahasiswa—secara semester lebih tua.
Pasalnya, mempelajari agama tidak sesederhana—dari fenomena yang kerapkali hadir di permukaan media sosial. Belajar beragama terkadang hanya dimaknai—bahwa cukup dengan membaca buku, membaca tulisan-tulisan yang berkaiitan dari berbagai laman di internet atau bahkan mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang sedang ngetren maupun populer di youtube, dan lain sebagainya. Belajar agama dibutuhkan kerendahhatian dalam bersikap untuk menuju tujuan pada sanad keilmuan yang jelas hingga menaruh hormat maupun takzim kepada guru agama yang memang tidak diragukan lagi akan kapasitas ilmu pengetahuan maupun wawasannya.
Sebab, jikalau sudah terjadi pada kesalahan awal—di forum pendampingan, ini membuka peluang masuknya kepentingan dari beberapa oknum maupun kelompok yang memanfaatkan berbagai lini yang ada di sana. Lebih lagi, dampak yang berkepanjangan dari hal tersebut, pola yang kemudian hadir adalah menjadi eksklusif. Berkaitan mengenai hal ini, menjadikan pola yang lebih terstruktur dan tersistematis dalam upaya pemasifan nilai-nilai maupun ajarannya. Dogmatisasi mungkin sangat begitu sering terjadi.
Ketika berbicara data, tidak mengherankan pada tanggal 30 Mei 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan beberapa kampus umum yang terpapar radikalisme. Masing-masing dari kampus tersebut: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR) hingga Universitas Brawijaya (UB). Kondisi ini sangat begitu mencemaskan. Terlebih—apalagi jikalau dikembalikan pada hakikat mahasiswa—adalah mereka yang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan, generasi penerus bangsa, agen kontrol sosial hingga agen perubahan.
Solusi
Dari kesemuanya, bukan tanggung jawab dari satu maupun pihak saja. Melainkan dari itu, merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai elemen yang ada di Indonesia. Konstruksi yang dihadirkan tentu saja adalah komitmen dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama di tengah heterogenitas yang ada di Indonesia. Kebebasan akademik, sebagaimana termatukub dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, harus menjadikan kerangka seluruh pihak yang terlibat—tidak menyelipkan kepentingan yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme maupun fundamentalisme.
Di luar itu, perlu diketahui bersama, mahasiswa sebagai generasi yang digadang-gadang sebagai agen perubahan maupun agen kontrol sosial—mencerminkan citra intelektualitas, moralitas maupun spiritualitas harus punya andil mencegah terjadinya gerakan-gerakan yang mengancam ideologi bangsa, Pancasila maupun keutuhan negara. Yang diharapkan dari para mahasiswa, tentu saja adalah terkait pola aktivisme di dalam kampus. Satu perhatian dalam wacana ini: masjid kampus. Mengambalikan kegiatan di masjid kampus seperti sebagai pusat kegiatan keilmuan, aktivitas intelektual, kajian keislaman, serta pelatihan-pelatihan yang menunjang softskill sebagai tanggung jawab intelektual, moral maupun sosial dalam peradaban yang terus berjalan.
Penulis adalah Ketua PMII Komisariat Kentingan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo 2018-2019; penulis buku 'Manifesto Cinta' (2017), dan 'Bola Fisika' (2018).