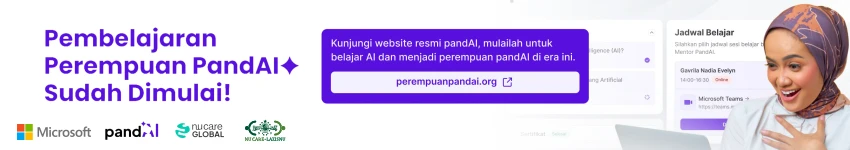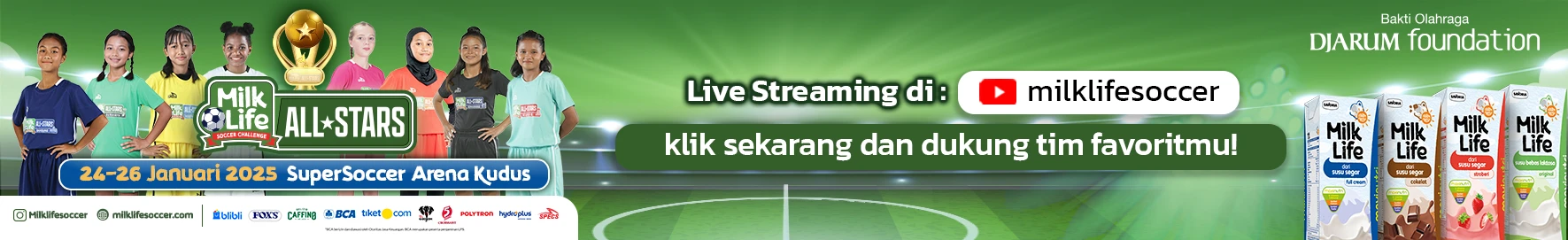Historiografi tentang Islamisasi Nusantara pada abad ke-14 sampai 16, biasanya dilakukan oleh para ahli arkeologi dan ahli bahasa–yang meneliti pelbagai macam teks ajaran Islam. Masalah utama yang biasanya dibahas adalah kapan Islam pertama kali memperlihatkan dampaknya. Islam di Jawa menyebar melalui Wali Songo, sembilan tokoh sakti Islam yang menyiarkan agama ini menurut tradisi Jawa. Ada banyak dongeng ihwal keajaiban yang mereka perlihatkan. Di antara Wali Songo, ada yang merupakan tokoh sejarah seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Ngampel. Namun ada juga yang hanya legenda dan diragukan apakah mereka memang ada.
Dari dongeng para wali itu selalu muncul kenyataan bahwa agama baru ini, yakni Islam lebih unggul sebagai kekuatan magis daripada agama yang lama (Buddha). Dari naskah agama Islam yang sampai pada kita dari zaman itu terungkap juga bahwa Islam yang menyebar ke Asia Tenggara adalah Islam Sufi yang berorientasi ke mistik. Menurut Michael Laffan, hanya Islam dalam bentuk mistik inilah yang dapat menyebar ke Nusantara (baca: Indonesia), karena cocok dengan alam rohani masyarakatnya.
***
Misteri peralihan agama di Nusantara dari abad ke-14 sampai 16 belum terpecahkan. Peralihan ini dapat dikatakan berlangsung singkat dan kokoh, sebab sampai kini agama Islam, bagaimanapun penghayatannya, adalah yang paling dominan di Indonesia. Selain itu, sejak Islam tersebar di Nusantara, agama memainkan peran politik yang lebih penting daripada sebelumnya. Memang dalam Pararaton dikisahkan tentang para brahmana yang meninggalkan Tunggul Ametung untuk mengakui Ken Arok sebagai raja. Namun bandingkan peristiwa tunggal ini dengan masalah yang dihadapi oleh Sultan Agung ketika menghadapi para ulama, atau yang lebih tragis lagi Sunan Amangkurat I, yang dikatakan membunuh ribuan ulama untuk menegakkan kekuasaannya.
Dalam setiap pemberontakan yang dihadapi oleh dinasti Mataram Islam dan ulamanya berperan, seperti dalam pemberontakan Trunojoyo (1678), Perang Diponegoro (1825-1830), gerakan ratu adil seperti di Cilegon (1882), ataupun Sarekat Islam yang menjadi bagian dari pergerakan nasional pada abad ke-20. Dalam kasus Perang Aceh (1872-1912) dan Perang Banjar (1859-1906) misalnya, Islam dan para ulamanya juga berperan besar.
Dari uraian di atas tampak peralihan agama jelas memiliki arti politis dan sosiologis yang dalam. Mendiang H.J. Benda dari Yale University, seorang sarjana yang ahli perihal Asia Tenggara dan Indonesia, mengajukan hipotesa bahwa perubahan agama di Nusantara dan di Asia Tenggara daratan terjadi pada zaman yang sama. Menurut saya, hipotesa Benda ini patut mendapat perhatian jauh lebih besar daripada kisah ajaib Wali Songo.
H.J. Benda melihat peralihan agama di Asia Tenggara dari Civa-Buddha, atau Buddha menurut istilah Jawa, ke Islam pada abad ke-14-16 tidaklah unik. Di daratan Asia Tenggara, kecuali di Malaysia, terjadi pula peralihan agama ke ajaran Buddha Theravada memiliki ciri yang lebih kerakyatan daripada ajaran agama sebelumnya, yang berkisar pada Brahmanisme, dimana brahmana-nya merupakan golongan pendeta yang bertugas melegitimasi konsep dewa-raja. Dengan kata lain, kaum brahman ini melihat ke atas atau ajaran mereka tidak berakar ke bawah, ke rakyat.
Baik Islam maupun Buddha Theravada memiliki konsep yang egalitarian, semua orang adalah sama di mata Tuhan, apakah ia raja, priyayi, atau rakyat biasa (wong cilik). Para ulama dalam agama Islam dan para biarawan (biksu/pongyi) dalam agama Buddha Theravada merupakan tokoh agama. Berlainan dengan kaum brahman, ulama maupun pongyi mengkritik atau sering menunjukkan sikap lebih kritis terhadap kewenangan raja. Lebih penting dari ini, ulama dan pongyi hidup di tengah rakyat dan menjadi tokoh di sana, sehingga dapat menjadi counter elite terhadap elite politik, yakni para pejabat kerajaan atau golongan priyayi.
Berlainan dengan priyayi yang tinggal di keraton atau di kota kabupaten, hal yang juga dilakukan oleh kaum brahman dahulu, para ulama dang pongyi lebih dapat menjadi saluran bagi keluhan rakyat. Seperti telah disebutkan di atas, banyak pemberontakan dipimpin oleh ulama atau pongyi. Pendek kata, menurut H.J. Benda, peralihan agama di Asia Tenggara pada abad ke-14-16 memberi perubahan struktural yang sangat penting, sebagai akibat dari krisis agama sebelumnya maupun krisis dalam hubungan antara raja dan rakyatnya.
Di daratan Asia Tenggara, krisis dewa-raja terefleksi dari runtuhnya Angkor di Kamboja kini. Di antara monumen peninggalan para dewa-raja di Asia Tenggara, tidak ada yang semegah, seagung, dan semonumental Angkorwat. Angkorwat ini tidak kalah bila dibandingkan dengan monumen sejarah lain, seperti piramida para Firaun di Mesir atau bangunan di Iran. Dengan sendirinya pembangunan Angkorwat ini merupakan beban bagi rakyat. Tetapi kita tidak mendengar apa-apa ihwal keruntuhan Angkorwat. Kemungkinan besar rakyat meninggalkan tempat tersebut karena melarikan diri dari beban penderitaan atau terjadi epidemi.
Tidak ada lagi pusat di Kamboja yang memiliki bangunan semegah Angkorwat pasca Brahmanisme diganti dengan Buddha Theravada. Ankorwat sendiri ditutupi hutan tropis yang lebat selama berabad-abad dan baru “ditemukan” oleh sarjana Prancis pada abad ke-19.
Kalau perubahan agama dari abad ke-14 sampai 16 disebabkan oleh dinamika masyarakat sebagai reaksi terhadap beban dari atas, lantas mengapa bukan agama Buddha Theravada yang menyebar di Nusantara dan kepulauan Asia Tenggara, melainkan Islam? Dalam hal ihwal ini Semenanjung Malaysia harus dilihat pula sebagai bagian dari kepulauan Asia Tenggara yang menganut Islam, yang tersebar sampai ke Luzon (Filipina Utara) dan di sekitar Manila sebelum Spanyol datang.
Masalah ini timbul justru karena struktur Buddha Theravada dan Islam maupun Katolik-Spanyol yang kemudian tersebar di Filipina Utara, menurut Benda, tidak banyak berbeda. Jawabannya adalah faktor geografis dan sejarah. Kepulauan Asia Tenggara sangat penting sebagai daerah perdagangan dan dari abad ke-14 sampai 16 perdagangan Islam adalah yang unggul.
Perdagangan itu berpusat di Gujarat, India, yang jatuh di bawah kekuasaan Islam. Perdagangan Islam ini menyebabkan timbulnya kerajaan Maritim di Sumatera Utara, seperti Piddie, Pasai, dan kemudian Aceh. Malaka, yang sudah merupakan pelabuhan penting sebelum rajanya masuk Islam dan bergelar Sultan Malaka, sengaja menarik perdagangan Islam.
Perlindungan militer dan politis karena ancaman Ayuthia (Siam) maupun Majapahit (Jawa) merupakan faktor dari perubahan agama di Malaka. Sejarawan O.W. Woters menunjukkan alasan konkret mengapa para maharaja Malaka masuk agama Islam, yakni untuk memperkuat kedudukan dagang dan politiknya. Memang, Malaka di bawah para sultannya yang Islam menjadi pelabuhan dan pusat imperium lautan yang terbesar di Asia Tenggara sampai 1512, ketika kerajaan maritim ini jatuh ke tangan Portugis. Sampai masa itu Malaka adalah pengganti Sriwijaya dan pendahulu Singapura di zaman modern.
Penyebaran Islam melalui pedagangan itu, bagi Nusantara, mengungkapkan masalah lain di samping masalah kerajaan dengan Brahmanisme-nya dan dinamika masyarakat, yakni konflik antara negara maritim dan negara agraris-pedalaman. Para sejarawan Belanda, semisal J.C. van Leur dan Bertram Johannes Otto Schrieke, sudah mengajukan pola pertentangan antara kedua struktur politis tersebut. Sriwijaya mewakili pola maritim melawan Mataram I di sekitar abad ke-9 sampai 10. Kerajaan-kerajaan pesisir yang Islam seperti Demak, Kudus, Tuban dan Giri Ngampel mewakili pola maritim. Hal yang sama juga terjadi antara pesisir utara melawan Mataram II (Senopati Sultan Agung) pada abad ke-16.
***
Singkat kata, penyebaran agama Islam ke Nusantara harus dilihat tidak saja karena konflik sosial antara kerajaan Brahman dan masyarakat, tetapi juga dari sudut persaingan antara pesisir dan pedalaman-agraris, antara kosmopolitanisme dan isolasionisme. Melalui pola pertentangan ini para sejarawan mencoba mendedahkan perubahan sosial, politik ataupun ekonomi yang terjadi.
Bagaimana dengan dongeng ihwal Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam? Zaman peralihan agama di mana pun juga selalu kacau, baik itu peralihan agama ke Islam, ke Katolik, atau ke Protestan. Perubahan itu selalu terkait dengan kisah-kisah ajaib. Yang terakhir ini adalah untuk memperkokoh kepercayaan dan penghayatan agama.
Dalam agama Kristen yang tersebar di Eropa, ada banyak cerita tentang kaum penyebar agama, orang suci, misalnya St. Patrick di Irlandia, St. George di Inggris yang membunuh naga, St. Wilibrodus di Belanda, St. Nicolas, atau St. Elizabeth yang melakukan hal-hal ajaib. Banyak di antara orang-orang suci itu, dalam usaha merasionalisasikan agama, kini mulai dikeluarkan dan tidak diakui oleh Gereja Katolik-Roma. Kendati demikian, usaha ini menimbulkan banyak protes dari umat Katolik, hal yang menunjukkan bahwa di Barat pun terdapat kesukaran untuk menyesuaikan rasio/ilmu dan kepercayaan dan penghayatan. Jadi, tidaklah mengherankan bila dalam penyebaran agama Islam di Jawa, ada pula kisah-kisah keajaiban Wali Songo.
Ketika menulis teorinya ihwal peralihan agama di Asia Tenggara, H.J. Benda mengambil contoh peran para biksu dalam melawan pemerintahan Ngo Dien Dhiem di Vietnam Selatan, peran para pongyi dalam pemberontakan Saya Sen di Myanmar pada 1930-an, dan peran para ulama dalam pemberontakan Cilegon (1882) di Nusantara. Para pemberontak dalam karya H.J. Benda itu gagal melawan negara.
Arkian, di masa kontemporer ini, agama sebagai jawaban masyarakat terhadap penindasan negara lebih relevan lagi, sebab kasus revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini terbukti dapat menggoncangkan negara totaliter modern Iran di bawah Syah Iran. Selama ini, ada kesan bahwa penindasan oleh negara dan perluasan campur tangan aparat dalam kehidupan masyarakat tanpa persetujuan masyarakat, yang merupakan gejala khas Dunia Ketiga, akan dijawab oleh masyarakat dengan revolusi liberal, sosialis, bahkan komunis. Padahal dari dahulu sampai kini jawaban masyarakat bisa juga melalui agama. Dengan kata lain, baik pada zaman kolonial maupun nasional, agama dapat menjadi unsur politis.
Penulis adalah alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyambut Idul Adha dengan Iman dan Syukur
2
Buka Workshop Jurnalistik Filantropi, Savic Ali Ajak Jurnalis Muda Teladani KH Mahfudz Siddiq
3
Lembaga Falakiyah PBNU Rilis Data Rukyatul Hilal Awal Dzulhijjah 1446 H
4
Khutbah Jumat: Relasi Atasan dan Bawahan di Dunia Kerja menurut Islam
5
Khutbah Jumat: Menanamkan Nilai Antikorupsi kepada Anak Sejak Dini
6
Ojol Minta DPR RI Tekan Menhub Revisi Dua Aturan soal Transportasi Online
Terkini
Lihat Semua