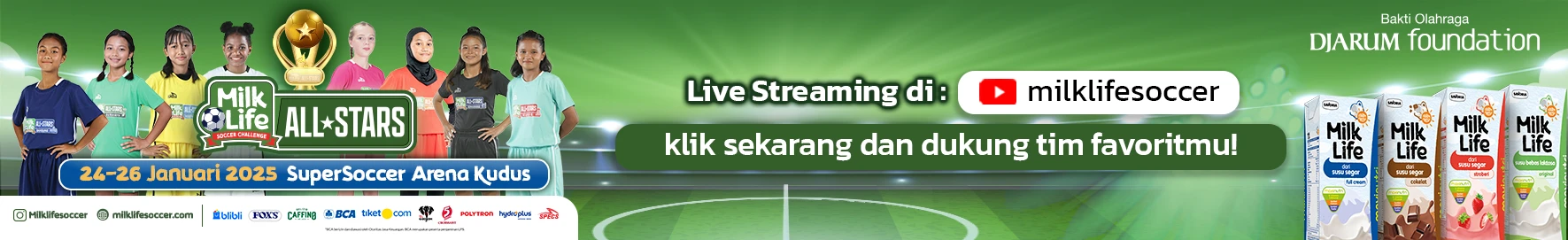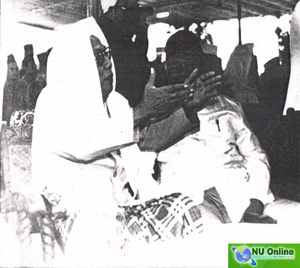Jakarta, NU.Online
Ketika gagasan pengembangan dan pembaruan pesantren dilakukan pada pertengahan 1980-an, beberapa persoalan penting pesantren ditinjau, sejak dari kurikulum, sistem pengajaran dan penjenjangan sampai durasi (jangka waktu) pendidikan. Selama ini pendidikan pesantren dinilai kurang efisien, sebab untuk menguasai suatu ilmu seseorang harus belajar sampai tua, ubanan, bahkan kemudian menjadi santri kelana yang mencari ilmu dari satu pesantren kepesantren lain, dalam kurun waktu yang cukup lama. Memang konsep thuluz zamani (durasi lama) merupakan prasyarat keberhasilan seseorang untuk menguasai keilmuan. Bahkan banyak di antaranya yang terlambat kawin, atau terus belajar padahal anaknya sudah besar, setelah merasa cukup atau karena dijemput orang tua atau mertuanya baru mereka pulang.
Lain lagi kisah KH Mudjib Ridwan Surabaya yang dikenal sebagai tokoh pencipta simbol NU, dia ini seorang santri kelana tulen, tidak ada pesantren penting di Jawa yang belum didatangi untuk meguru, apalagi pesantren besar seperti Tebuireng, Lirboyo, Langitan semua sudah dijamah. Namun suatu ketika ia kena batunya, ketika nyantri di pesantren Bangkalan pimpinan Kiai Khalil yang terkenal sangat ma’rifat. Mujib muda memang sudah lama nyantri di pesantren itu, yang sebenarnya hanya untuk menyepuh (mematangkan) ilmu.
<>Mengetahui motif si santri itu Kiai Khalil tidak kehilangan akal untuk mengusirnya, maka disuruhlah dia menyapu halaman pesantren bukan di pagi hari sebagaimana lazimnya, tetapi di siang bolong, saat halaman dalam keadaan bersih, tetapi karena perintah guru, maka ia menurut saja. Ketika sedang menyapu, Kiai Kholil berteriak, “Ada maling, kepung-kepung, itu dia di halaman, ayo tangkap.!”
Kontan santri yang mendengar seruan Kiai itu lari mengejar sang maling. Melihat dirinya dalam kepungan segera Ridwan lari tunggang langgang keluar masuk kampung agar tak terkejar, akhirnya naik dokar dan kemudian naik perahu menyeberangi selat Madura, menuju kampungnya di Surabaya. Orang tuanya kaget ketika melihat anaknya pulang secepat itu, lalu diceritakan kisahnya. Saat itu juga ayah Ridwan sowan ke Kiai Kholil untuk menanyakan kenapa anaknya diusir, maka Kiai Kholil dengan ringan menjawab, “ya dia itu memang maling karena sudah punya ilmu banyak, sudah alim tetapi masih mencuri ilmu saya, makanya saya usir untuk pulang”. Mendengar jawaban itu sang ayah sangat lega bahwa itu sebuah isyarat bahwa anaknya telah alim sudah saatnya berhenti mondok untuk mengajarkan ilmunya pada masyarakat.
Sebenarnya durasi atau jangka waktu pendidikan tidak perlu dikritik atau diubah secara drastis, sebab itu sudah merupakan mekanisme keilmuan pesantren yang memang butuh pendalaman dan kematanagan. Berbeda dengan disiplin keilmuan modern yang teknis, ilmu dzahiri (katon) yang mengenal asas efisien dan efektif, yang mengarah pada kedangkalan dan instan yang penting cepat terasa manfaatnya. Karena tradisi santri kelana itu tidak lain sebagai sebuah pendidikan pasca sarjana, kalau durasi pendidikan pesantren dikritik, kenapa pendidikan modern yang berlarut-larut berjenjang S1 hingga S3 yang sama-sama butuh waktu lama dan tidak efisien dibiarkan tanpa kritik, diterima sebagai kewajaran bahkan keharusan.
Pada dasarnya kaum pesantren menjadi ulama atau kiai besar setelah mereka menghayati keilmuannya secara mendalam dan menerapkan dalam tingkah laku. Ini sama persis yang dijalankan oleh para pangeran Jawa para calon raja, pada umumnya mereka adalah pelajar yang tekun, pengembara yang berpengalaman dan sekaligus petapa yang tangguh. Ada keseimbangan antara olahraga, oleh pikiran dan oleh rasa, agar menjadi orang yang sabar arif dan bijak.
Para pembaru pemikiran Islam selama ini memang sepenuhnya dikuasai oleh paradigma modernisasi, sehingga mengukur sesuatu dengan logikanya sendiri yang dianggap sebagai logika universal, dengan menafikan logika masyarakat lain yang lebih rasional, yang justru dengan kebijakannya sendiri mampu mengembangkan sistem keilmuan yang maju dan mandiri, yang memang prinsipnya bukan efisien dan efektif, tetapi kedalam dan keseriusan.
Maka yang perlu dikritik atau ditambahkan dari keilmuan tradisional, yang selama ini cenderung normatif, adalah ruang lingkungnya agar diperluas, mencakup dimensi sosial dan kesejarahan, agar keilmuan yang dikembangkan dinamis tidak hanya secara akademis tetapi juga secara sosiologi, untuk menumbuhkan komitmen sosial mereka agar bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Dari situ bisa diambil hikmahnya bahwa seseorang tidak lagi bisa mengukur perkembangan dengan logikanya sendiri, perkembangan dan logika tradisi perlu diapresiai, karena ternyata dalam kebuntuan sosial, tradisi yang bisa memberikan peganagan dan harapan (Bregas N A)
***