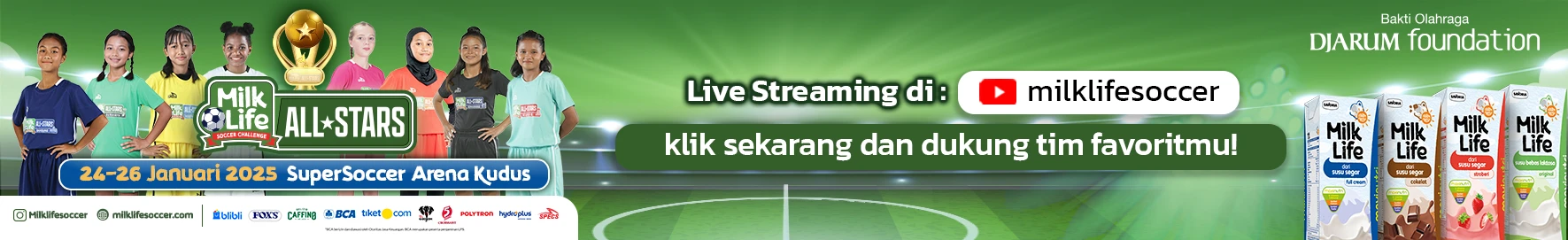Pendidikan modern dikiritik oleh kalangan akademisi karena memisahkan anak didik dari alam lingkungan, terutama dunia kerja di mana mereka berasal. Banyak anak nelayan, petani atau saudagar setelah bersekolah tidak bisa kembali ke habitatnya, karena setelah menerima citarasa pendidikan mereka tidak lagi kerasan dengan dunia lama yang menghidupinya. Hal itu tidak lain karena pendidikan diselenggarakan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan lapangan kerja yang ada.
Berbeda dengan pendidikan tradisional, lebih bisa berdialog dengan lingkungan, sehingga pendidikan pendidikan bukan harga mati. Tetapi terus-menerus dinegosiasikan dengan kondisi setempat, baik dalam penetapan kurikulum hingga pengaturan waktu. Karena pada dasarnaya pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan anak didik dalam mengkelola dunianya sendiri.
<>Di dunia pesantren misalnya jam pelajaran disesuaikan dengan jadwal kerja, dan musim tanam atau musim panen. Banyak santri yang sekolah tanpa bekal dari rumah, tetapi harus bekerja, karena itu pengajian diselenggarakan diluar jam kerja, seperti setelah subuh, setelah ashar atau pada malam hari. Demikian juga musim libur sekolah bukan tahun baru, melainkan berdasarkan musim tanam atau musim panen, sehingga santri kembali bisa bekerja di sawah atau ladang untuk mencukupi bekal sekolah mereka.
Pengalaman menarik yang dikembangkan di pesantren Plosorejo Nganjuk untuk mengikat para santri dalam dunia pertanian, maka sang kiai menetapkan metode sendiri. Setiap santri lelaki yang menikah disarankan berangkat dari pesantren dan semua santri beserta keluarga digerakkan untuk menjadi pengiring, baik jalan kaki, naik sepeda atau dokar. Semua para pengiring tidak memakai pakaian pesta, melainkan diharuskan memakai seragam petani, celana dan baju hitam, sedangkan kalangan wanita memakai kebaya biasa, semuanya tidak boleh berkerudung, tetapi harus memakai topi bambu. Kalau pengiring mencapai puluhan atau ratusan maka disewakan topi di pasar Kertosono, selama prosesi sang empunya topi mengawasi, baru setelah acara walimah usai topi dikembalikan untuk dijual lagi di pasar. Namun tidak sedikit dari pengiring yang terus membeli, sehingga sang pedagang topi beruntung mendapat uang sewa dan sekaligus dagangan laku, dan tidak kalah beruntungnya bisa mendapatkan makanan gratis selama pesta berlangsung.
Cara yang dilakaukan Kiai Abdul Fakih itu dimaksudkan agar para santri tidak malu terjun sebagai petani mengutamakan penguatan dasar ekonomi, agar menjadi orang yang mampu dan mandiri secara ekonomi, agar bisa mandiri secara pikiran dan sikap, apalagi pada zaman penjajahan Belanda semacam itu, kemandirian merupakan asas kebahagiaan dan kemuliaan. Dengan menekuni dunia kerja itulah santri dan pesantren bisa berkembang walaupun tanpa subsidi dari penjajah asing itu. Non kooperatif dengan penjajah merupakan sikap dasar pesantren karena mereka mandiri secara ekonomi.
Dengan cara itu diharapkan alumni pesantren tidak meminta-minta belas kasihan penjajah, baik untuk kehidupan pribadinya maupun untuk membangun sarana pesantrennya. Independensi pesantren ini bisa dijaga dengan baik terhadap intervensi penjajah, maupun intervensi pemerintahan otoriter pasca kemerdekaan, dengan demikian pesantren bisa menjadi basis perlawanan rakyat terhadap kedlaliman. (munim dz)***
Dikisakan oleh KH Masyhuri Ponorogo