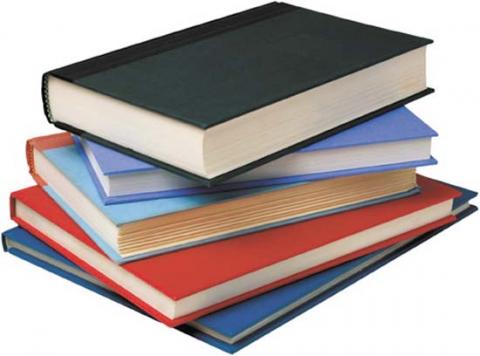Oleh: Najib Mubarok
Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang tidak biasa. Biasanya, suatu masalah timbul karena kebodohan. Namun, yang terjadi akhir-akhir ini permasalahan terjadi justru karena orang-orang berilmu, lulusan pendidikan tinggi.Timbul perdebatan-perdebatan tak berujung tentang akar masalah. Namun tidak ditemukan solusi dikarenakan masing-masing pihak menganggap dirinya paling benar.
Atau mungkin yang sebenarnya terjadi bukanlah demikian. Mungkin permasalahan-permasalahan yang timbul semuanya disebabkan karena kebodohan. Namun, tidak satu pun yang menyadari dirinya dalam kebodohan, orang bodoh yang bodoh akan kebodohannya.
Sebelum masa kerasulan Muhammad SAW, bangsa arab berada dalam kerusakan moral, ketidakadilan, bahkan penindasan dalam wujud perbudakan dan kepemimpinan yang lalim. Satu masa yang disebut zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Disebut zaman kebodohan tidak lain karena kerusakan-kerusakan yang terjadi adalah akibat ketidaktahuan. Di masa penjajahan, bangsa Indonesia sangat mudah diperalat menjadi boneka-boneka kolonial, diadu domba, diperbudak penjajah. Akar permasalahan paling utama adalah kurangnya wawasan, ketidaktahuan, minimnya informasi karena minimnya pendidikan.
Lalu, zaman pun berubah dan bergerak maju, dari kebodohan menuju keilmuan. Pendidikan sekolah tidak lagi menjadi barang langka, sebaliknya menjadi kwajiban bahkan kebutuhan. Wawasan dan akses informasi yang dahulu amat mahal, sekarang menjadi mudah atau bahkan terlalu mudah untuk didapatkan. Namun, semua seperti fatamorgana. Kemajuan-kemajuan dalam bingkai modernisasi di zaman ini seakan tidak menemukan tujuannya. Kita mengatakan zaman ini maju dalam keilmuan jauh dari kebodohan. Namun kerusakan-kerusakan yang terjadi di zaman kebodohan masih terulang, bahkan boleh jadi lebih rusak lagi. Jika dahulu kerusakan terjadi akibat ketidaktahuan, maka sekarang terjadi justru karena mengetahui dan bersengaja melakukan kerusakan. Mungkin bisa dikatakan, kerusakan yang terjadi dizaman ini dilakukan oleh mereka dengan pengetahuan dan wawasan luas, dilakukan dengan sengaja dan terencana, sangat sulit diperbaiki karena para pelakunya bersembunyi dalam kedok intelektualitas.
Dalam upaya perbaikan dengan disertai niatan introspeksi oleh setiap diri dari kita, hal pertama yang dapat diupayakan adalah menanyakan kembali pemahaman kita tentang ilmu dan semua variabelnya, menanyakan kembali sudahkah upaya-upaya kita dalam mengamalkan ilmu menemukan tujuannya. Setidaknya terdapat tiga hal yang sangat penting untuk kita renungkan lagi makna dan pemahamannya, cakupan dan tujuannya. Ilmu, ulama sebagai subjek ilmu, dan mu’allim sebagai pengemban amanat ilmu, perlu kita kaji ulang berdasarkan fakta-fakta praktik di lapangan. Dan tentu saja, disertakan pula firman Allah SWT dan sabda rasulullah SAW sebagai dasar pijakan berpikir.
Ada tiga nash Al-Quran dan Hadits yang saya gunakan dalam tulisan ini. Penggunaan nash Al-Quran dan Hadits tidak saya maksudkan untuk saya tafsirkan, karena saya mengakui tidak memiliki kemampuan cukup untuk menafsirkan. Penggunaan nash Alquran dan Hadits kita gunakan sebagai refleksi atas fakta pemahaman yang terjadi, sebagai parameter sudahkah pemahaman kita terkait ilmu dan variabelnya menemukan tujuan pensyariatannya. Terdapat hal menarik pada nash-nash yang disertakan dalam tulisan ini. Semuanya mengandung ‘adatul qashri “اِنَّمَا” yang memiliki arti “anging pestine” dalam bahasa Jawa.
Berkenaan dengan ilmu, saya teringat dengan cerita seorang teman saat dia hendak berangkat kuliah dan mendapat nasehat dari ayahnya, “Niatkan kuliahmu untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, lillahi ta’ala.” Cerita berbeda saya dapatkan dari salah satu teman saya yang lain saat berkonsultasi dengan keluarganya terkait rencana pilihan jurusan kuliahnya. “Kalau kamu ambil jurusan itu kamu mau kerja apa nanti?” Tanya sang ayah. Mungkin demikianlah yang saat ini dialami oleh kebanyakan dari kita. Kita mengalami degradasi standar nilai untuk memaknai sesuatu, terutama ilmu. Seakan-akan, ilmu dimaknai hanya dari sudut pandang potensi materialistisnya, peringkat nilai, ijazah, kemudahan kerja, kedudukan sosial dan kemapanan finansial. Terdapat sebuah hadits riwayat Imam Bukhari yang dapat kita gunakan untuk mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih baik tentang ilmu.
البخارى قال:قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: مَن يُرِد اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّههُ فِي الدِّينِ واِنَّمَا العِلمُ بِالتَّعَلُّمِ
Artinya: “Imam Bukhari berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang Allah kehendaki terhadapnya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam agama, dan bahwasannya ilmu itu diperoleh hanya dengan belajar.”
Ilmu dan belajar tidak dapat dipisahkan. Satu-satunya cara agar kita berada di jalan menuntut ilmu adalah dengan belajar, hanya dengan belajar. Belajar memiliki banyak dimensi. Membaca buku atau mendengarkan ceramah hanya bentuk formalnya. Belajar muncul dari kerendahan hati merasa bodoh. Karena merasa bodohlah seseorang mampu meniatkan diri belajar. Karena merasa bodohlah seseorang yang belajar tidak akan mungkin menemukan keangkuhan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, siapakah mereka orang-orang di belakang kedok intelektualitas yang dengan angkuhnya mudah memberi label salah dan sesat kepada sesamanya?.
Ilmu yang hanya bisa didapat dengan belajar mengajarkan kita berorientasi pada usaha dan proses menuntut ilmu, mengajarkan tidak adanya jalan pintas. Peringkat nilai, ijazah, gelar akademik, bahkan kedudukan dan pekerjaan dapat diperoleh dengan jalan pintas. Namun ilmu tidak.
Ulama sebagai subjek ilmu, pelaku dari suatu cabang ilmu. Dia yang ahli dalam ilmu ekonomi adalah ulama ekonomi. Dia yang ahli dalam ilmu matematika adalah ulama matematika. Dia yang ahli dalam ilmu tambal ban adalah ulama tambal ban. Dia yang ahli memungut sampah, yang dengan baju kumuh dan gerobak sampahnya ahli mengelola sampah, adalah ulama bidang ilmu persampahan.
Namun sepertinya, pemahaman tentang ulama di lapangan berkata lain. Ulama adalah sebutan bagi mereka yang ahli beretorika, yang memiliki keahlian menuai tepuk tangan dari setiap kalimatnya.
Seseorang disebut ulama hanya dilihat dari gelar dan kepintaran otaknya. Akibatnya, tidak sedikit ulama ilmu keuangan menjadi pelaku korupsi, tidak sedikit ulama ilmu kedokteran menjadikan orang sakit tidak lebih sebagai lahan ekonominya, tidak sedikit ulama -ulama yang menjabat di pemerintahan melupakan rakyatnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Fathir:28, sebagai berikut:
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالاَنْعَامِ مُخْتَلِفُ اَلْوَانُهً كَذَالِكَ اِنَّمَا يَخشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ العُلَمَآءُ اِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
Artinya: “Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Bahwasannya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun.”
Sangat menarik bagaimana Allah SWT menghubungkan antara ketakutan kepada-Nya dan ulama. Ulama menjadi manusia khusus dari hamba-hamba-Nya yang mampu merasa takut kepada Allah SWT. Satu-satunya yang mampu merasa takut kepada-Nya adalah ulama, hanya ulama. Ulama yang memiliki akar kata yang sama dengan ilmu, yang berasal dari kata dasar “mengetahui”. Dalam pengertian formal, mengetahui memang hanya terkait dengan hasil tangkapan indera dan otak. Namun dalam pengamalan dan implikasi-implikasinya, seorang berilmu diharuskan memiliki kontrol hati, kontrol laku, dan berujung pada ketaqwaan dan ketakutan kepada Allah SWT. Lalu, masihkah kita mampu untuk mengatakan kepada mereka dengan kepintaran dan gelarnya, yang menjadi oknum pejabat yang korup, menjadi oknum dokter pegawai bayaran, menjadi oknum pemimpin yang lali, sebagai orang yang berilmu?.
Mu’allim adalah orang yang mengajarkan ilmu, seorang pengajar, seorang guru. Mengajarkan ilmu adalah kwajiban, amanat bagi siapapun sebagai wujud mengamalkan ilmu. Mu’allim adalah sifat yang melekat bagi siapapun, karena setiap orang memiliki kwajiban mengajarkan ilmu sesuai kadar ilmu yang dipunyai. Namun seiring perubahan zaman, makna mu’allim pun bergeser maknanya. Mu’allim yang semula bermakna sifat yang merupakan amanat, berubah menjadi satu profesi menjanjikan, satu profesi yang menjamin kemapanan finansial dan kedudukan sosial. Tentu saja, masih banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pengajar dan tetap berorientasikan pada penyampaian alanat ilmu. Namun, tidak sedikit pula yang menjadikan mengajar sebagai formalitas dalam rangka kegiatan ekonomi. Hadits riwayat Imam Bukhari berikut ini dapat kita jadikan pembelajaran tentang kearifan seorang yang mengajarkan ilmu.
عن معاوية قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: مَن يُرِد اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّههُ فِي الدِّينِ واِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعطِى...
Artinya: “Dari Muawiyah berkata: saya mendengar nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang Allah kehendaki terhadapnya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam agama. Dan bahwasannya saya hanyalah pembagi, Allah yang memberi...”
Rasulullah SAW memberikan teladan bagaimana semestinya seseorang mengajar. Hal terpenting untuk diperhatikan oleh seorang pengajar adalah kwajiban dalam menyampaikan amanat ilmu, hanya itu. Bahkan, bukan menjadi tanggung jawab seorang pengajar kepahaman mereka yang diajar. Tanggung jawab utama dari seorang pengajar adalah mengajar semaksimal mungkin. Dan tentu saja tidak semestinya, seorang pengajar menjadikan faktor ekonomi sebagiai orientasinya.
Seakan sudah menjadi suatu keniscayaan, mereka dengan pengetahuan dan kecakapan berfikir yang baik akan menempati kedudukan penting dalam kehidupan, posisi-posisi penting yang menjadi garda depan kehidupan. Tentu sangat disayangkan, jika mereka yang berada di garda depan tidak benar-benar berilmu, tidak benar-benar ulama, dan tidak benar-benar mampu memberi keteladanan ilmu. Mungkin sudah terlambat untuk berharap pada zaman saat ini. Namun, kita masih bisa berharap pada generasi muda, generasi berikutnya yang kita semogakan mampu benar-benar berilmu dengan segala
cakupannya. Semoga kelak negeri ini berjalan maju dipimpin oleh mereka para ulama sejati dengan semua kelengkapan moralnya. Semoga kelak generasi-generasi ulama sejati akan terus berlanjut secara kontinu karena terus diwariskan oleh para mu’allim dari generasi ke generasi.
*
Penulis adalah dosen Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam NU (STAINU) Temanggung
Terkait
Terpopuler
1
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
2
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
3
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
4
PBNU Terima Audiensi GAMKI, Bahas Isu Intoleransi hingga Konsensus Kebangsaan
5
Kick Off Jalantara, Rais Aam PBNU Pimpin Pembacaan Kitab Karya Syekh Abdul Hamid Kudus
6
Kisah Di Balik Turunnya Ayat Al-Qur'an tentang Tuduhan Zina
Terkini
Lihat Semua