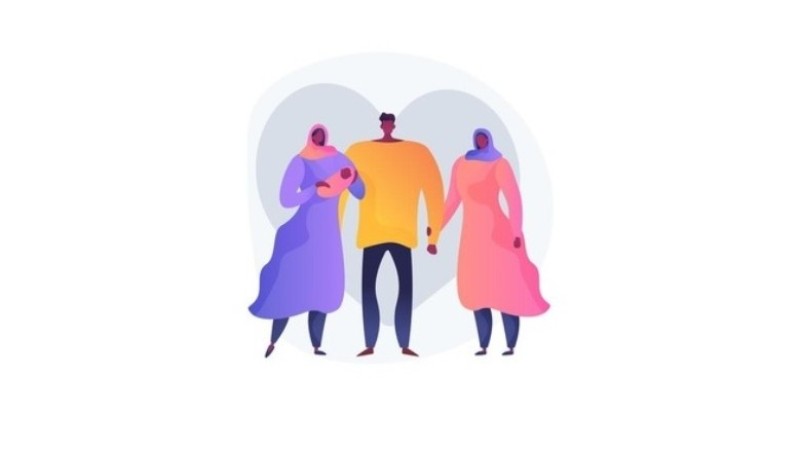
Penurunan angka poligami di kalangan NU itu berbarengan dengan meningkatnya peran para perempuan di lingkungan pesantren sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.
Muhyidin Basroni
Kolomnis
Dalam beberapa perkumpulan bersama bapak-bapak muda yang berlatar belakang NU sekaligus pesantren, baik melalui jumpa nyata maupun maya, ada satu hal yang saya perhatikan. Hal tersebut adalah tema poligami yang kerap sekali dijadikan sebagai bahan lelucon. Dengan segala macam kata turunannya mulai dari matsna, ta’addud, azwaja, wayuh, sampai ‘buka cabang’, tema ini tidak habis dijadikan bahan lucu-lucuan. Pertemuan langsung, telekonferensi, layar media sosial, hingga grup obrolan online, semua tidak lepas dari candaan bertema itu.
Lelucon ini di mata saya lebih serupa bualan. Saya sebut bualan karena umumnya yang sudah sejak dulu suka melempar lelucon perihal poligami ini sekalipun, sampai bertahun-tahun juga tidak kunjung terkonfirmasi mempraktikkannya. Mungkin karena ada keinginan namun tidak keturutan, maka berwacana saja alias omong kosong kemudian dipilih menjadi jalan menghibur diri. Kalau tidak bisa mempraktikkan, paling tidak bisa membual tentang perkara ini.
Soal apa alasan yang bersangkutan ingin mempraktikkan poligami, tulisan ini tidak akan membahasnya. Apakah juga sebenarnya yang bersangkutan itu benar-benar ingin poligami atau hanya sekadar murni bercanda, tulisan ini tidak hendak membahasnya. Pun bagaimana sikap pribadi pengarang tulisan ini sendiri terkait isu dimaksud, tulisan ini tidak berani membahasnya.
***
Oke. Dalam bualan yang saya maksud tadi, salah satu narasi utama humornya adalah keinginan laki-laki melakukan poligami namun dibarengi ketatnya kontrol sang istri. Humor berlanjut ke olok-olok tentang siapa yang paling penakut dan istri siapa yang paling galak. Lalu muncullah beragam julukan bagi para suami, mulai dari imamul kha’ifin (pemimpin para penakut), sayyidul kha’ifin (penghulu para penakut), sulthanul khoi’ifin (sultannya para penakut) sampai malikul kha’ifin (rajanya para penakut). Para istri pun tak kelewatan, ikut dijuluki dengan nama-nama jabatan kepolisian atau militer.
Seorang teman pernah menggelari saya sebagai khadimul kha’ifin (pelayannya para penakut). Benar-benar payah! Sudah dimasukkan ke golongan penakut, jadi pelayan pula. Saya yang merasa segagah ini sudah barang tentu tidak terima dianggap begitu. Yang pasti, dalam lalu lalang celoteh humor soal poligami ini, saya juga ikut arus untuk terlibat melempar lelucon dan olok-olok ke sesama teman. Tapi ya itu, yang saya lakukan ini sudah sepengetahuan dan seizin istri.
Dalam hati, sebenarnya ada rasa risih dengan lucu-lucuan seperti ini, karena dilontarkan dalam keadaan para perempuan bisa ikut menyimaknya. Bahkan di antara para perempuan itu terdapat pasangannya sendiri. Pasti dalam benak mereka terpikir betapa maskulin, patriarkis, misoginis atau seksis sekali guyonan macam ini. Saya yakin banyak perempuan yang tidak menghendaki si suami memadunya. Saya yakin juga para perempuan itu tidak mau untuk harus menjadi galak dulu agar pasangannya tidak melakukan hal itu.
Hmmm. Apa malah itu disengaja? Guyonan itu secara sengaja terus-menerus dilempar supaya diketahui istri, lalu sang istri makin lama luluh dan akhirnya menawari, begitu? Halah! Maunya!
***
Sebenarnya istilah poligami itu merujuk kepada praktik di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki pasangan lebih dari satu. Kalau laki-laki punya istri lebih dari satu, istilahnya poligini. Kalau perempuan punya suami lebih dari satu, istilahnya poliandri. Ini bukan hasil googling, ya. Ini benar-benar dari ingatan saya atas pelajaran sosiologi di sekolah waktu itu. Namun kenapa istilah poligami di lingkungan kita lebih dimaknai sebagai praktik laki-laki memiliki istri lebih dari satu? Menurut saya, ini karena dalam Islam yang dilegalkan hanya poligini bukan poliandri, sehingga poligami ya lebih dimaknai sebagi poligini itu sendiri.
Baik. Paragraf di atas cuma selingan, tapi penting untuk saya utarakan.
Lantas, soal fenomena poligami di kalangan NU sendiri menurut beberapa teman mengobrol memang menunjukkan penurunan. Ini tentu amatan sekadarnya, tidak disokong oleh data statistik melalui penelitian. Seorang kiai muda NU yang saya kenal dan meyakini kebenaran fenomena ini bahkan sampai bercanda kalau ia ingin pindah ormas saja.
Kiprah Perempuan yang Meningkat
Beberapa waktu yang lalu, saya berada dalam sebuah perjalanan dalam satu mobil dengan beberapa kiai muda NU yang semuanya mengasuh pesantren. Dari awal perjalanan sampai tujuan yang jarak tempuhnya lebih dari satu jam itu, obrolan dan canda didominasi oleh tema apa lagi, kalau bukan poligami. Serang-menyerang antara satu penumpang mobil dengan yang lain, yang semuanya pelaku monogami, berjalan begitu asyik.
Sampai saat pembicaraan soal poligami menjadi lebih serius tanpa ada gelak tawa lagi. Dalam keseriusan ini kami menginsyafi bahwa penurunan angka poligami di kalangan NU itu berbarengan dengan meningkatnya peran para perempuan di lingkungan pesantren sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Dari urusan pendidikan sampai pilihan warna cat bangunan di dalam pesantren, kini para bu nyai dan ning bukanlah sekadar sebagai penonton lagi, bukan sekadar kanca wingking (teman di belakang) lagi bagi para pak kiai dan gus.
Dalam berorganisasi pun, saya sendiri menyaksikan bahwa gerak para perempuan NU kian hari kian meningkat. Mereka yang mengasuh pesantren atau yang tidak, yang berkecimpung di kegiatan keagamaan atau tidak, semakin aktif dalam organisasi baik yang terafiliasi dengan NU secara struktural maupun kultural. Tidak hanya di organisasi lama, mereka juga aktif di organisasi-organisasi baru yang mereka bentuk.
Pembicaraan dalam mobil tadi mengandung kesimpulan bahwa kemungkinan besar, dalam konteks NU sekaligus pesantren, antara turunnya angka poligami dengan meningkatnya peran perempuan itu saling berkaitan. Kesimpulan ini jelas cuma kira-kira, benar maupun tidaknya perlu diuji melalui penelitian ilmiah. Saya sendiri punya pikiran kalau makin kompleksnya tuntutan zaman bagi hidup seorang laki-laki, tak terkecuali dari kalangan NU, membuat pikirannya tentang poligami makin teralihkan, sehingga angkanya pun makin turun.
Lalu suasana mobil sempat hening sejenak, entah karena semua sedang merenung atau meratap atau apa, saya tak tahu. Sepersekian waktu kemudian, saya memecah kesunyian. Saya bilang kalau generasi NU kita masih bisa membicarakan meski tidak melakukan, mungkin generasi NU mendatang bahkan untuk membicarakannya saja tidak bisa. Satu mobil kemudian bisa tertawa dan ceria kembali.
***
Nah. Kalau bicara tentang ingin atau tidak ingin, hati orang siapa yang tahu. Tapi kalau bicara berani atau tidak berani, kiranya peribahasa ‘tong kosong nyaring bunyinya’ atau ‘air beriak tanda tak dalam’ masihlah relevan digunakan. Sepengamatan saya, laki-laki yang saya kenal dan terkonfirmasi melalui informasi A1 sudah mempraktikkan poligami, malah kalem saja tanpa bualan dan olok-olok.
Tapi yang paling lucu tetap teman saya, orang NU yang satu ini. Dia berminat poligami dan ingin melakukannya secara baik-baik yaitu dengan sepengetahuan istri. Ia menyampaikan keinginannya ke istri dan sang istri ternyata tidak mempermasalahkan! Bahkan pernah suatu ketika saat ketemu bersama, ia terang-terangan bilang ke saya, di depan istrinya, minta tolong dicarikan! Tapi, sampai detik ini ia masih belum berhasil mewujudkan keinginanya, karena nyatanya belum ada yang mau. Rupanya sang istri sudah paham betul sejauh mana ‘marketability’suaminya itu.
Muhyidin Basroni, pengajar di UNU Yogyakarta dan IKANU Training Center
Terpopuler
1
Sosok Nabi Daniel, Utusan Allah yang Dimakamkan di Era Umar Bin Khattab
2
3 Pesan Penting bagi Pengamal Ratib Al-Haddad
3
Mimpi Lamaran, Menikah, dan Bercerai: Apa Artinya?
4
Mahfud MD Ungkap Ketimpangan Struktural Indonesia
5
Gus Yahya: Di Tengah Ketidakpastian Global, Indonesia Harus Bertahan dan Berkontribusi bagi Dunia
6
Tak Bisa Dipisahkan, Mahfud MD: Hukum yang Baik Lahir dari Politik yang Bagus
Terkini
Lihat Semua










