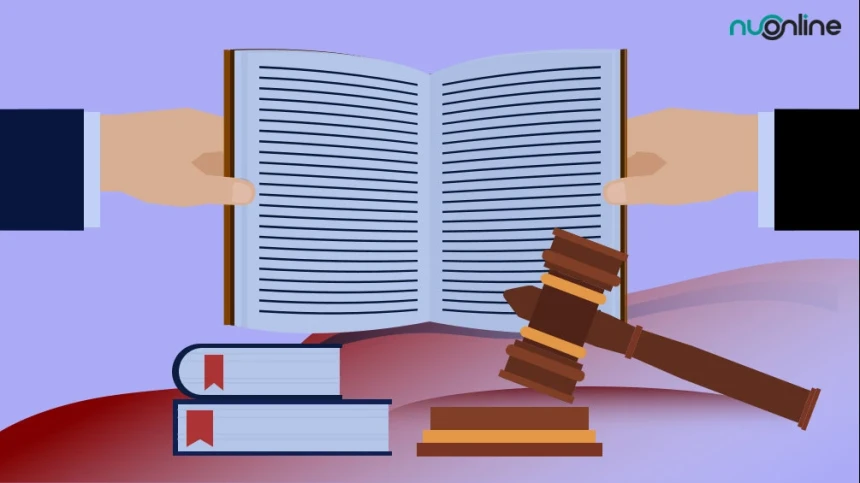Kritisi KUHP, Ahli Pidana: Siapa yang Sebetulnya Mau Dilindungi
NU Online · Kamis, 8 Desember 2022 | 12:00 WIB
Syifa Arrahmah
Penulis
Jakarta, NU Online
Ahli pidana Setya Indra Arifin memberi catatan kritis atas pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).
Ia menilai terdapat unifikasi (penyatuan) hukum sebagai problem mendasar proyek pembentukan hukum nasional. Atas problem tersebut, kepentingan hukum apa dan siapa yang sebetulnya hendak dilindungi oleh KUHP.
“Jika hendak dikategorikan ke dalam beberapa figur di balik materi muatan KUHP ini, yakni individu, masyarakat, dan negara, pertanyaannya lantas kepentingan hukum ini untuk individu, masyarakat, atau negara,” kata Indra, sapaan akrabnya, kepada NU Online, Kamis (8/12/2022).
Lantas, lanjut dia, jika ukuran yang paling dapat diterima dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan/tindak pidana dan perbuatan lainnya bukan merupakan tindak pidana adalah terletak pada soal kepentingan hukum yang hendak dilindungi secara layak atau pantas, siapa yang sebenarnya paling layak?
“Jika memang ketiganya memang perlu untuk mendapat perlindungan, apakah KUHP telah mampu menyeleraskan pergolakan ketiga kepentingan dimaksud dalam pasal-pasal yang hendak diaturnya,” ucapnya.
Seperti diketahui, sidang paripurna pengesahan UKHP menjadi undang-undang sempat diwarnai adu argumen. Terdapat beberpa pasal yang dinilai kontroversial, salah satunya, bunyi pasal 240, menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.
Publik menilai pasal tersebut sebagai pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki.
Kemudian pasal 218: setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda Rp 200 juta.
Kedua pasal tersebut dikhawatirkan akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin masa depan dan akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.
Hal itu yang membuatnya berpikir bahwa pengambilan keputusan menjadikan KUHP sebagai Undang-Undang tidak cukup tepat jika dikatakan sebagai dekolonialisasi. Meski faktanya para petinggi negeri ini sangat ingin lepas dari kolonialisasi, tetapi kenyataannya sistem hukum yang diterapkan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, hari ini juga dipakai oleh mereka.
“Jika hendak jujur, cara berhukum di negara kita jelas merupakan peninggalan nenek moyang bangsa-bangsa penjajah,” jelas Dosen Bagian Pidana, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.
Atas dasar itu, ia berpandangan bahwa KUHP masih memerlukan evaluasi mendalam terkait bagaimana menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang saling berkelindan dan layak dilindungi, termasuk bagaimana menempatkan posisi seorang penguasa di hadapan warga negaranya.
Menurutnya, jika Presiden dan Wakil Presiden atau Lembaga Negara misalnya, berkepentingan untuk dilindungi martabatnya dengan melarang penghinaan terhadapnya, tentu hal itu dapat dianggap wajar dari sisi kepentingan nasional/negara (terlepas dari perkembangan terakhir soal putusan MK yang menguji pengaturan ini).
Namun, tambah dia, justru bermasalah jika delik penghinaan ini hendak ditempatkan dalam delik aduan, sebab bertentangan dengan asumsi dasar adanya delik pengaduan itu sendiri.
“Atas maksud pengaturan pasal ini jelas bahwa kepentingan negara lebih kental dalam perumusan ketentuan pidana ini,” tegas Indra.
Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Syakir NF
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua