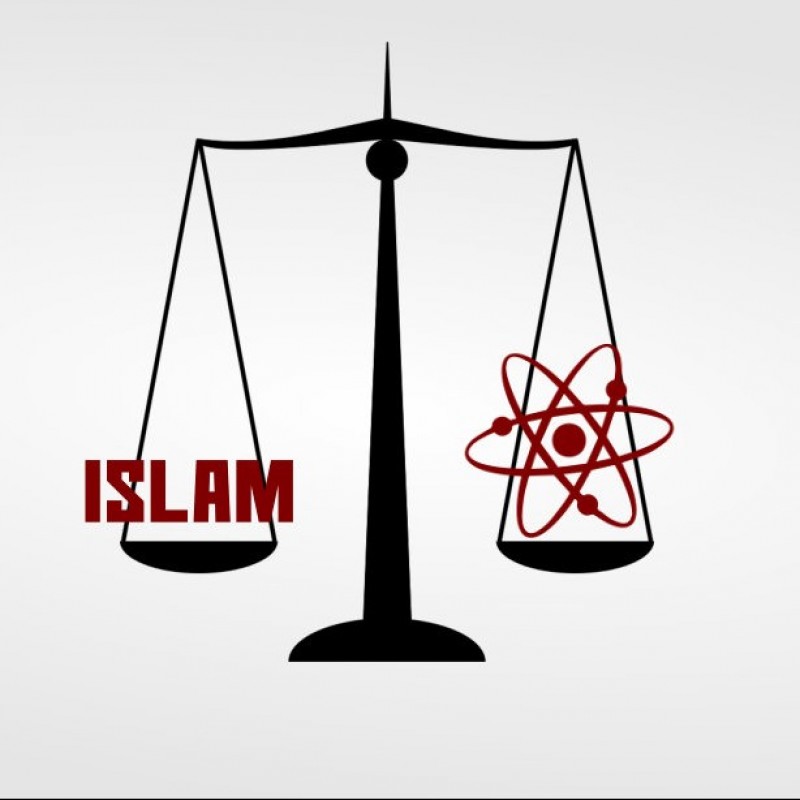Di tengah masyarakat, mungkin masih ada individu yang mempunyai idealisme seperti Sayidina Abu Bakar As-Shiddiq, yakni sahabat Nabi Muhammad SAW yang jujur, tegas, amanah, dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada ambisi dan kepentingan pribadi dan kelompoknya, terutama dalam hal pengelolaan negara dan birkorasi yang ada di bawah naungannya. Sayangnya, yang terjadi seringkali hanya praktik oligarki.
Ironi pengelolaan negara dan birokrasi yang tujuan utamanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak justru yang terjadi ialah upaya melanggengkan kepentingan-kepentingan kelompok kecil dalam wadah partai politik. Bahkan tidak jarang setelah tampuk kekuasaan diraihnya, mereka memikirkan langkah-langkah untuk meraih kekuasaan pada periode selanjutnya.
Tidak aneh jika negara hanya dikuasai segelintir kelompok yang mempunyai basis kuasa dalam bidang ekonomi dan media. Gerakan civil society yang mempunyai basis sosial-masyarakat dicampakkan begitu saja perannya dalam mengelola negara sehingga mereka acapkali hanya dijadikan lumbung suara dalam pemilihan umum. Inilah di antara pemahaman praktik oligarki di dalam perpolitikan Indonesia.
Pemandangan praktik oligarki terlihat jelas dalam mengelola ibu kota negara, Jakarta. Bagaimana mungkin kursi wakil gubernur dibiarkan kosong selama lebih dari satu tahun? Sedangkan perannya sangat dibutuhkan dalam melayani masyarakat. Tentu saja tawar-menawar politik antarpartai pengusung belum mencapai kesepakatan sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat. Di sini terlihat mereka hanya mementingkan kuasa kelompoknya sendiri ketimbang kepentingan masyarakat secara luas.
Persoalan tersebut juga terjadi dalam level pengelolaan negara. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, dalam paradigma Machiavellian, negara acap menggunakan segala cara demi mengamankan kekuasaan dan otoritasnya lewat semua instrumen yang ia miliki: modal, media, juga legitimasi institusi ilmu pengetahuan.
Situasi tersebut makin runyam ketika negara juga bersekutu dengan kelas oligarki. Dalam konteks Indonesia, itulah yang terjadi sepanjang era Orde Baru dan masih terdapat sisa-sisanya hingga sekarang, di era reformasi. Di era reformasi, sosok idealisme seperti sahabat Abu Bakar pun akhirnya ‘membusuk’ karena tenggelam dalam kepentingan kelompok oligarki dan oknum-oknum penghamba kekuasaan.
Belajar dari Gus Dur
Masyarakat Indonesia tentu mengetahui viralnya buku Menjerat Gus Dur (Desember, 2019) karya anak muda jurusan Pendidikan Sejarah jebolan Universitas Negeri Jakarta, Virdika Rizky Utama. Oknum-oknum penjerat Gus Dur untuk lengser dari jabatan Presiden sebelumnya mungkin telah banyak dikaji. Namun, buku Virdika menyajikan dokumen autentik yang menjelaskan oknum dan kelompok yang telah melakukan upaya pelengseran Gus Dur secara politis.
Dalam program Kick Andy edisi 15 November 2007, Gus Dur menegaskan, sejarah akan membuktikan bahwa dirinya dilengserkan secara politis karena secara hukum tidak pernah terbukti bersalah. Kelompok oligarki yang disebut dalam buku Menjerat Gus Dur berhasil “membujuk” Megawati untuk hadir di Sidang Istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001 guna menjungkalkan Gus Dur, sahabat yang justru sudah mendukung dan melindungi Megawati dari jeratan rezim Soeharto. Dokumen pelengseran Gus Dur yang ditemukan oleh Virdika membuktikan pernyataan Gus Dur di dalam acara talkshow tersebut.
Lebih dari menjelaskan oknum-oknum yang melengserakan Gus Dur dengan berbagai macam cara, buku Menjerat Gus Dur juga upaya perlawanan terhadap oligarki politik yang selama ini juga menjerat kehidupan sosial-masyarakat melalui kepentingan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan semangat Gus Dur yang menjadi icon perlawanan oligarki pada masa rezim Orde Baru Soeharto.
Politik Gus Dur dan politik NU secara umum ialah politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan politik yang penuh dengan etika. Ketiga konsep politik ini digagas oleh Almaghfurlah KH MA Sahal Mahfudh sebagai politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah). Roda pengelolaan negara ini harus diperkuat dengan prinsip kebersamaan dari seluruh elemen bangsa. Upaya tersebut juga harus seiring dengan langkah konkret mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan persamaan di hadapan hukum. Inilah yang ditekankan Gus Dur, selain humanisme dan prinsip-prinsip kesalehan sosial dan intelektual.
Sebagai seorang santri sekaligus ulama pesantren yang lekat dengan seluruh lapisan kehidupan masyarakat, Gus Dur mengajarkan orang-orang untuk berani dan kritis serta tidak apolitis terhadap kehidupan bernegara. Karena dalam masyarakat yang apolitis, persekutuan antara negara dengan para oligarkh dapat menyebabkan persoalan genting yaitu sulitnya membentuk pergerakan progresif yang mampu memobilisasi massa atau, minimal, menawarkan wacana politik alternatif.
Lebih-lebih secara mendasar tidak semua mobilisasi dapat berhubungan langsung dan mampu menjawab problem dan kontradiksi yang terjadi di masyarakat. Pada masa Orde Baru, Gus Dur membentuk wadah Forum Demokrasi (Fordem) yang didirikannya pada 1991 setahun setelah Soeharto dan pendukungnya mendirikan ICMI. Gus Dur ingin menegaskan identitas bangsa Indonesia dalam wadah tersebut.
Pembentukan Forum Demokrasi bagi Gus Dur bukan hanya sekadar membentuk ‘parlemen jalanan’, tetapi juga upaya mobilisasi politik tingkat tinggi dengan basis material yang kokoh, yakni pemetaan jaringan yang berisi masyarakat dan para intelektual dengan ‘warna-warni’ yang berbeda dengan pencanangan target perbaikan kehidupan sosial-politik. Gus Dur melakukan langkah strategis tersebut, sebab hanya dengan seperti itulah bangsa Indonesia dapat memenangkan pertarungan atas ruang politik yang telah terkontaminasi kepentingan oligarki.
Penulis adalah Redaktur NU Online
Terpopuler
1
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
2
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
5
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
6
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
Terkini
Lihat Semua