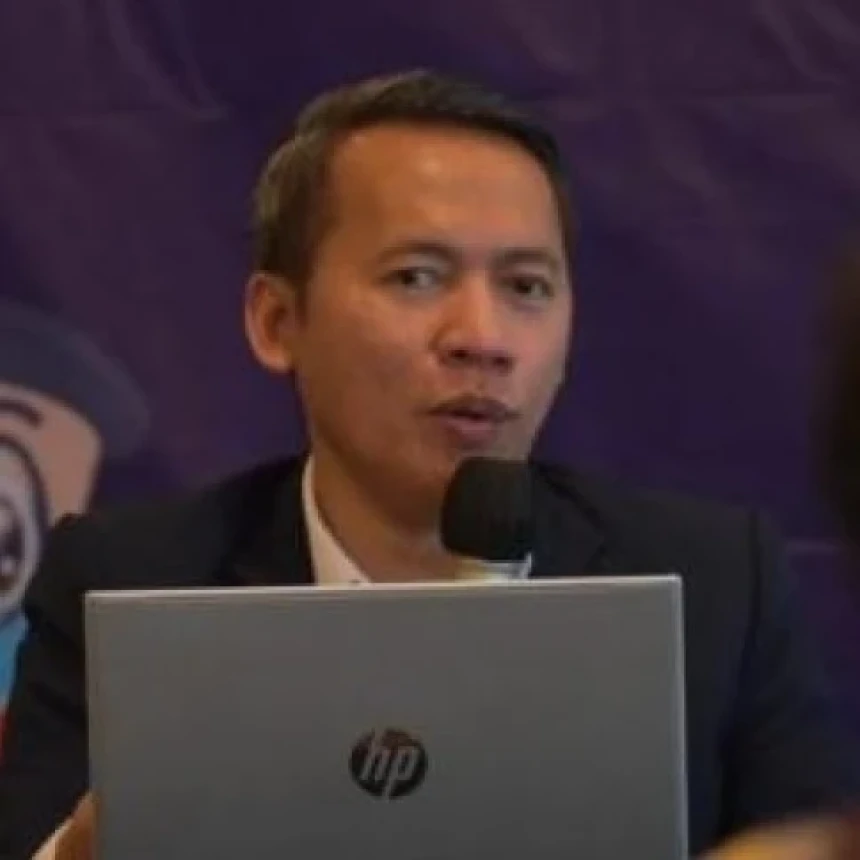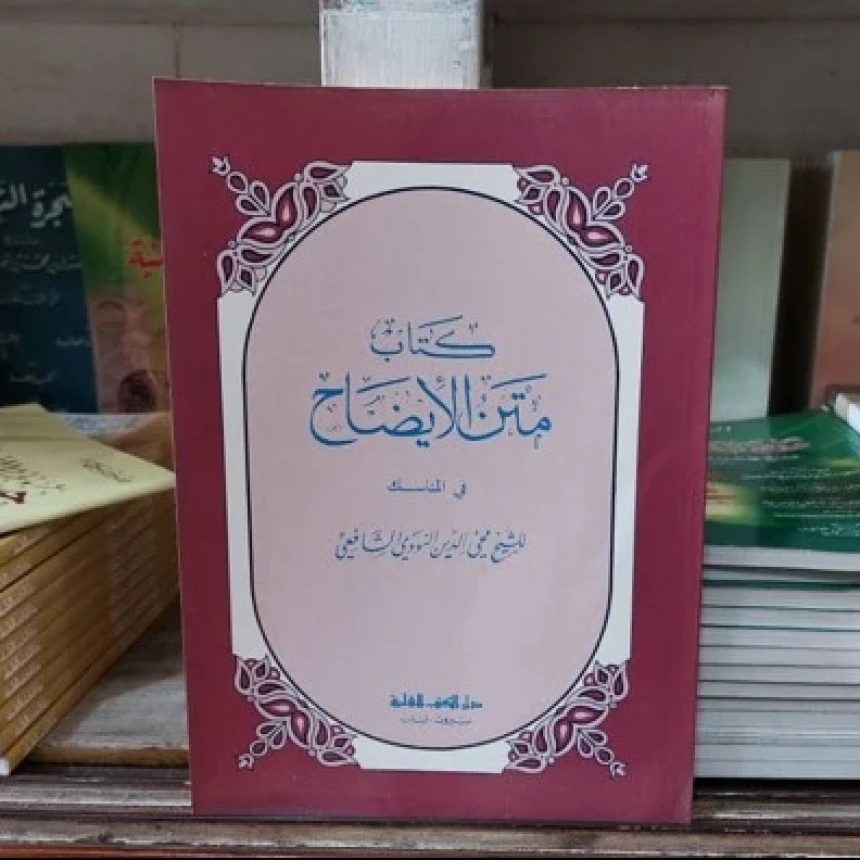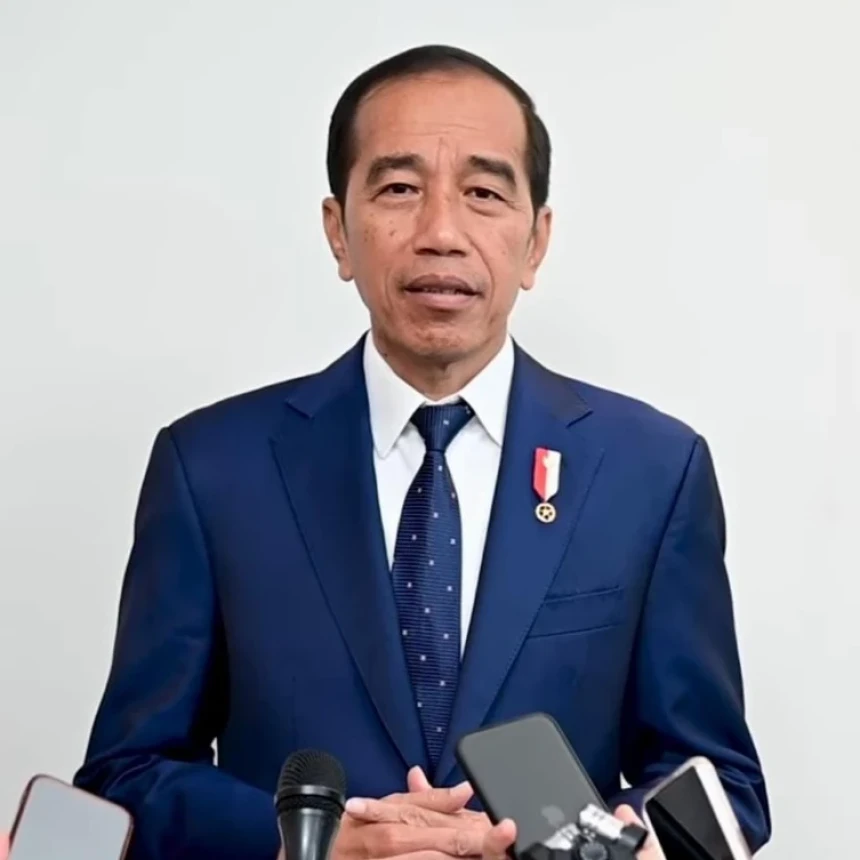Pada penyelenggaraan haji tahun 2025 ini, saya mendapat kehormatan bertugas sebagai bagian dari Mustasyar Diny, yakni konsultan ibadah yang tergabung dalam struktur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Saya bersama sejumlah ulama dan tokoh agama lainnya bertugas memberikan bimbingan manasik, pendalaman fiqh, serta pertimbangan keagamaan kepada jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Pengalaman ini memberi saya kesempatan menyaksikan langsung denyut pelayanan haji di lapangan; mulai dari tenda di Mina, padatnya jalur thawaf di Masjidil Haram, hingga situasi kritis seperti di Muzdalifah dan Arafah. Saya menyapa para jamaah lansia, mendengar keluhan soal fasilitas, serta melihat bagaimana para petugas berjuang keras menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah. Di tengah kompleksitas ini, saya menyadari bahwa penyelenggaraan haji bukan semata urusan teknis, melainkan ibadah besar yang menuntut ketepatan tata kelola, empati, dan akuntabilitas.
Refleksi itu terasa semakin kuat ketika saya mencermati wacana yang kini mengemuka: penggabungan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) ke dalam Undang-Undang Badan Pengelola Keuangan Haji (UU BPKH). Gagasan ini patut dikritisi secara serius, karena menyatukan dua fungsi yang sejatinya berbeda dan tidak seharusnya dipaksakan dalam satu wadah hukum.
RUU PIHU mengatur aspek-aspek pelayanan ibadah haji secara langsung: dari pendaftaran, bimbingan, pemondokan, konsumsi, kesehatan, transportasi, hingga perlindungan hukum jamaah. Ini adalah domain eksekusi publik yang memerlukan kelincahan, kedekatan dengan lapangan, dan keputusan yang cepat. Sementara BPKH adalah lembaga keuangan yang mengelola dana haji dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan optimalisasi nilai manfaat. Kedua ranah ini sama-sama vital, tetapi tidak memiliki titik temu operasional yang dapat disatukan begitu saja.
Apabila RUU PIHU digabungkan ke dalam UU BPKH, dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan mandat kelembagaan. Ketika pelayanan ibadah terganggu, siapa yang akan bertanggung jawab? Dan ketika Dana Abadi Umat terancam, apakah dana tersebut dapat didahulukan untuk memenuhi kebutuhan darurat jamaah? Dalam kenyataan di lapangan yang saya saksikan, keputusan sering kali harus diambil dalam hitungan menit, bukan menunggu proses administratif yang panjang dan rigid.
Padahal, RUU PIHU sudah mengarahkan pada penguatan kelembagaan tersendiri. Dalam rumusannya, disebutkan bahwa penyelenggara haji adalah “Menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan ibadah haji dan umrah.” Hal ini membuka jalan hukum untuk membentuk lembaga khusus, baik dalam bentuk Kementerian maupun Badan yang memiliki kewenangan penuh atas pelayanan jamaah haji, dengan struktur, anggaran, serta sumber daya manusia yang sesuai dengan kompleksitas ibadah haji.
Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong efisiensi birokrasi serta pemisahan fungsi kelembagaan. Di banyak negara dengan jumlah jamaah haji yang besar, urusan haji ditangani oleh lembaga atau kementerian khusus. Oleh karena itu, Indonesia sudah saatnya untuk mengambil langkah serupa, bukan malah menarik mundur dengan meleburkan pelayanan ibadah haji ke dalam kerangka pengelolaan keuangan.
RUU PIHU juga membawa visi penting membangun ekosistem ekonomi haji. Dari pemberdayaan UMKM penyedia makanan, penguatan industri halal, pengembangan layanan digital, hingga diplomasi pelayanan dengan pihak Arab Saudi, semua ini memerlukan kelembagaan yang aktif dan adaptif. Lembaga semacam itu harus fokus pada inovasi kebijakan, bukan dibatasi oleh mandat pengelolaan investasi.
Saya tidak menafikan pentingnya peran BPKH. Justru BPKH harus terus diperkuat agar Dana Haji tetap aman dan produktif. Tapi fungsi pelayanan harus tetap berada di tangan lembaga yang memiliki fokus utama pada ibadah dan manusia, bukan angka dan portofolio. Fungsi ini menyentuh dimensi spiritual, sosial, bahkan budaya.
Sebagai Mustasyar Diny, saya sering mendapatkan pertanyaan dari jamaah tentang fiqh taisir (kemudahan dalam beribadah bagi lansia dan disabilitas), pelaksanaan manasik dalam kondisi darurat, serta pelayanan teknis lainnya. Semua pertanyaan tersebut menuntut adanya kelembagaan yang tanggap dan memiliki kewenangan untuk bertindak. Tidak ada jamaah yang bertanya mengenai laporan keuangan haji, mereka hanya berharap untuk dilayani dengan cara yang manusiawi dan profesional.
Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan dengan sepenuh kesadaran: RUU PIHU harus disahkan sebagai undang-undang tersendiri, dan tidak digabungkan ke dalam UU BPKH. Pemisahan fungsi ini bukan soal ego kelembagaan, melainkan soal prinsip dasar dalam tata kelola publik, yakni kejelasan mandat, akuntabilitas, dan fokus kerja.
Ibadah haji adalah puncak pengabdian spiritual. Di dalamnya terkandung harapan, air mata, dan pengorbanan besar dari jutaan umat Islam. Negara wajib hadir secara penuh dalam melayani mereka, bukan setengah hati, apalagi dengan sistem yang tidak sesuai prinsip tata kelola yang sehat.
Sebagai seseorang yang berada di tengah jamaah, dan sebagai bagian dari struktur ibadah yang menyentuh langsung umat, saya merasa bertanggung jawab menyampaikan ini. Agar tata kelola haji Indonesia tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga sesuai nilai dan amanah spiritual yang dikandungnya.
Choirul Sholeh Rasyid, Ketua PBNU, Mustasyar Diny – Konsultan Ibadah PPIH Arab Saudi 1446H/2025M