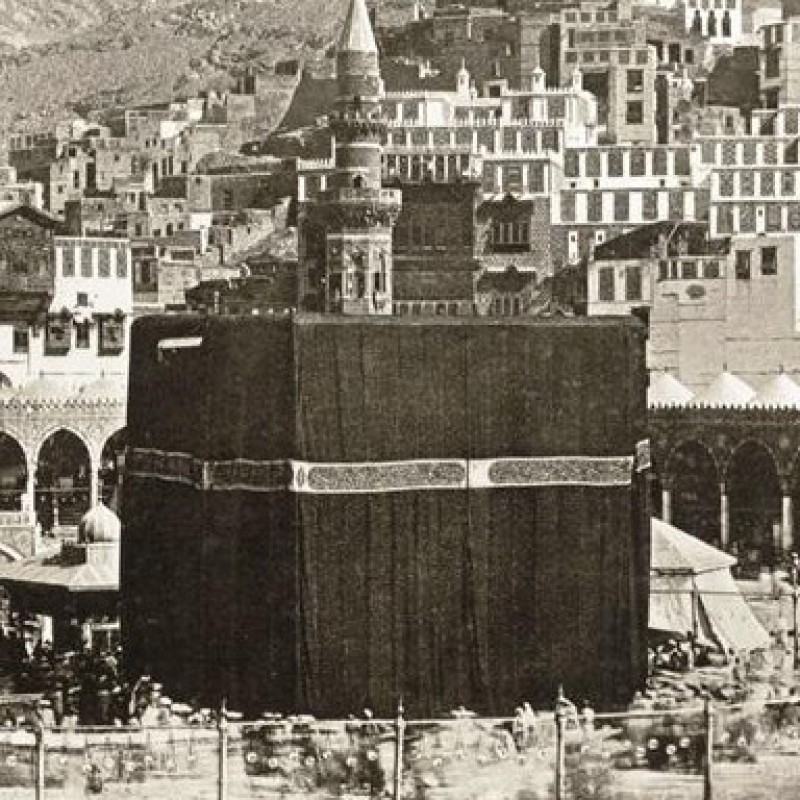Nyai Solichah Wahid Hasyim, Pejuang Dapur Umum dan Kurir di Medan Perang
NU Online · Jumat, 21 Agustus 2020 | 05:00 WIB
Nama kecilnya Munawaroh, yang akhirnya dikenal dengan nama Sholihah Wahid lahir di Jombang, 11 Oktober 1922. Dia adalah anak kelima dari 10 bersaudara putri dari pasangan Kiai Bisri Syansuri (seorang tokoh besar NU) dengan Nyai Chadijah.
Sejak kecil, kehidupannya berada di lingkungan pesantren dengan pengawasan pendidikan yang cukup ketat dari kedua orangtuanya. Pendidikan awal yang diterimanya tak lain adalah pendidikan agama serta Bahasa Arab sebagai bekal mengajar para santri putri di pesantren yang diasuh Ayahnya.
Kiai Bisri mendidik putrinya di madrasah diniyah yang dikelolanya dengan materi-materi pendidikan Islam tradisional sebagaimana yang diajarkan kepada santri. Hanya saja, sebagai bekal agar bisa membantu mengajar santri kelas bawah, Kiai Bisri memberikan tambahan pelajaran pribadi selesai Salat Dzuhur dan Isya' kepada putra-putrinya termasuk kepada Neng Waroh.
Menurut KH Salahuddin Wahid dalam buku Sama Tapi Berbeda: Potret Keluarga Besar KH. A. Wahid Hasyim, pendidikan yang diterima ibundanya adalah pendidikan yang kental dan sarat dengan nilai ajaran agama, yang mencapai tingkat setaraf pendidikan menengah pertama (Madrasah Tsanawiyah).
“Namun, transfer nilai-nilai keislaman dari Mbah Yai (kakung) dan Mbah Nyai (putri) kepada ibu berjalan dengan baik terutama terkait keteladanan,” imbuhnya.
Kecerdasan intelektual Neng Waroh tampak ketika belajar bersama saudara-saudaranya. Dia lebih cepat bisa menyerap pelajaran dan memiliki kemampuan lebih karena kemauan serta rasa ingin tahunya. Semangat belajar serta mengamalkan apa yang dipelajarinya sangat tinggi, terbukti dengan ketekunan Neng Waroh dalam menuntut ilmu serta mengajarkannya kepada santri.
Pengalaman mengajar santri, membuat Neng Waroh, berpengetahuan luas dan maju meski belum mengenal tulisan latin. Sifat kepemimpinannya sangat menonjol sejak kecil. Layaknya seorang manajer, dia memiliki banyak gagasan dan seringkali mengatur saudara-saudaranya untuk bertugas melakukan pekerjaan. Begitu pula kepada teman-temannya serta santri di pesantren tempat dia tinggal.
Selain punya jiwa kepemimpinan, keberaniannya juga tampak sejak kecil. Terbukti, Seringkali dia turut serta melihat prosesi pemakaman orang-orang Tionghoa yang meninggal. Hal yang tak lazim dilakukan anak perempuan seusianya pada masa itu.
Tak hanya sekadar melihat, bahkan Neng Waroh juga mengambil makanan-makanan yang dibawa para pengiring jenazah yang biasa ditinggalkan di area makam Bong Cino. Hal itu merupakan bukti semangat keingintahuan, keberanian, serta kemauan yang tinggi dari sosoknya.
Sebenarnya, kedua orang tua Neng Waroh sudah mewanti-wanti agar dia tidak keluar sendirian tanpa seizin Kiai Bisri maupun Nyai Chadijah. Selain itu juga harus ditemani saudara laki-lakinya. Namun larangan itu kerap dilanggar jika memang dirasa dia punya keperluan penting dan merasa tidak ada bahaya yang mengancam.
Melihat "kenakalan" putrinya, tak lantas membuat Kiai Bisri marah dan langsung menegurnya di depan umum. Sebagai ayah yang bijak, Kiai Bisri menasehati Neng Waroh seorang diri agar sang putri tak merasa malu dan minder.
Sikap berani mengambil risiko ini pula menjadi bekal Neng Waroh (yang lebih dikenal Nyai Sholihah Wahid Hasyim) turut serta membantu perjuangan para relawan perang. Di tengah medan perang mempertahankan kemerdekaan, Neng Waroh menyusup sebagai kurir yang bertugas membawa makanan, pesan-pesan rahasia serta obat-obatan ke garis depan pejuang di daerah Mojokerto, Krian (Sidoarjo) dan Jombang.
Meski di tengah kecamuk pertempuran, hal itu tak menyurutkan nyalinya bertugas sebagai kurir. Tugas yang membahayakan keselamatannya itu dilakukan oleh Nyai Solichah Wahid Hasyim. Semuanya demi usaha yang bisa dilakukan seorang perempuan untuk membantu perjuangan melawan penjajahan.
Saat itu, Nyai Solichah yang tak lain adalah Ibunda Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam jajaran anggota Fujinkai yang merupakan organisasi perempuan bikinan Jepang dan beranggotakan para istri-istri pejabat. Para perempuan pribumi banyak memanfaatkan organisasi ini untuk berjuang serta membantu para pejuang kemerdekaan, sebagaimana yang dilakukan Nyai Sholihah.
Kisah kegigihan Nyai Solichah ini dituturkan oleh putra ketiganya, Kiai Sholahudin Wahid, ketika memaparkan perjuangan Sang Ibunda, Nyai Solichah Wahid pada masa kemerdekaan.
“Ibu aktif dalam kegiatan dapur umum di Jombang yang bertugas membantu para pejuang kemerdekaan. Termasuk di dalamnya memberi dukungan moral dan menampung berbagai keluhan dari para pejuang dan prajurit,” ujarnya.
Tak sebatas itu, perjuangan Nyai Solichah pun berlanjut tidak hanya pra kemerdekaan tapi juga pasca-kemerdekaan dengan perannya berkecimpung di NU dan juga lembaga Legislatif mulai terpilih sebagai anggota DPRD hingga DPR RI. Semasa hidupnya, juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di antaranya turut serta dalam kepengurusan Yayasan Dana Bantuan (YDB) sejak tahun 1958 sampai akhir hayatnya.
Penulis: Nidhomatum MR
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua