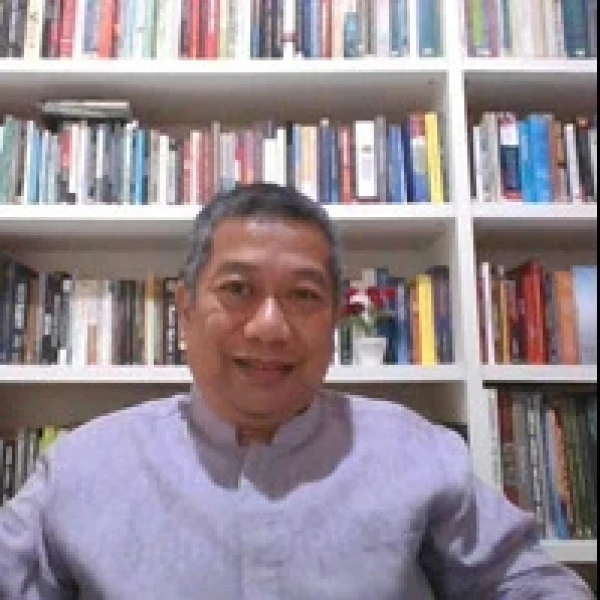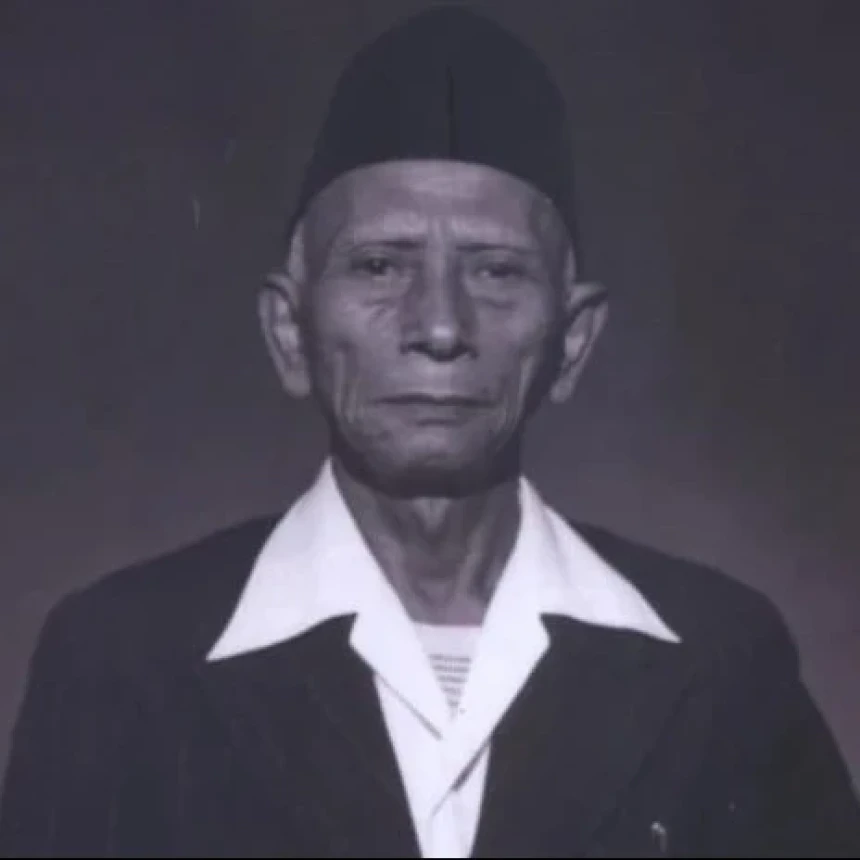Eko Ernada
Kolomnis
Delapan puluh tahun perjalanan Indonesia bukan hanya kisah bertahan sebagai negara, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini membangun pengaruh di panggung global. Dalam rentang itu, Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran strategis—mulai dari penggerak perjuangan kemerdekaan, penjaga moral bangsa, hingga aktor kultural yang memperkuat soft power Indonesia di dunia. Perjalanan NU dalam politik luar negeri Indonesia adalah cerminan transformasi lebih luas: dari menjaga jarak terhadap isu global menuju keterlibatan aktif dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
NU lahir pada 1926 di tengah kegelisahan ulama Nusantara menghadapi kolonialisme dan dinamika dunia Islam yang kala itu sedang bergolak. Setelah Proklamasi 1945, kontribusinya segera terlihat melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, yang memberi legitimasi moral dan religius bagi perjuangan mempertahankan republik.
Peristiwa ini tidak hanya menggerakkan rakyat Surabaya, tetapi juga mengirim sinyal kuat kepada dunia: kemerdekaan Indonesia berdiri di atas fondasi nilai-nilai keagamaan yang membela keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan.
Memasuki dekade awal kemerdekaan, NU lebih memilih mengalihkan fokus dari keterlibatan langsung dalam isu global demi memprioritaskan penguatan internal dan stabilisasi nasional. Pada masa ini, energi politik dan sosial bangsa tersedot untuk membangun institusi, memulihkan ekonomi, dan meredam konflik domestik. NU mengambil peran sentral dalam konsolidasi sosial, menjaga harmoni antarumat beragama, dan meneguhkan identitas keislaman yang selaras dengan keindonesiaan. Sikap ini wajar, mengingat posisi Indonesia sebagai negara baru yang masih rentan.
Namun, globalisasi dan dinamika geopolitik memaksa semua aktor, termasuk organisasi keagamaan, untuk beradaptasi. Arus ideologi lintas batas, kebangkitan radikalisme transnasional, perubahan iklim, hingga krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia mendorong NU untuk meninjau kembali posisinya. Dari situ, lahir pergeseran menuju keterlibatan internasional yang lebih proaktif—dari sekadar merespons isu menjadi menginisiasi agenda.
Baca Juga
Risalah Komite Hijaz kepada Raja Sa’ud
Pada abad ke-21, transformasi ini semakin nyata melalui konsep civilizational diplomacy atau diplomasi peradaban. NU tidak lagi sekadar menjadi pengamat atau pendukung kebijakan luar negeri, melainkan tampil sebagai mitra strategis negara dalam memproyeksikan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.
Forum seperti Religion of Twenty (R20), yang diinisiasi NU di bawah payung G20, menjadi momentum penting. Di sana, NU berhasil memposisikan Indonesia sebagai jembatan dialog lintas iman, menawarkan narasi Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian global.
Kerangka konstruktivisme dalam Hubungan Internasional memberikan landasan teoretis untuk memahami pergeseran ini. Konstruktivisme menekankan bahwa perilaku aktor global dibentuk oleh identitas, norma, dan makna yang dikonstruksi secara sosial—bukan hanya oleh kepentingan material.
Dalam perspektif ini, NU berperan sebagai norm entrepreneur yang aktif membentuk citra Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah sebagai bagian dari identitas diplomasi publik Indonesia. Nilai-nilai seperti tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), ta’addul (adil), dan tawazun (seimbang) tidak hanya menjaga harmoni domestik, tetapi juga mengonstruksi persepsi global bahwa Islam Indonesia adalah mitra yang damai, modern, dan dapat dipercaya.
Keunggulan NU terletak pada kemampuannya menggabungkan kearifan lokal dengan relevansi universal. Islam yang membumi di Nusantara ini kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola yang damai. Dalam situasi global yang kerap terjebak pada stereotip negatif terhadap dunia Muslim, NU mampu menghadirkan narasi tandingan yang kredibel. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada citra Indonesia, tetapi juga pada keamanan nasional, karena mencegah masuknya ideologi radikal dan memperluas dukungan internasional terhadap model Islam moderat Indonesia.
Meski demikian, peran global NU menuntut refleksi kritis. Pertama, apakah NU sudah memanfaatkan sepenuhnya posisinya sebagai aktor global? Keikutsertaan dalam forum internasional memang penting, tetapi tanpa strategi jangka panjang dan koordinasi yang erat dengan pemerintah, potensi ini bisa terfragmentasi.
Kedua, bagaimana menyeimbangkan misi keagamaan dengan realitas geopolitik yang sering penuh kompromi?
Baca Juga
Jurus Diplomasi Kiai Wahid Hasyim
Dunia diplomasi kadang menuntut negosiasi yang sulit, termasuk berinteraksi dengan pihak yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai NU. Ketiga, bagaimana memastikan bahwa pesan yang dibawa tetap otentik dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek?
Di titik inilah, Resolusi Peradaban menjadi penting, bukan sekadar jargon, melainkan fondasi moral bagi keterlibatan global NU. Jika Resolusi Jihad 1945 adalah seruan mempertahankan kemerdekaan fisik, maka Resolusi Peradaban adalah komitmen mempertahankan kemerdekaan nilai.
Peradaban di sini bukan hanya tentang capaian teknologis atau ekonomi, tetapi juga kualitas hubungan antar manusia, martabat kemanusiaan, dan harmoni dengan alam. Dalam pandangan filosofis, peradaban yang utuh bukanlah yang sekadar menguasai materi, tetapi yang mampu menundukkan ego demi kemaslahatan bersama.
Dengan cara pandang ini, NU tidak hanya menjadi representasi Islam moderat Indonesia, tetapi juga aktor yang menyuarakan dimensi etis global: bahwa pembangunan harus seimbang dengan keadilan sosial, kemajuan teknologi harus diiringi tanggung jawab moral, dan perdamaian harus melibatkan rekonsiliasi hati, bukan hanya kesepakatan di atas kertas. Inilah pesan yang perlu dibawa NU ke forum-forum dunia—sebuah tawaran yang tidak banyak dimiliki negara lain.
Kekuatan soft power Indonesia, sebagaimana banyak dicatat para pengamat, bukan terletak pada kekuatan militer atau ekonomi semata, tetapi pada kemampuannya memproyeksikan nilai dan citra yang positif. NU, dengan jaringan pesantren, ulama, dan komunitas globalnya, berada di posisi unik untuk mengartikulasikan nilai-nilai itu. Melalui pelatihan kepemimpinan global berbasis pesantren, keterlibatan dalam penyelesaian konflik internasional, dan kemitraan dengan organisasi lintas iman di berbagai negara, NU dapat mengokohkan reputasi Indonesia sebagai penengah dan pembangun perdamaian.
Menjelang delapan dekade usia republik, kita dihadapkan pada pilihan strategis: tetap nyaman di zona reaktif atau berani menjadi arsitek nilai di panggung internasional. NU, dengan sejarah panjang dan kapasitas yang dimiliki, memiliki semua syarat untuk menjalankan peran itu. Tantangannya tinggal pada kemauan politik, konsistensi, dan visi jangka panjang yang memadukan misi keagamaan, kepentingan nasional, dan dinamika global.
Akhirnya, kemerdekaan tidak hanya diukur dari lepasnya bangsa dari kolonialisme, tetapi juga dari kemampuan menjaga kedaulatan nilai di tengah gempuran ideologi dan kepentingan global. Resolusi Peradaban adalah undangan untuk berpikir dan bertindak melampaui batas geografis, menjadikan Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi pembentuk arus peradaban dunia.
Eko Ernada, Pengurus Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU & Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua