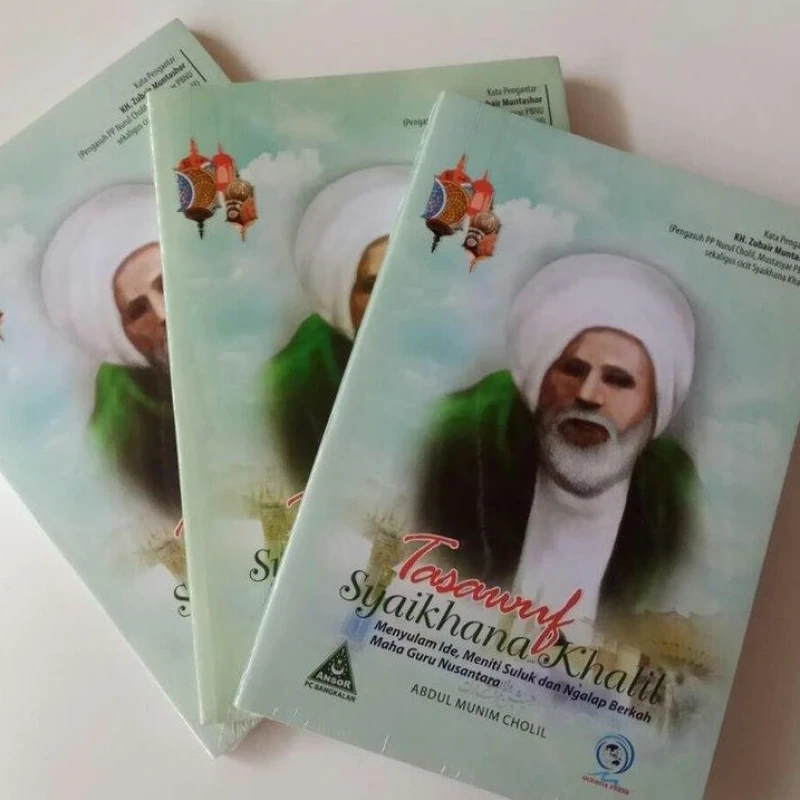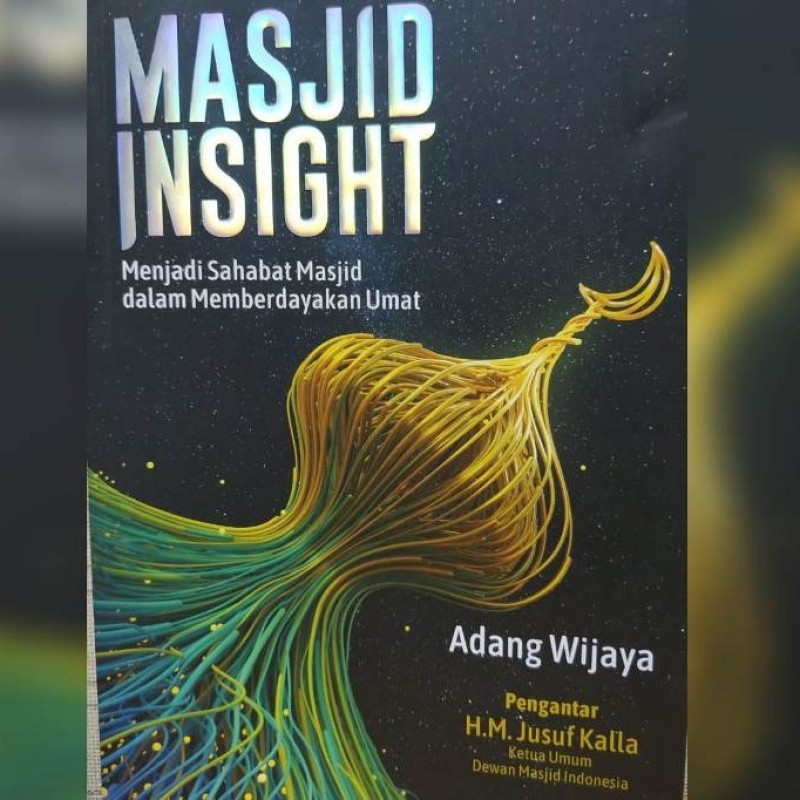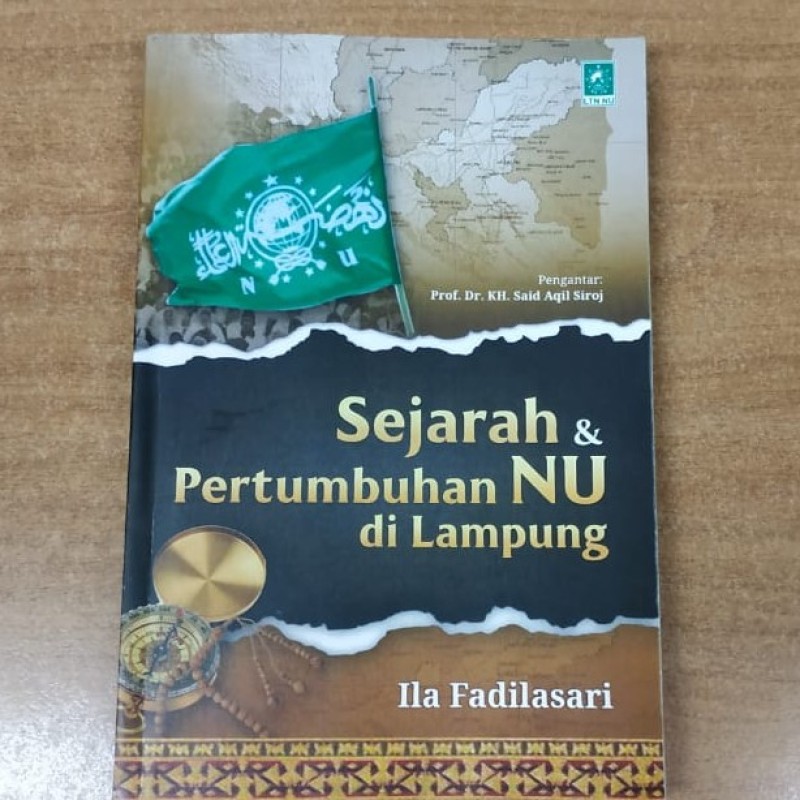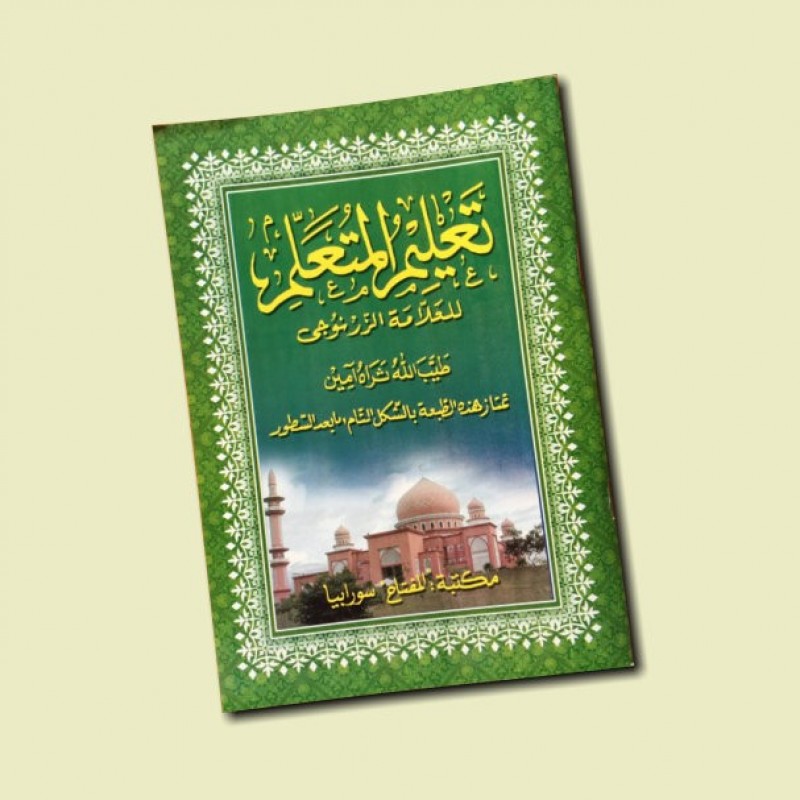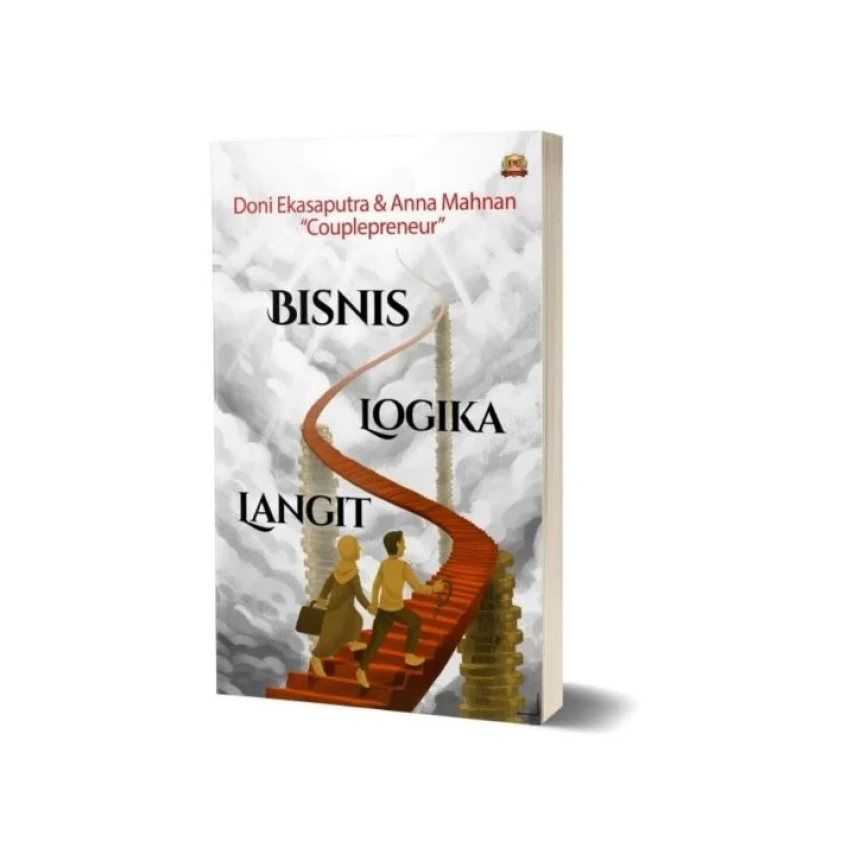Fiqh Al-Usrah: Menyatukan Hukum Keluarga dan Akhlak dalam Semangat Kesalingan
NU Online · Senin, 18 Agustus 2025 | 13:30 WIB
Kajian fiqih keluarga di berbagai literatur sering kali didominasi oleh pendekatan normatif yang menekankan ketentuan hukum secara tekstual: sah atau batal, halal atau haram, wajib atau haram. Pendekatan ini memang penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, namun kerap meninggalkan kesan bahwa fiqih terpisah dari dimensi moral-spiritual yang menjadi ruh syariat.
Dalam kerangka inilah, Fiqh Al-Usrah hadir membawa orientasi baru. Buku ini tidak berhenti pada uraian hukum, melainkan secara konsisten menempatkan akhlak sebagai fondasi utama dalam memahami dan mengamalkan hukum keluarga.
Fiqh Al-Usrah ditulis oleh KH Faqihuddin Abdul Kodir—akrab dikenal dengan sebutan Kang Faqih—seorang penulis produktif berlatar belakang pesantren yang kuat dan menjadi salah satu figur penting dalam Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
Kepeduliannya terhadap isu perempuan dan keluarga merefleksikan perspektif inklusif dan kontekstual dalam menafsirkan fikih. Dalam membaca teks-teks keislaman, Kang Faqih tidak berhenti pada makna literal, tetapi menelusuri asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat) dan asbāb al-wurūd (sebab turunnya hadits Nabi saw) dan konteks sosial-historis yang melatarbelakanginya.
Ia mengaitkan penafsiran dengan maqāṣidus syarī‘ah, memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia.
Pendekatan ini lahir dari kesadaran historis bahwa banyak teks muncul dalam konteks masyarakat Arab yang memandang perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, dengan struktur keluarga yang dibangun di bawah dominasi dan otoritas penuh pihak laki-laki.
Dengan menangkap spirit pembaruan Islam—yang sejak awal datang untuk mengangkat martabat perempuan, melindungi hak-hak mereka, dan menyeimbangkan relasi dalam keluarga—Kang Faqih berupaya menghadirkan pembacaan fikih yang relevan dan transformatif. Fiqh Al-Usrah menjadi wadah untuk menafsirkan teks secara mendalam, memadukan semangat normatif syariat dengan visi keadilan gender, sehingga hukum yang lahir tidak hanya sah secara formal tetapi juga selaras dengan tujuan moral dan sosial Islam.
Pendekatan yang digunakan dalam buku ini berpijak pada perspektif trilogi KUPI: mubadalah, ma‘rūf, dan keadilan hakiki. Dalam kerangka tersebut, memahami teks-teks agama, terutama yang berkaitan dengan keluarga, dilakukan melalui pendekatan mubadalah—yakni pembacaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam kewajiban dan hak. Pendekatan mubadalah ini mengusung tiga prinsip utama: mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (pergaulan yang patut dan penuh hormat), ta‘āwun (saling membantu), dan musyārakah (berbagi peran dan tanggung jawab).
Pendekatan penulis tercermin jelas dalam pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri. Dengan menggunakan kerangka trilogi KUPI tersebut, Kang Faqih mampu mengurai ulang pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri secara proporsional dan setara. Ia menegaskan bahwa dalam hubungan pernikahan, tidak tepat jika pelayanan dalam rumah tangga—termasuk dalam aspek hubungan suami-istri—dinyatakan semata sebagai kewajiban istri terhadap suami.
Sebaliknya, pelayanan itu dipahami sebagai hak sekaligus kewajiban yang berlaku timbal balik antara suami dan istri. Dalam perspektif mubadalah, semua perintah dan anjuran syariat yang diarahkan kepada salah satu pihak, apabila relevan, juga berlaku kepada pihak yang lain. Artinya, pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual dalam pernikahan merupakan tanggung jawab bersama yang dilandasi oleh prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, diperkuat oleh semangat ta‘āwun dalam membantu, dan diwujudkan melalui musyārakah dalam berbagi peran. Dengan demikian, relasi pernikahan tidak menjadi arena subordinasi, tetapi menjadi kemitraan yang saling menguatkan dan melindungi.
Bagian harta bersama dalam Fiqh Al-Usrah menunjukkan kekuatan inovasi Kang Faqih dengan tiga model pengelolaan keuangan keluarga: keranjang minimal, keranjang menengah, dan keranjang maksimal. Ketiganya bukan sekadar opsi teknis, tetapi kerangka etis yang berakar pada prinsip mubādalah, ma‘rūf, dan keadilan hakiki. Keranjang minimal menekankan otonomi masing-masing pihak; keranjang menengah menggabungkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan strategis; keranjang maksimal memusatkan seluruh pendapatan dalam satu pengelolaan bersama.
Pendekatan ini sudah kaya secara konsep, tetapi akan lebih operasional jika dilengkapi skenario kasus konkret. Misalnya, bagaimana penamaan aset (atas nama suami, istri, atau keduanya) memengaruhi hak dan kewajiban saat perceraian atau kematian; pembagian aset pribadi pra-nikah dan pasca-nikah; pengelolaan utang; hingga penilaian kontribusi kerja domestik. Panduan praktis seperti ini akan memperkuat jembatan antara prinsip keadilan yang ideal dengan realitas hukum dan sosial yang dihadapi keluarga, sehingga buku ini tidak hanya memberi arah normatif tetapi juga solusi aplikatif.
Dalam Fiqh Al-Usrah, Kang Faqih memandang talak melalui kacamata sejarah sosial-hukum Islam. Ia menegaskan bahwa salah satu misi penting syariat adalah membebaskan perempuan dari praktik-praktik zalim yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam, ketika laki-laki memegang kekuasaan penuh untuk menekan dan mengontrol perempuan dengan berbagai cara.
Praktik seperti ẓhihār, li‘ān, dan īlā’ menjadi instrumen untuk menelantarkan atau merendahkan perempuan tanpa memberi mereka ruang pembelaan. Islam kemudian hadir untuk mengatur, membatasi, dan menghapus ketidakadilan itu dengan menetapkan syarat dan prosedur yang jelas, serta memberikan hak kepada perempuan untuk keluar dari situasi yang merugikan.
Dalam kerangka yang sama, Kang Faqih melihat bahwa ijtihad kontemporer yang mengharuskan talak diputuskan melalui pengadilan merupakan kelanjutan dari spirit pembebasan ini. Jika talak tetap menjadi hak mutlak suami tanpa mekanisme pengawasan, potensi ketidakadilan terhadap perempuan akan serupa dengan penindasan yang terjadi melalui ẓhihār, li‘ān, atau īlā’ pada masa pra-Islam. Melalui peran pengadilan, proses talak dapat diawasi, alasan perceraian dapat diuji, dan hak-hak perempuan — termasuk nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan dari fitnah — dapat dijamin. Pendekatan ini, menurut Kang Faqih, selaras dengan semangat maqāṣidus syarī‘ah untuk mewujudkan keadilan, melindungi pihak yang rentan, dan mencegah kembalinya praktik-praktik yang merugikan perempuan.
Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi normatif dan etik. Gaya bahasa yang digunakan komunikatif namun tetap berbobot, memungkinkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk mengakses isi buku tanpa kehilangan kedalaman analisis. Setiap penjelasan disertai relevansi dengan realitas sosial kontemporer, sehingga tidak terkesan terlepas dari kehidupan nyata. Pendekatan ini membuat Fiqh Al-Usrah relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga bagi pasangan suami-istri yang ingin membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai syariat yang menyeluruh.
Secara keseluruhan, Fiqh Al-Usrah memberikan kontribusi yang berarti bagi khazanah fikih keluarga di Indonesia. Dengan menempatkan akhlak sebagai pilar pemahaman hukum, buku ini mengingatkan kembali tujuan sejati syariat: menciptakan kemaslahatan lahir dan batin. Pendekatan yang diusung penulis sejalan dengan prinsip moderasi (tawassuṭh) dan keseimbangan (tawāzun) dalam manhaj Ahlussunnah wal Jama‘ah.
Bagi pembaca yang menginginkan pemahaman fiqih keluarga yang tidak kering secara hukum dan tidak longgar secara moral, buku ini layak menjadi rujukan. Ia bukan hanya memandu pembaca memahami aturan, tetapi juga mengajarkan bagaimana aturan itu dihidupkan dengan akhlak yang mulia, demi membangun keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan penuh keberkahan.
Sebagai penutup, Fiqh Al-Usrah layak diperkaya pada edisi mendatang dengan panduan implementasi praktis bagi para konselor, penghulu, dan fasilitator mediasi keluarga. Harapannya, prinsip-prinsip mubādalah, ma‘rūf, dan keadilan hakiki yang menjadi ruh buku ini dapat langsung diterjemahkan ke dalam langkah-langkah aplikatif di lapangan. Panduan ini dapat berupa format dialog, prosedur mediasi, atau studi kasus yang menggambarkan penerapan nilai-nilai kesalingan dalam menghadapi persoalan rumah tangga.
Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi referensi konseptual, tetapi juga menjadi manual etis-praktis yang mampu memperkuat peran para pendamping keluarga dalam membangun relasi yang adil, setara, dan harmonis sesuai spirit Islam.
Buku ini juga akan semakin menguat jika di masa mendatang dilengkapi dengan dukungan data empiris yang menggambarkan realitas sosial kontemporer. Penyertaan statistik perceraian, angka kekerasan dalam rumah tangga, serta peta beban kerja domestik antara laki-laki dan perempuan akan mempertegas urgensi pembaruan perspektif yang ditawarkan.
Data-data ini tidak hanya akan memperkaya analisis, tetapi juga memberi pijakan faktual bagi pembaca, konselor, maupun pengambil kebijakan untuk memahami tantangan aktual keluarga Muslim dan mengimplementasikan prinsip-prinsip mubādalah secara lebih efektif di lapangan.
Identitas Buku
Penulis: Faqihuddin Abdul Kodir
Penerbit: Afkaruna.id Villa Pasirwangi, Ujung berung, Bandung Indonesia
Cetakan Pertama, Februari 2025 (Sya’ban 1446)
Hj. Iffah Umniati Ismail, Pengurus LBM PBNU dan Dosen UIN Jakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua