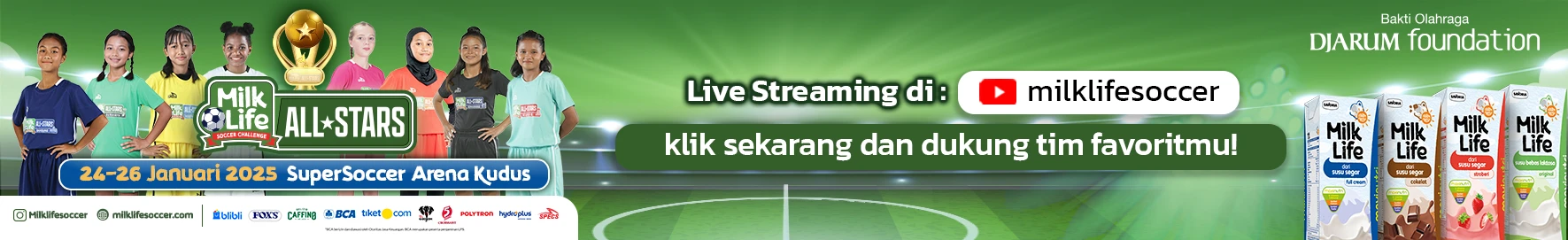"Hadiah Asrul Sani" untuk D. Zawawi Imron
NU Online · Selasa, 2 April 2013 | 20:30 WIB
Umumnya orang keluar hotel dijemput oleh sopir pribadi di lobi hotel. Kalau tidak, mereka melangkah keluar sebentar lalu menyetop taksi, sebuah transportasi tambangan. Namun, D. Zawawi Imron melangkah dengan tongkatnya bersama Ahmad Tohari menghentikan bajaj tanpa canggung atau perasaan malu.
<>
Kendaraan roda tiga yang menghasilkan getaran-getaran tertentu mengantarkan keduanya dari sebuah hotel di Raden Saleh menuju Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (28/3) malam.
Tepat setahun lalu (28/3/2012), keduanya melewati rute yang sama untuk mengisi pidato budaya yang disampaikan oleh Zawawi Imron sendiri. Bedanya, keduanya tahun lalu menumpang taksi.
Zawawi Imron malam itu tercatat sebagai seorang penyair yang menerima Hadiah Asrul Sani (HAS) atas kategori Kesetiaan Berkarya dari Situs Resmi PBNU NU Online yang memperingati 10 tahun kelahirannya.
Ketika ditanya mengapa menjadi seniman, Zawawi Imron yang digelari “Celurit Emas” mengatakan, “Karena seniman itu istimewa. Seniman itu orang yang tersesat di jalan yang benar.”
Perihal itu disampaikan Zawawi Imron, dalam sambutan penerimaan HAS di hadapan sedikitnya 200 hadirin yang memadati Gedung PBNU lantai delapan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3) malam. Zawawi Imron hingga kini masih terus menulis puisi.
Berikut ini merupakan riwayat penyair yang selalu membasahkan mulutnya dengan selawat Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya ditulis oleh Hairus Salim dalam Ensiklopedi NU.
D Zawawi Imron
Ia lahir di Batang-batang, Sumenep, Madura, 1945, namun tidak tahu tanggal dan bulannya, adalah penyair, esais, dan juga pelukis. Berdiam seumur-umur di kampung kelahirannya, tapi penyair yang tak tamat Sekolah Rakyat (SR) dan hanya sempat mencicipi pendidikan di Pesantren Lambicabbi, Gapura, Semenep, tak lebih dari dua tahun ini, dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional.
Mulai menulis puisi sejak umur 13 tahun, ketika belajar di pesantren, mulanya sebagai kegemaran dan panggilan jiwa saja tanpa ada keinginan untuk menjadi seorang yang disebut sebagai ‘penyair.’ Namun, pada tahun 1973, seorang teman mengetik dan mengirimkan puisinya ke media lokal Minggu Bhirawa yang diredaksi oleh Suripan Sadi Hutomo yang kemudian memuatnya. Puisi yang dimuat pertama kali tersebut berjudul “Sembari Diri Berangkat Tua”. Hal ini mendorongnya untuk terus menulis puisi dan menjadi penyair.
Inspirasi-insiprasi dan ide-ide puisinya diambil dari lingkungan alam dan kultur yang menghidupinya: laut dan pengalaman pelayaran anggota keluarga dan warga kampungnya, derap karapan sapi, irama musik saronen, kidung-kidung kampung halamannya, bukit-bukit yang tandus, ladang yang kering, legit siwalan, dan gema orang kampungnya mengaji Al-Quran.
Hidup dalam kemiskinan memberikannya pengalaman batin dan spiritual yang kaya. Tetapi anehnya, ia merasa gagal menulis dalam Bahasa Madura, bahasa ibunya, sehingga memilih Bahasa Indonesia sebagai media ekspresi.
Pada tahun 1979, sajaknya memperoleh Juara I dalam lomba yang ditaja Perhimpunan Sahabat Pena Indonesia. Sebelumnya, dua antologi puisinya juga telah disiarkan. Namun namanya baru benar-benar muncul di pentas puisi nasional ketika pada Temu Penyair 10 Kota di Taman Ismail Marzuki (TIM) tahun 1982, sajaknya diulas secara khusus oleh Subagio Sastrowardoyo, seorang penyair sekaligus kritikus berpengaruh. Sejak itu namanya kian menjadi perhatian dalam jagat sastra nasional.
Tahun 1983, 1984, dan 1985, sajaknya berturut-turut memenangkan lomba yang digelar Perhimpunan Indonesia Amerika. Pada tahun 1985, antologinya Nenekmoyangku Air Mata memperoleh hadiah Yayasan Buku Utama. Menyusul itu, pada tahun 1990, kumpulan puisinya Celurit Emas dan Nenekmoyangku Air Mata terpilih sebagai buku terbaik oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tahun 1995, puisinya “Dialog Bukit Kamboja” memenangkan hadiah utama penulisan puisi ANTV.
Puisi “Celurit Emas” adalah semacam tanggapan kulturalnya terhadap Sudomo, Pangkomkamtib saat itu, yang demi alasan keamanan nasional secara pukul rata melarang keras orang membawa senjata tajam. Melalui kebijakan yang disebut sebagai “Operasi Celurit,” digelar razia terhadap mereka yang membawa senjata tajam. Celurit, senjata khas orang Madura, yang sebenarnya lebih banyak dipakai untuk keperluan di ladang, sawah, atau mengupas atau memotong sesuatu di pasar, dan juga telah digunakan orang di banyak tempat, seakan menjadi terdakwa dalam operasi ini. Maka lahirlah dari tangannya, puisi “Celurit Emas”. Popularitas puisi ini memberikannya julukan sebagai ‘Si Celurit Emas”.
Bersama Dorothea Rosa Herliany, Joko Pinurbo, dan Ayu Utami, Zawawi pernah tampil dalam acara kesenian Winter Nachten di Belanda (2002). Menjadi pemrasaran dalam Seminar Majelis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia (MABBIM) dan Majelis Asia Tenggara (MASTERA) Brunei Darussalam (Maret 2002). Beberapa sajaknya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, Belanda, dan Bulgaria. Yang juga penting dicatat sajaknya Bulan Tertusuk Lalang mengilhami film Garin Nugroho dengan judul sama. Puisinya yang lain, “Lemper” dibacakan dalam film Cinta dalam Sepotong Roti yang juga garapan Garin Nugroho.
Puisi-puisi Zawawi memiliki struktur yang unik menurut kaidah struktur Bahasa Indonesia. Ia sendiri mengaku bahwa meski bahasa yang dipakainya Bahasa Indonesia, strukturnya pada hakikatnya tetap bahasa ibunya, Bahasa Madura. Hal ini, seperti dijelaskannya pada penyair Abdul Wachid BS yang menelusuri proses kreatifnya, tercermin dari cara kiasan, pemilihan irama maupun ungkapan spontanitasnya.
Sampai akhir 1960an, ia mengaku buta dengan perpuisian Indonesia dan hanya membaca sesuatu dari koran-koran bekas. Daerahnya yang relatif terisolir tak memungkinkannya berkomunikasi dengan baik dengan dunia luar. Karena itu, kidung, dongeng, dan syair-syair dalam Bahasa Madura sangat memengaruhinya, sehingga tak aneh kalau puisi-puisi awalnya kebanyakan bersifat naratif. Tetapi belakangan, setelah ia cukup mengenal puisi-puisi penyair Indonesia yang lain, puisi-puisinya lebih bersifat liris atau perpaduan antara keduanya. Zawawi menyadari kecenderungan ini, setelah puisi-puisinya itu selesai ditulis dan diapresiasi. Tetapi ia tak begitu memperhatikan hal ini karena dalam proses kreatifnya, ia mengaku selalu mulai dari penghayatan, bukan pengertian.
Zawawi terkenal sebagai penyair yang produktif. Karya-karyanya yang telah dibukukan meliputi Semerbak Mayang (1977), Madura Akulah Lautmu (1978), Celurit Emas (1980), Bulan Tertusuk Ilalang (1982), Nenek Moyangku Airmata (1985), Berlayar di Pamor Badik (1994), Bantalku Ombak Selimutku Angin (1996), Lautmu Tak Habis Gelombang (1996), Madura Akulah Darahmu (1999), dan Kujilat Manis Empedu (2003). Selain puisi, ia juga rajin menulis esai di berbagai media. Dua kumpulan esainya telah dibukukan, masing-masing Unjuk Rasa kepada Allah (1999) dan Gumam-Gumam dari Dusun: Indonesia di Mata Seorang Santri (1999).
Buku puisinya yang berjudul Kelenjar Laut (Yogyakarta, 1997) mendapat tiga penghargaan. Hadiah Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) dari Kerajaan Malaysia (Nopember 2010), hadiah dari Badan Pengembangan dan Pembidaan Pusat Bahasa (2011), dan Sea Award dari Kerajaan Thailand (Februari 2012).
Zawawi adalah seorang budayawan sejati. Ia melakoni dan menjalankan berbagai peran kreatif dan selalu setia berada di tengah masyarakat atau berhubungan dengan masyarakat lain. Selain menulis, ia juga rajin keliling membacakan puisi ke berbagai kota di Indonesia dan menjadi pemrasaran dalam bidang sastra dan kebudayaan. Bakatnya yang lain adalah melukis. Lukisan-lukisannya telah diikutsertakan dalam berbagai pameran bersama di kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya, bersanding dengan karya-karya perupa terkemuka lainnya. Beberapa lukisan ulama dia taruh di Museum NU Surabaya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang da’i agama yang fasih, dan konon sebagai kiai inilah ia lebih dikenal di kampungnya, daripada sebagai penyair.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Terpopuler
1
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
2
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
3
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
4
PBNU Terima Audiensi GAMKI, Bahas Isu Intoleransi hingga Konsensus Kebangsaan
5
Kisah Di Balik Turunnya Ayat Al-Qur'an tentang Tuduhan Zina
6
Kick Off Jalantara, Rais Aam PBNU Pimpin Pembacaan Kitab Karya Syekh Abdul Hamid Kudus
Terkini
Lihat Semua