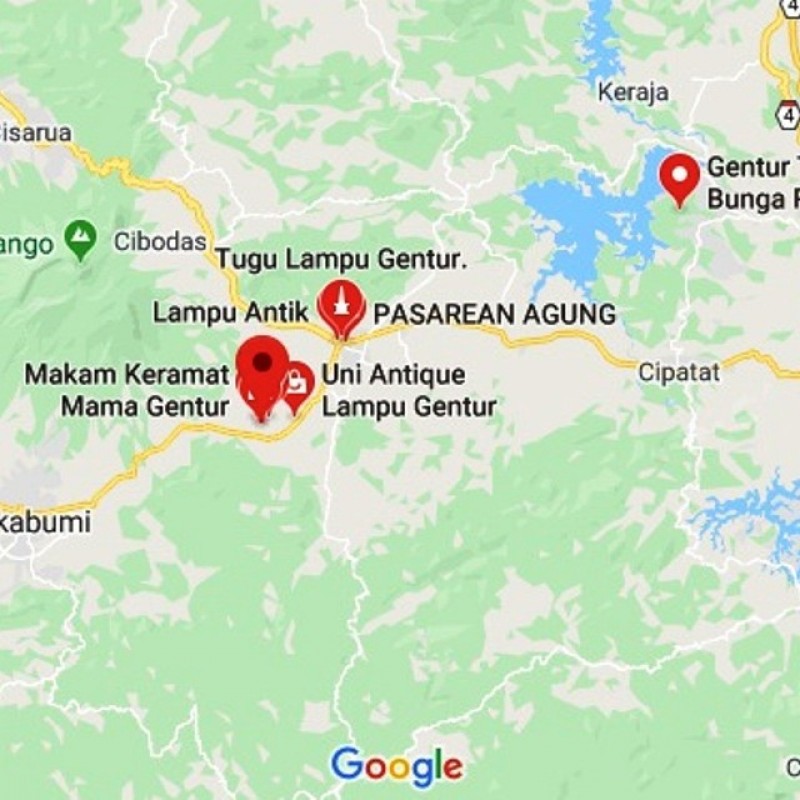Saya akui, terlalu luas hal yang harus dielaborasi jika melihat judul di atas. Untuk menarik sebuah kesimpulan terhadap judul besar tersebut memerlukan penelitian lebih serius bukan sekadar racikan kata-kata. Paling tidak, opini ini dapat dijadikan pijakan awal, apa yang seharusnya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama agar kelompok akar rumput (NU kultural) mengakui bahwa keberadaannya tetap sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Bukan hanya di Tatar Sunda, juga di setiap daerah di negara ini.
Tidak dapat dipungkiri, pergerakan sebuah organisasi selalu bersinggungan dengan keberadaan organisasi lainnya. Bahkan dapat saja bersinggungan dengan kekuasaan. Bukan hanya pertarungan dalam hal ideologi, juga akan selalu menghadapi pertarungan di ranah sosial kultural. Tata cara di dalam peribadatan pun dapat menjadi pemantik persinggungan antar organisasi.
Munculnya wacana Nahdlatul Ulama struktural dan Nahdlatul Ulama kultural sebetulnya bukan hal mendasar dalam sebuah organisasi. Namun melalui pewacanaan ini secara eksplisit tersampaikan pesan bahwa siapa pun yang mengerjakan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (misalnya tahlilan, selametan, kendurian, dsb), mereka masih merupakan orang-orang NU secara kultur, hanya secara struktural tidak masuk ke dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama.
Pada tahun 2000, saat penulis masih duduk di bangku kuliah, persinggungan pemikiran terutama amaliah termanifestasi saat seorang dosen mengatakan muludan, rajaban, bedug, tasbeh, tahlilan, dan amaliah yang biasa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama merupakan bentuk bid’ah, pengamalannya tidak didasari oleh dalil atau nash. Beberapa teman mahasiswa, karena sebagian besar memiliki latar belakang pesantren, saat pulang kuliah sontak berkata kepada saya: “ Biarpun dosen itu mengatakan demikian, kita mah tetap mengamalkannya (amaliah yang disebut bid’ah), kita tetep NU”.
Kisah tersebut merupakan bagian kecil dari persinggungan yang sengaja dilakukan oleh organisasi lain –hanya karena berbeda pandangan terhadap tradisi dan kultur yang telah lama berkembang di masyarakat – melakukan serangan kepada masyarakat (NU kultural). Tidak sedikit, masyarakat yang mudah dipengaruhi hanya karena –seolah-olah para propagandis tersebut- lebih memiliki kapasitas memaparkan persoalan keagamaan karena setiap hal selalu disisipi oleh dalil dari dua sumber hukum primer (Al-Qur’an dan hadits). Masyarakat kultural tentu saja tidak akan dapat melawan hujjah mereka dengan argumentasi lain saat dua sumber primer dalam Islam dijadikan alasan mengerjakan amaliah tertentu. Di kelompok Nahdlatul Ulama kultural inilah sikap skeptik mudah lahir.
Sementara itu, di masyarakat urban, persinggungan pemikiran yang lebih serius telah dimulai dua dekade lalu. Meskipun kalangan muda Nahdlatul Ulama memiliki alasan mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial dalam memberikan penafsiran –secara progressif- terhadap nash, kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok lain sebagai sebuah aliran baru dan cenderung menyesatkan. Liberalisme dalam tubuh Nahdlatul Ulama diwacanakan dan dibahasakan kembali kepada masyarakat tradisional pengamal kultur ke-NU-an. Pandangan kalangan muda Nahdlatul Ulama telah direfleksi oleh kelompok lain bahwa Nahdlatul Ulama saat ini telah diracuni oleh virus sepilis. Pewacaaan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dapat dikatakan sedikit ampuh untuk menghantam pola pikir masyarakat kultural yang masih tabu dengan terma-terma berbau Barat.
Selama dua dekade tersebut merupakan fase penguatan di tubuh NU. Bahkan dapat disebut sebuah fase test-case seberapa kuat hantaman itu dapat meluluh-lantakkan benteng kultural di masyarakat. Kekhawatiran yang mucul telah terselesaikan, meskipun isu sepilis tetap digemakan, tetapi isu ini toch tidak menghantam secara masif benteng pertahanan kultural. Termasuk di Tatar Sunda. Masyarakat yang telah mengamalkan amaliah-amaliah Aswaja meskipun dari berbagai organisasi sering berbisik bahwa dirinya masih sama dengan Nahdlatul Ulama. Tradisi keagamaan yang telah dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat Islam. Ada satu anomali yang terjadi selam sepuluh tahun terakhir ini, yayasan yang dikelola oleh kaum Salafi telah memberikan bantuan pembangungan ribuan mesjid kepada masyarakat dengan beberapa syarat antara lain: tidak boleh ada bedug dan nama mesjid harus diganti. Tetapi masyarakat justru semakin lebih gencar melakukan aktivitas dan tradisi ke-NU-an di mesjid tersebut.
Masyarakat Sunda dalam Bingkai Nahdlatul Ulama
Kita harus jujur, jika dilihat dari perspektif politis, kenapa pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengalami kekalahan di Jawa Barat, tidak ada sangkut-pautnya dengan pertumbuhan radikalisme dan intoleransi di provinsi ini. Kekalahan secara politis tidak dapat disangkutpautkan dengan pertumbuhan intoleransi di satu daerah karena perbandingannya pun memang sudah tidak tepat. Kelalahan politis murni merupakan kelalahan dalam strategi dan marketing politik saja.
NU kultural merupakan entitas paling besar di Tatar Sunda. Permasalahan yang muncul dalam perkembangan ke-NU-an di Tatar Sunda dapat saya simpulkan berkutat pada persoalan adab-adaban dan kemestian hubungan antara Nahdlatul Ulama struktural dengan masyarakat kultural. Ada beberapa kejadian, misalnya tokoh sebuah pondok pesantren mengambil langkah –seolah- keluar dari Nahdlatul Ulama tetapi tetap mengerjakan amaliah Aswaja.
Alasannya sederhana, ada adab dan sopan-santun yang mulai redup. Para pengurus Nahdlatul Ulama di wilayah masih kurang melakukan pendekatan dan membuat strategi bagaimana menghadapi tokoh seperti ini. Nahdlatul Ulama harus memokuskan diri dalam membentuk para “inohong” atau melahirkan tokoh-tokoh karismatik di daerah dan berbasis pondok pesantren. Secara struktural, hubungan vertikal antara pengurus pusat dan daerah harus lebih diintensifkan mengkaji persoalan ini. Artinya, masyarakat telah kehilangan tokoh-tokoh karismatik atau figur-figur dari kalangan pesantren setelah dikelola oleh generasi kedua dan ketiga dari tokoh sebelumnya. Figur-figur inilah yang akan tetap merawat masyarakat dalam mengamalkan amaliah-amaliah keaswajaan sebagai pijakan Nahdlatul Ulama dalam berkiprah dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terpopuler
1
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
2
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
5
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
6
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
Terkini
Lihat Semua