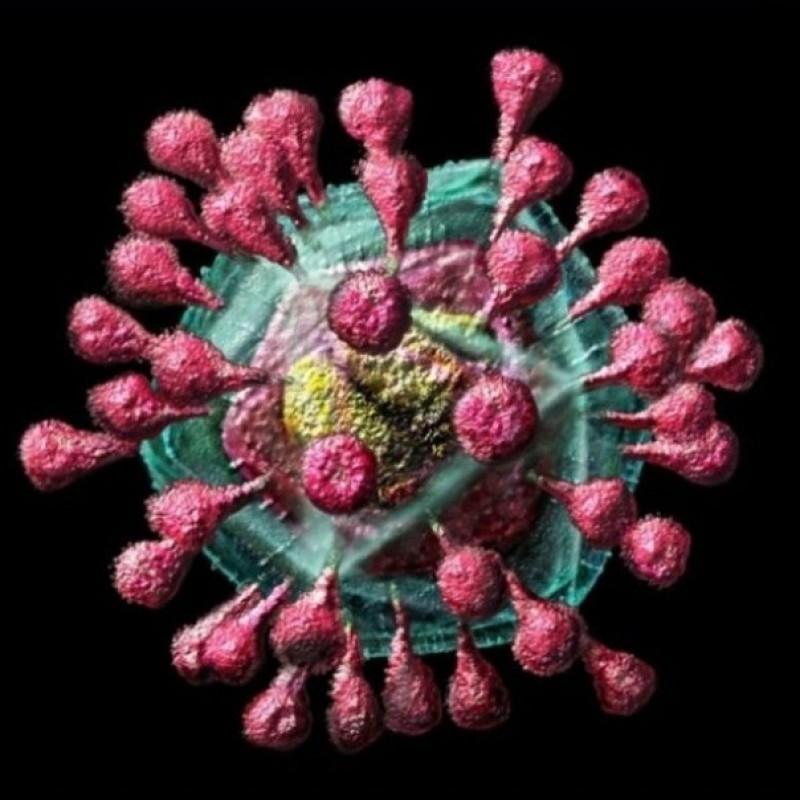Baca: Wabah yang Mengubah Peradaban Manusia (Bagian 1)
Baca: Wabah yang Mengubah Peradaban Manusia (Bagian 2)
Beberapa wabah yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia beberapa abad lalu telah memunculkan polemik pada tiga pranata kehidupan: ilmuwan, agamawan, dan masyarakat umum yang memiliki kecenderungan mengikuti pandangan dua kelompok sebelumnya.
Bagi masyarakat umum atau awam, apapun yang disebutkan oleh dua kelompok tersebut jika dirasakan dapat menguntungkan dan mampu memberikan solusi terhadap wabah dan bencana yang dialami, itulah yang akan mereka ikuti. Sesuai dengan makna dari kata musyarakah sebagai cognate dari kata masyarakat berarti: kelompok yang siap bersekutu dengan siapa saja selama memberikan keuntungan.
Wabah Siprian (250 M)
Wabah Siprian yang terjadi dalam kurun waktu 21 tahun dari 250 – 271 M dalam pandangan Santo Siprianus sebagai bentuk hukuman untuk penebusan dosa yang dilakukan oleh orang-orang “kafir” kepada penganut Kristen. Hal ini mengemuka dengan satu alasan, satu tahun sebelum wabah menerjang wilayah kekuasaan Romawi, Decius, kaisar saat itu mengeluarkan dekrit dan perintah kepada pasukan Romawi untuk melakukan penyiksaan kepada para penganut kristen.
Apa yang dikemukakan oleh Santo Siprianus tentu saja mendapatkan sambutan dari para penganut Kristen saat itu. Mereka memandang bahwa nubuwat hari akhir sebagai salah satu doktrin penting keyakinan setiap agama benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat. Histeria keberagamaan diperlihatkan melalui dua cara: para penganut Kristen mengolok-olok orang-orang “kafir” dan mereka meleburkan diri dalam ritual-ritual bersama yang mereka sebut sebagai “masa penyesalan”.
Selama masa penyesalan sambil menunggu kedatangan hari akhir tersebut ditempuh dengan cara-cara khusus, antara lain: melumuri tubuh dengan debu, memakai pakaian berkain kasar (goni). Walakin, wabah Siprian tetap saja semakin meluas, menewaskan 5000 orang per hari.
Penyematan Siprian terhadap wabah ini dilakukan oleh Gallus, kaisar pengganti Decius yang meninggal tahun 251 M, sebetulnya untuk menstigmatisasi Santo Siprianus dan pengikutnya. Tuduhan penyebaran wabah mematikan ini dialamatkan oleh kaisar Romawi kepada para penganut Kristen sebagai penyebab utama kemunculan wabah. Kebijakan yang dilakukan oleh kaisar saat itu dengan cara mengubur tubuh korban, ditaburi oleh kapur, kemudian dibakar.
Sejarawan mencatat gejala klinis yang disebabkan oleh wabah ini ditandai oleh kemunculan luka pada mulut, beberapa bagian tubuh memperlihatkan luka bakar. Otoritas Romawi juga tetap melakukan isi dekrit Decius melakukan penganiayaan kepada para pemeluk Kristen.
Kemunculan wabah mematikan ini telah melahirkan kekhawatiran dalam diri Santo Siprianus, dia menuliskannya dalam satu risalah berjudul De Moratalitate (kefanaan): “Saya mengamati bahwa di antara orang-orang kristen pun ada beberapa kelompok memiliki iman yang lemah, tergoda oleh manisnya kehidupan duniawi, jatuh dalam kelembutan seksualitas, dan tidak memiliki keteguhan merasakan kehadiran kekuatan ilahi dalam diri mereka.”
Hal di atas dipandang oleh Santo Siprianus sebagai pertanda akhir dunia dan kedatangan kerajaan surga. Kerisauan ini akhirnya diungkapkan dalam kebuntuan sikap: “kematian akibat wabah bukan hal yang perlu ditakuti tetapi harus dihadapi dengan penuh sukacita. Sebab, kematian akan membawa kalian kepada Kristus.”
Siprianus melakukan berbagai pendekatan untuk mengokohkan keyakinan para penganut Kristen saat itu. Pertama, kepada para pengikutnya berusaha menginspirasi kesabaran dan ketabahan. Kedua, meyakinkan kepada mereka untuk tetap lebih mempertegas diri dan tetap berkomitmen dalam kekristenan dengan mengeluarkan pernyataan bahwa kemuliaan surga memang sangat kontras dengan kesengsaraan akibat wabah yang terjadi. Ketiga, mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Tuhan telah menubuatkan akan timbulnya perang, kelaparan, gempa bumi, dan sampar (wabah) di berbagai tempat.
Tepatnya, bagi Santo Siprianus sebagai seorang uskup Karthago, wabah dan penyakit yang dialami oleh orang-orang kristen saat itu sebagai ujian dari Tuhan untuk membuktikan seberapa besar kayakinan manusia kepada-Nya. Dalam risalahnya, dia menyatakan: Deus de hoc mundo recedenti inmortalitatem adque aeternitatem pollicetur, et dubitas? (Tuhan telah menjanjikan keabadian saat kamu meninggalkan dunia, kamu meragukannya?
Dalam menyikapi pandemi corona virus disease 2019, tampaknya semangat perdebatan seperti yang pernah dialami oleh Santo Siprianus dengan kaisar Romawi masih diperlihatkan oleh manusia-manusia modern. Tentu saja dalam bentuk berbeda tetapi memiliki kemiripan substansi.
Meskipun fatwa tata cara melaksanakan ibadah ritual dikeluarkan oleh MUI untuk mengantisipasi penyebaran Corona tetap saja disikapi secara salah pemaknaan oleh beberapa kelompok. Di media sosial pernah tersebar kalimat seperti ini: meninggal saat menunaikan sholat berjamaah kemudian meninggal karena virus lebih baik daripada berdiam diri di rumah. Padahal penanganan wabah di zaman sekarang jelas sekali sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan cara-cara otoriter seperti yang pernah dilakukan oleh Decius dan Gallus.
Saya pikir, tidak ada pemerintah di belahan dunia manapun yang melakukan dehumanisasi (penganiayaan) kepada orang-orang yang terpapar virus, apalagi sampai membunuhnya dengan cara dibakar hidup-hidup. Langkah-langkah yang ditempuh oleh dunia untuk menanggulangi Covid-19 benar-benar sangat manusiawi meskipun tetap saja dipandang sebagai upaya untuk menjauhkan manusia kepada agama dan rumah ibadah oleh beberapa kelompok.
Apa yang dilakukan oleh Santo Siprianus dengan cara pandang orang-orang yang sangat histeris terhadap keyakinannya memiliki konteks yang jauh berbeda. Siprianus memandang wabah sebagai ujian dari Tuhan karena saat itu kemunculan wabah beririsan dengan kebijakan kaisar melakukan penganiayaan kepada para pengikutnya. Sementara itu, kemunculan corona virus disease 2019 saat ini sama sekali tidak dilatarbelakangi oleh kebijakan dehumanisasi oleh satu pemerintah kepada rakyatnya.
Meskipun ada saja asumsi-asumsi yang berkembang bahwa kemunculan Corona merupakan akibat dari meledaknya rancangan senjata biologis di satu negara, sebuah upaya untuk menguasai dunia di era perang dagang. Asumsi seperti ini patut dipertanyakan: apakah hanya karena ingin mendapatkan keuntungan besar, satu negara atau beberapa kelompok manusia harus menyebarkan ketakutan dan merusak tatanan dunia terlebih dahulu? Toh, keuntungan dalam perdagangan dan perokonomian justru akan diraih saat tatanan dunia dipenuhi oleh kedamaian. Kita memproduksi barang dalam jumlah besar, lantas akan dipasarkan ke mana, dijual ke negara mana di saat setiap negara sedang berjibaku melawan pandemi Covid-2019?
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
3
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
4
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
5
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
6
Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun
Terkini
Lihat Semua