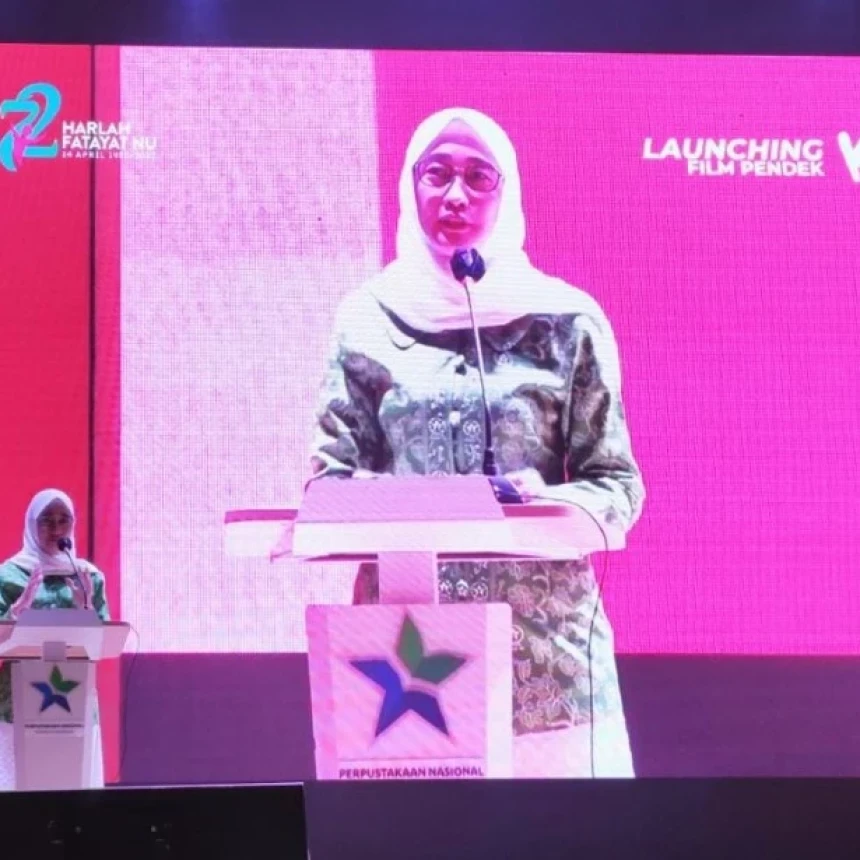Perdebatan Boleh Tidaknya Perempuan NU Jadi DPR hingga Lurah pada 1960
NU Online · Ahad, 24 April 2022 | 16:00 WIB
Ajie Najmuddin
Kontributor
72 tahun yang lalu atau 24 April 1950, Fatayat NU resmi didirikan dan dua tahun kemudian baru disahkan menjadi badan otonom (banom) NU. Bersama Muslimat NU yang sudah terlebih dahulu berdiri, kelahiran Fatayat NU sebagai organisasi perempuan di masa itu, memberi warna tersendiri dalam dinamika organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1955, menyusul kemudian lahir Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), yang menyasar ke kalangan pelajar.
Kiprah para perempuan NU ini kemudian mendapatkan pengakuannya di publik, dalam artian mendapatkan kesempatan yang lebih untuk menyuarakan pendapat mereka. Seperti ketika beberapa dari perempuan NU tersebut terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante Republik Indonesia (RI).
Pada Pemilu tahun 1955, para kader Muslimat dan Fatayat NU, dengan rincian 5 orang menjadi anggota DPR RI dan 7 orang (termasuk anggota pengganti) menjadi Konstituante. Tentunya termasuk di tingkat daerah juga banyak dari mereka yang ikut terpilih.
Dikutip dari buku Hasil Rakjat Memilih; Tokoh-Tokoh Parlemen Hasil Pemilu Pertama – 1955 (Parlaungan, 1956) mereka yang terpilih menjadi anggota DPR RI, yaitu Ny Asmah Sjahrunie, Ny Mahmudah Mawardi, Ny Mariam Kanta Sumpena, Ny Mariyamah Djunaidi, dan Ny Hadiniyah Hadi Ngabdulhadi.
Sedangkan yang menjadi anggota Konstituante, sebagaimana dilansir dari buku Berangkat dari Pesantren (Saifuddin Zuhri, 2013) yakni Ny Solichah Saifuddin Zuhri, Ny Adiani Kertodiredjo, Ny Ratu Fatmah Chatib, Ny Abidah Mahfudz, Ny Nihayah Maksum, Ny Aisjah Dachlan, dan Ny Siti Djamrud Daeng Tjaja.
Yang menarik, meski mereka telah terpilih menjadi anggota DPR dan Konstituante RI dari hasil Pemilu 1955, NU sendiri baru memutuskan secara resmi keterlibatan wanita NU di politik, pada Konferensi Besar (Konbes) NU di Surabaya tahun 1957.
Adapun redaksi dari keputusan bolehnya perempuan menjadi anggota DPR/DPD, yakni sebagai berikut:
“DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (tsubutu amrin li amrin), bukan untuk menentukan qadha (lizamil hukmi). Oleh sebab itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Afifah, 2. Ahli dalam hal-hal tersebut di atas, 3. Menutupi auratnya, 4. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin, 5. Aman dari fitnah, dan 6. Tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara’. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka haram. Dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriah NU berhak menariknya.”
Perempuan Menjadi Lurah
Beberapa tahun berselang, kembali muncul perdebatan tentang boleh tidaknya aktivis perempuan menjadi pemimpin pemerintahan, khususnya dalam level desa atau kelurahan (kades/lurah). Waktu itu ada anggota Fatayat NU yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, tapi karena merasa tidak ada rujukan, maka ditanyakan kepada para kiai.
Pada Rapat Dewan Partai NU di Salatiga tanggal 25 Oktober tahun 1961, hasil dari keputusan rapat tersebut memberikan beberapa opsi, pendapat rujukan dari beberapa ulama, dengan redaksi sebagai berikut:
“Sebenarnya mencalonkan orang perempuan untuk pilihan Kepala Desa itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim. Demikianlah menurut mazhab Syafi’i, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta benda. Sedang Imam Ibn Jarir memperbolehkan dalam segala urusan dari apa saja.” (Ahkamul Fuqaha, 2011)
Keputusan yang diambil, kemudian memperbolehkan sang kader ikut dalam pencalonan sebagai kepala desa. Meski kemudian, tidak dijelaskan bagaimana kelanjutannya, apakah jadi atau tidak.
Lain zaman, tentu lain kebijakan. Di masa kini, para perempuan NU malah sudah banyak yang menjadi pemimpin dan pejabat pemerintahan, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga level RT.
Meski demikian, perdebatan mengenai perempuan menjadi kepala pemerintahan seperti itu masih kerap muncul, terutama menjadi isu kampanye untuk menjatuhkan suara sang calon pemimpin (perempuan).
Penulis: Ajie najmuddin
Editor: Muhammad Faizin
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
3
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
4
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
5
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
6
Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun
Terkini
Lihat Semua