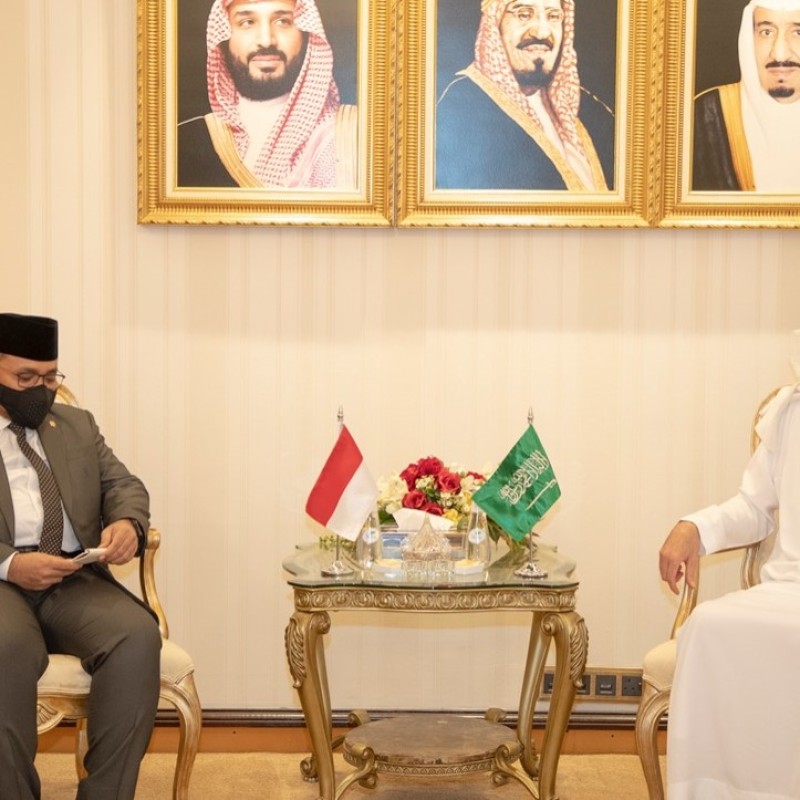Muhammad Aiz Luthfi
Penulis
Perjalanan ibadah haji masyarakat Nusantara yang dilaksanakan pada zaman kolonial tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Hal ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan mulai dari fasilitas, regulasi sampai alat transportasi. Gambaran berbagai macam kejadian dan perjuangan umat Islam di Nusantara yang berkaitan dengan perjalanan ibadah haji itu dapat dijumpai dalam buku Berhaji di Masa Kolonial (2008) karya Prof M. Dien Madjid.
Dien Madjid mencatat, walimatus safar atau slametan sebelum berangkat haji dan umrah sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Umumnya, sebelum berangkat haji ada upacara perpisahan untuk saling memaafkan antara calon jamaah haji dengan masyarakat, mulai dari keluarga, kerabat dan juga tetangga, selanjutnya mereka akan mengantarkan kepergian calon jamaah sampai ke pelabuhan.
Baca Juga
Hukum Selamatan Sebelum Berangkat Haji
Upacara tersebut tiada lain adalah sebagai bentuk penghormatan kepada calon jamaah haji yang akan melakukan perjalanan sangat jauh dan cukup lama. Bisa jadi upacara tersebut menjadi pertemuan terakhir sehingga tidak menjadi beban di kemudian hari karena sudah saling memaafkan.
Perjalanan para calon jamaah haji menuju Makkah digambarkan penuh dengan rintangan dan perjuangan. Di antaranya harus melewati ombak samudera yang besar dan hembusan angin kencang yang bisa mengakibatkan kapal karam dan membuat penumpang menjadi meninggal, cedera karena terhempas atau terhimpit, barang-barang berharga seperti uang, emas, dan perak menjadi hilang, namun ada juga penumpang yang masih beruntung dan selamat dari kecelakaan.
Selain itu, saat berlayar di atas lautan ada juga jamaah yang meninggal dunia karena kelelahan, kekurangan sarana, atau mengidap penyakit. Permasalahan lain yang terkadang bisa menimpa pada sebagian penumpang adalah harus merelakan barang-barang berharga karena dicuri orang. Akibatnya, ketika sampai di pelabuhan ia harus mencari pekerjaan menjadi buruh atau meminjam uang kepada syekh (pembimbing haji) untuk mendapatkan uang dan bisa melanjutkan perjalanan.
Pada zaman itu, perjalanan haji memakan waktu minimal enam bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun karena kehabisan bekal dan bekerja di perkebunan atau perusahaan setempat. Tidak sedikit orang Nusantara yang bisa berangkat haji namun tidak bisa kembali pulang karena meninggal di perjalanan atau terdampar di suatu tempat. Sampai saat ini, kesedihan keluarga, kerabat dan tetangga saat hadir di acara walimatus safar atau ikut serta mengantarkan calon jamaah haji masih bisa dilihat dan dirasakan.
Penulis: Aiz Luthfi
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
4
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua