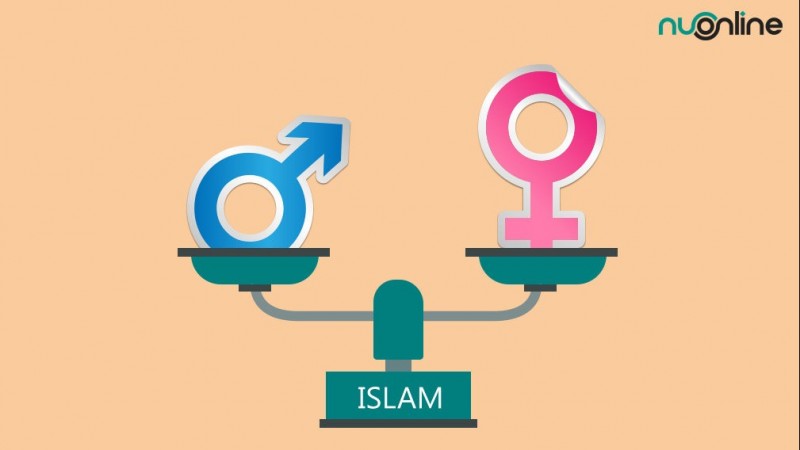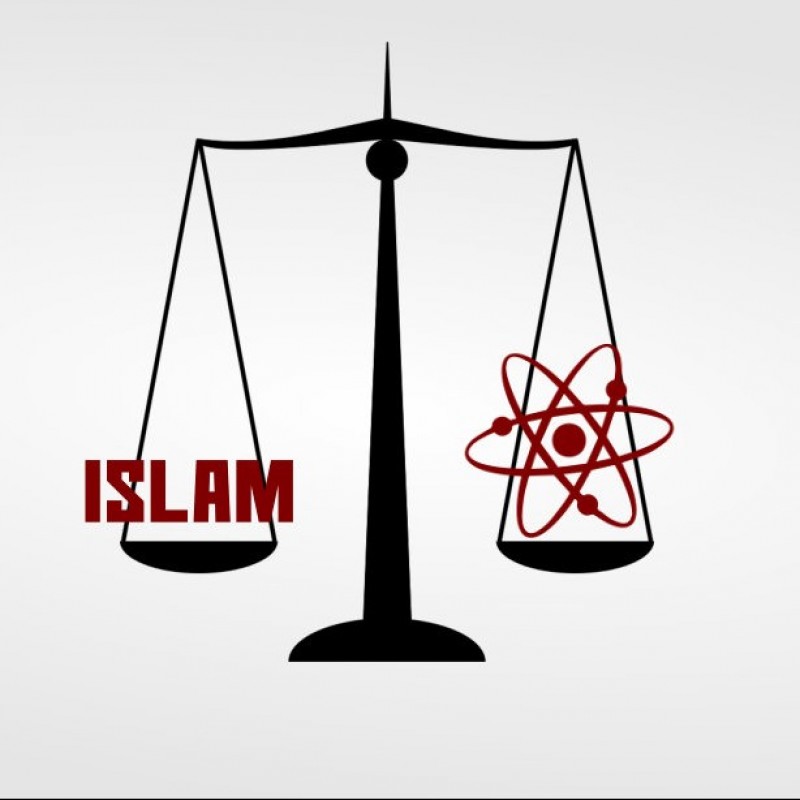Fahri Hilmi
Kolomnis
Suatu ketika pada 1991 awal, Swami Shanti Prakash, pendeta Hindu kenamaan asal India, melawat ke Jakarta. Jemaat Hindu se-Indonesia tentu saja memenuhi tempat di mana acara lawatan itu berlangsung. Berduyun-duyun umat Hindu Tanah Air berkumpul dan menyambut sang pendeta.
Agar diketahui, Swami Shanti Prakash merupakan salah satu dari 20 pemuka agama di India yang setiap tahun kakinya dibersihkan oleh presiden dengan air susu. Beliau juga seorang yang peduli masyarakat miskin dan pinggiran. Hampir setiap hari sang pendeta memberi makan jutaan orang miskin di 180 kuil yang ia kelola di seluruh India. Beliau adalah orang yang teramat berpengaruh di kalangan umat Hindu dan masyarakat India.
Dalam acara lawatannya ke Jakarta, Gus Dur hadir sebagai undangan khusus sang pendeta. Saat Gus Dur tiba di ruang acara, seorang pengiring pendeta berbisik kepada Swami Shanti Prakash, “Gus Dur telah tiba.” Seketika sang pendeta berdiri tertatih dan dengan susah payah menghampiri guna menyambut Gus Dur. Maklum, saat itu sang pendeta sudah uzur, usianya 80 tahun, dan buta. Beliau merentangkan tangannya tanda tawaran pelukan persahabatan kepada Gus Dur. Pelukan itu disambut Gus Dur. Sembari memeluk Gus Dur, sang pendeta berbisik dengan penuh tekanan, “Saya titip umat Hindu di sini.”
Kisah luar biasa itu terdokumentasikan dengan rinci dalam sebuah buku bergambar berjudul Gus Dur: Berbeda itu Asyik (2004) karya Iip D. Yahya. Dalam wawancara dengan majalah Tiara (1991), Gus Dur mengatakan, “...pada saat itu saya merasa bangga sekali diterima sebagai warga umat manusia. Rasanya tidak sia-sia hidup ini,” demikian Gus Dur.
Rasa bangga sekaligus senang yang diungkapkan Gus Dur pasca pertemuannya dengan Swami Shanti Prakash tentu tidak terlepas dari gagasan kosmopolitanisme Islam yang telah lama dianut oleh putra KH Wahid Hasyim itu. Kesenangan itu muncul sebagai ekspresi dari visinya mengenai “kewargaan dunia”. Karena Gus Dur mendaku dirinya menjadi “warga dunia”, maka ungkapan sang pendeta dapat dianggap sebagai sebuah pencapaian besar dari pengakuan itu.
H. As'ad Ali, dalam esai pengantar buku Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan (Syaiful Arif, 2013) berjudul “Konstruksi Pemikiran Gus Dur”, mengatakan bahwa konstruksi pemikiran Gus Dur adalah berasaskan: universalisme Islam, pribumisasi Islam, dan kosmopolitanisme Islam.
Universalisme Islam berbicara mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, yang terbelah ke dalam: perlindungan atas hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak berkeluarga. Pribumisasi Islam berbicara mengenai konteks lokalitas Islam. Dalam hal ini, ajaran Islam yang telah melalui proses pribumisasi itu akan berhadapan dengan isu pluralisme dan konflik antar golongan, jika dikontekstualisasikan dengan fakta homogenitas Indonesia. Sedangkan, kosmopolitanisme Islam adalah titik pijak dari lahirnya gagasan-gagasan universalisme Islam dan pribumisasi Islam.
Pada tulisan sebelumnya, saya telah membahas mengenai gagasan kosmopolitanisme Islam ini dalam Kosmopolitanisme dan Daya Serap Islam. Di dalamnya, kita dapat nengetahui bahwa kosmopolitanisme berbicara mengenai keterbukaan Islam terhadap rasionalitas-rasionalitas yang berasal dari pemikiran manapun, untuk kemudian dikodifikasikan atas dasar ajaran-ajaran Islam.
Dalam Hairus Salim (2020: 130-131), gagasan kosmopolitanisme Islam meluber ke dalam lima poin jaminan dasar: (1) Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; (2) Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; (3) Keselamatan keluarga dan keturunan; (4) Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan (5) Keselamatan profesi.
Kesetaraan Gender
Membaca kelima dasar jaminan di atas, dapat dikatakan bahwa gagasan ini dapat dijadikan titik pijak bagi perjuangan keadilan dan kesetaraan pada lokus apa pun, selama terdapat penindasan dan diskriminasi di mana pun berada. Berangkat dari pembacaan demikian, penulis hendak mengajak pembaca kepada gagasan eklektis antara ide kosmopolitanisme Islam dengan perjuangan kesetaraan berbasis gender, atau singkatnya kesetaraan gender.
Perjuangan kesetaraan gender adalah perjuangan yang menuntut penyetaraan, baik dari segi hak hukum, hak ekonomi, hak reproduksi, hak politik, dan segala bentuk hak asasi manusia antara laki-laki, perempuan, dan eksistensi gender lainnya.
Gagasan ini memiliki rem pelekat sekaligus bendera bernama feminisme. Gagasan ini mulai menyeruak ke permukaan saat masyarakat perempuan Perancis, pada masa Revolusi abad 17, merasa masih ditindas dan tak terpenuhi hak-haknya kendati revolusi usai berlangsung. Penindasan yang selama ini terjadi ternyata dientaskan atas dasar kebutuhan laki-laki. Artinya, perempuan menjadi pihak yang ditindas di antara yang ditindas.
Akibat situasi yang sedemikian mencekik itu, kaum perempuan Perancis mulai turun ke jalan dan meneriakkan suara-suara mereka di ruang-ruang publik. Sejak saat itulah, hingga kini, wacana feminisme dan kesetaraan gender mulai dibicarakan dan dibukukan.
Dari ringkasan sejarah demikian, dapat diketahui bahwa secara bahasa, gagasan perjuangan kesetaraan gender dan feminisme berasal dari Barat. Fakta inilah yang membuat banyak kelompok Islam konservatif menyangka kalau feminisme memiliki pengaruh buruk terhadap kadar keimanan seorang Muslim. Bahwa apa pun yang lahir dari rahim Barat, adalah ajaran yang haram dalam Islam.
Padahal, gagasan mengenai kesetaraan gender ini menjadi salah satu agenda dakwah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam semasa perjuangan Islam awal. Hanya saja, saat itu tidak dipakai istilah feminisme atau gender. Tentu saja, karena kedua istilah itu berasal dari semesta pengetahuan Barat. Akan tetapi, rasionalitas yang ditawarkan oleh feminisme identik dengan Islam, terutama berbicara mengenai kemanusiaan.
Substansi dari feminisme dan kesetaraan gender adalah terwujudnya keadilan berdasarkan gender, masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Lalu, mengacu pada substansi tersebut, apakah terdapat pertentangan dengan perjuangan Nabi?
Bukankah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam adalah tokoh yang paling vokal dalam menentang penindasan manusia atas manusia? Perbudakan dihapus, kaum mustadh'afin diangkat derajatnya, poligami dibatasi, dan menghilangkan sekat-sekat identitas sempit manusia berdasarkan asal usul yang sama, yakni Adam dan Hawa.
Kesamaan substansi perjuangan ini tak mungkin bertemu jika kita masih terjebak dengan eksklusivitas agama hanya karena akar historis yang sedikit berbeda. Lain halnya jika menggunakan kosmopolitanisme Islam sebagai alat perekat.
Dalam menggunakan gagasan kosmopolitanisme Islam sebagai titik pijak perjuangan kesetaraan gender, kita akan tertuju kepada dua garis besar pembacaan.
Pertama, kosmopolitanisme Islam dapat dijadikan landasan eklektik yang membiarkan wacana feminisme masuk ke dalam khazanah keilmuan Islam. Hal ini secara tidak langsung dikatakan oleh Gus Dur dalam esainya berjudul “Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama” (Majalah Aula: Risalah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, No. 5/1985: 23-32).
Dalam esai tersebut, Gus Dur mengatakan bahwa untuk duduk setara dengan ideologi-ideologi dunia, Islam mesti mau menyerap pemahaman dan pemikiran yang positif dari luar sehingga dapat terwujud relevansi.
Kemauan serap-menyerap ini, menurut Gus Dur, telah menjadi watak asli dari agama Islam. Prinsip “al-muhafadhatu 'alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” (melestarikan hal lama yang masih bagus, dan menyerap hal baru yang lebih bagus) menjadi landasan dari lahirnya pemahaman tersebut.
Berbasis pembacaan demikian, wacana feminisme dan kesetaraan gender mestinya dapat diterima dengan baik dalam ajaran Islam, karena memuat substansi perjuangan yang kembar dan identik.
Kedua, penghilangan batas-batas identitas sempit yang dianut dalam kosmopolitanisme menunjukkan kalau semua pihak, selama ia tertindas, apalagi perempuan, haruslah bangun dan berdiri untuk memperjuangkan kesetaraan gender.
Cekikan patriarki, di mana laki-laki menjadi pihak penindas, akan runtuh apabila semua laki-laki memahami konsep anti-identitas sempit ini. Menganut prinsip kosmopolitanisme, siapa pun, tak terlepas ia lelaki atau perempuan, ia Islam atau bukan, akan melebur menjadi satu.
Kekuatan gabungan ini akan tergerak dan berjuang menghilangkan batas-batas yang dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan; saling menghargai; hingga saling memperjuangkan hak satu sama lain. Semua perjuangan ini tentunya akan berlandaskan pada satu aspek tunggal: kemanusiaan.
Tak Ada Tendensi Anti-Lelaki
Meminjam template kalimat penutup esai M. Abdullah Badri berjudul Kosmopolitanisme Gender (Suara Merdeka, 2010), penulis hendak mengatakan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukanlah milik perempuan, bukan pula milik Barat. Sebagai terminologi, ia meliputi perempuan, laki-laki, dan seluruh entitas gender yang ada.
Perjuangan kesetaraan gender yang kosmopolit sudah pasti akan malancarkan persekusi dan tudingan penindasan yang tak hanya ditujukan kepada lelaki, melainkan kepada semua pelaku penindasan, pendukung budaya patriarki, dan pemegang etika fir'aunisme yang menciptakan kericuhan dan konflik sosial.
Lalu, apakah Islam yang memperjuangkan kemerdekaan manusia akan menolak itu?
Penulis adalah admin @pikiranlelaki_. Dapat ditemui di @fahrihill.
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
2
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Prabowo Sebut Polisi yang Langgar Hukum dalam Penanganan Demo Akan Ditindak
5
Prof. Moh. Koesnoe, Cendekiawan NU Kaliber Dunia: Ahli Hukum Adat dan Pendidikan
6
Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen oleh Polisi Dinilai Keliru dan Salah Sasaran
Terkini
Lihat Semua