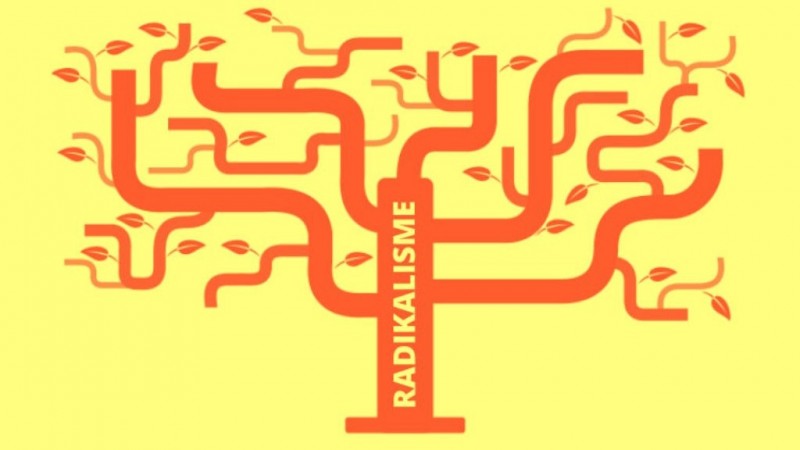Di kalangan radikalis seringkali ditemukan adanya pecah kongsi antara paham orang tua dan anak-anak mereka. Para inovator radikalisme yang menyebut dirinya mutasyaddid seakan pintar mengendus selera pasar, khususnya mengenai apa yang dibutuhkan kaum muda yang masih labil dan rentan keyakinannya. Pasaran yang menggiurkan tatkala dunia politik mengalami kekeruhan dan kekisruhan, ketiadaan figur teladan, serta kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial.
Demikian halnya dengan logika kaum perusuh. Pemahaman mereka tentang esensi agama dibuat kabur dan simpang siur. Mereka membangun logikanya sendiri, sambil menerima petuah dan iming-iming yang dianggap menjanjikan solusi bagi jaminan masa depan mereka.
Pemikiran yang liar ini bisa menjurus kepada paham nasionalisme ekstrem yang pernah dibuktikan oleh para kaki tangan Hitler (Nazi). Pengultusan pada figur penguasa, yang dianggap memiliki otoritas tinggi (mu’tabir) tak beda jauh dengan gerakan kaum perusuh yang radikal dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan.
Apakah bedanya para pengikut Abdurrahman al-Baghdadi (pentolan ISIS) dengan para pengikut Dimas Kanjeng atau Brajamusti yang sama-sama beranggotakan orang-orang limbung yang dangkal dalam kerangka berpikir. Demikian halnya bila kita memerhatikan tabiat dan gerak-gerik kekuasaan militeristik di zaman Nazi, yang pernah memorak-porandakan galeri atau pusat-pusat kebudayaan Jerman.
Gerakan perusuh yang dipelopori organisasi militan ISIS (‘idad asykari) juga pernah membumihanguskan paham-paham kebudayaan lokal, serta meluluhlantakkan situs-situs purbakala yang dianggap sebagai thagut dan sarana kesyirikan.
Terkait dengan itu, kita bisa memahami ketika para kiai dan ulama NU begitu tegas dan peduli pada maraknya gerakan radikalisme kaum perusuh di negeri ini. Prinsip-prinsip yang menjadi moto hidup NU, senantiasa melestarikan tradisi lama yang bermanfaat, sambil bersinergi dengan kearifan-kearifan lokal (local wisdoms).
Di sisi lain, NU cukup kreatif menimba ilmu dari hal-hal baru yang bermaslahat. Kredo ini merupakan benih-benih humanitas yang dapat memperkaya khazanah, serta melahirkan sikap-sikap yang dewasa dalam beragama. Karena bagaimana pun, peran agama harus sanggup bersanding dan selaras dengan kearifan budaya lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
Pola Ajar dan Pola Asuh
Gejala-gejala radikalisme yang marak di negeri ini tak lepas dari problem sosial kita bersama. Tentu saja ada faktor pola ajar dan pola asuh yang merupakan mata rantai ajaran sang guru (mursyid) kepada muridnya. Juga dari bacaan macam apa yang merasuk ke dalam otak dan memori anak-anak didik kita.
Sebagai pemimpin pesantren, penulis meyakini bahwa tidak ada kitab dan ajaran apapun yang menganjurkan anak-anak bangsa agar mendahului kehendak Tuhan. Juga tidak ada guru dan pendidik manapun yang secara sengaja mengajarkan muridnya agar bertindak anarkis atau menganjurkan aksi-aksi kerusuhan.
Logika macam apa yang bisa membenarkan seseorang bertindak anarkis berdasarkan keyakinan yang dipupuk secara sepihak, memandang ajaran agama secara sepotong-sepotong, membuka lembaran kitab dengan memilih bab-bab yang dianggap menyenangkan bagi kepentingan egoisme dan keangkuhannya?
Lalu, bagaimana dengan bab-bab yang lebih urgen dan prioritas, misalnya anjuran untuk bersabar, tawakal, kasih-sayang terhadap sesama, atau keagungan ajaran Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin? Sebagai pendidik, kiranya perlu ditekankan tentang prioritas terpenting dari keberkahan lajunya informasi yang menyertai kehidupan kita, agar jangan mudah terpancing pada hal-hal yang tidak substantif untuk dipersoalkan.
Terorisme dan Kerusuhan
Kerusuhan dalam bentuk terorisme yang digerakkan oleh kemampuan individual, pada umumnya didorong oleh nafsu dan kehendak pribadi, bukan gerakan militansi yang memiliki jaringan ideologi tertentu. Biasanya, sang perusuh bertindak karena didorong situasi mendesak, balas-dendam atau sakit hati kepada pihak atau instansi yang menjadi sasarannya. Dalam istilah kriminologi disebut sebagai gerakan lone wolf yang bertindak secara pribadi, tanpa jejaring sosial, dan umumnya keahlian itu diperoleh dari trik-trik meracik bom melalui internet.
Beberapa motif penting dari gerakan individualis ini tak lepas dari problem yang sering disebut ‘polusi pikiran’ yang menimbulkan depresi dan rasa takut, galau, cemas, pengaruh narkoba, xenophobia, atau kriminal murni. Dalam kasus ini, motif menjadi penting dalam membaca misteri di balik aksi, agar pihak aparat yang berwenang memiliki sikap ekstra hati-hati, bahwa tidak semua aksi kerusuhan dan terorisme, dapat digeneralisasi sebagai tindakan berdasarkan ideologi dan paham keagamaan.
Adakalanya kerusuhan itu didasari oleh paham kelompok tertentu, yang hendak menciptakan sensasi agar masyarakat memperhatikan perjuangan komunitas mereka. Tidak jarang kaum teroris modern justru memanfaatkan perangkat media, baik cetak maupun elektronik, untuk mengampanyekan pesan-pesan perjuangannya.
Sebagaimana yang terungkap dalam aksi-aksi kerusuhan Jakarta pada Mei 1998 – dalam novel Pikiran Orang Indonesia– kita menyaksikan betapa masif dan terorganisasinya suatu gerakan yang terang-terangan mengatasnamakan stabilitas dan keamanan. Namun dalam praktiknya bertindak ofensif bagaikan hukum rimba belantara, yang mengabaikan nilai-nilai humanisme universal.
Saat ini, kita telah memasuki pasca-reformasi, bertahun-tahun masa euforia setelah terkungkung rezim militerisme Orde Baru selama 32 tahun. Di sisi lain, sebagian masyarakat merasa berhak mengekspresikan gagasan dan pemikiran yang kadang melahirkan tindakan merugikan bagi kemaslahatan bersama. Padahal, setiap kebebasan mesti dibatasi oleh adanya kebebasan pihak lain, hingga kita tidak sepantasnya menerobos lampu merah di simpang jalan, pada saat pihak lain memanfaatkan kebebasannya untuk melintasi lampu hijau.
Kita pun tidak selayaknya berhitung, apakah pihak-pihak lain yang mengendarai kendaraan dari arah yang berlawanan itu beragama Islam, Kristen, Konghucu, maupun beretnis Sunda, Jawa, Minangkabau, Batak, dan seterusnya. Jikapun kita beramal baik dalam bentuk harta maupun gagasan pemikiran, apakah juga dihitung-hitung bahwa sang penerima amal tersebut harus beragama Islam maupun non-Muslim?
Justru setiap pemeluk agama harus menampilkan dirinya dengan sikap-sikap yang arif, bijak dan egaliter, hingga diupayakan membuat pihak lain terpesona dan terpukau oleh karena kebesaran dan keagungan dari ajaran-ajaran agama tersebut.
Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayan, Rangkasbitung, Banten
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua