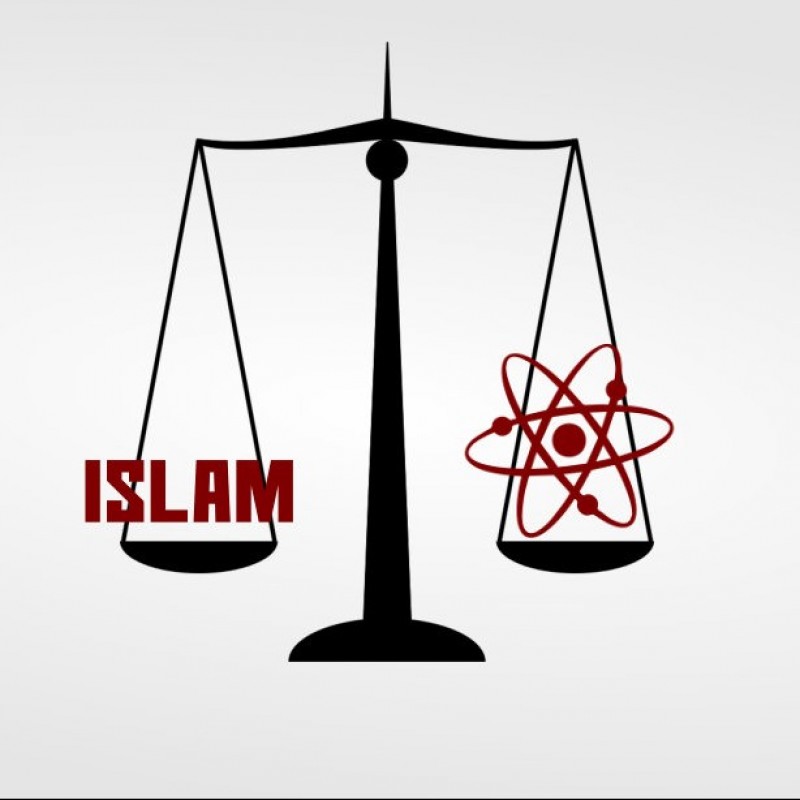Kiai Chusain Ilyas terdiam beberapa detik. Lalu menjawab, “Pertanyaan ini aneh. Lha, semisal tiga janda itu satu keluarga (bersaudara), kalau tidak boleh satu rumah, lalu yang dua mau tinggal di mana,”
Kiai Chusain Ilyas berkali-kali mengulang pernyataan, “Pertanyaan ini aneh,”, sambil memberi penjelasan-penjelasan lainnya. Tiga janda itu, kata Kiai Chusain Ilyas, jangan diperkarakan tentang tinggal serumah atau tidak. Namun yang sebaiknya diupayakan adalah bagaimana mereka mendapat jodoh.
Pertanyaan tersebut, tidak bisa tidak, bersumber dari pemikiran yang ada dalam salah satu tradisi di Nusantara. Asalnya sama dengan pemikiran bahwa kalau seorang lahir pada Selasa Wage menikah dengan seseorang yang lahir pada Senin Legi, akan lebih sulit mendapat rezeki dari pada pasangan lain yang lahir pada Sabtu pahing dan Kamis Kliwon.
Sama usulnya dengan tradisi yang mengatakan bahwa kalau sebuah keluarga berkunjung ke satu pesisir pantai tertentu, tidak boleh membawa nasi kuning. Alasannya, membuka peluang bagi salah satu keluarga pengunjung itu untuk kesurupan.
Tradisi-tradisi semacam tersebut di atas adalah perkara yang tidak masuk di akal dan mustahil. Mustahil yang dimaksud, adalah karena memosisikan hukum Allahu Ta’ala tidak pada tempatnya. Pada contoh pertama, jelas mustahil bagi Allah Yang Maha Memudahkan melarang tiga orang janda hidup dalam satu rumah. Kedua, jelas mustahil bagi Allah Yang Maha Memberi rezeki membatasi kehidupan pasangan suami istri hanya pada hitungan nama-nama hari. Ketiga, mana mungkin ada hubungan antara nasi kuning dengan kesurupan. Kecuali, yang dimakan keluarga itu nasi kuning milik jin atau setan.
Pemikiran berbasis tradisi semacam inilah bid’ah yang mesti diberangus. Modelnya ada beragam jenis di negeri Nusantara ini. Tradisi seperti inilah yang masuk dalam kategori kullu bid’atin dhlalalah. Sementara dalil kullu bid’atin dlalalah bukan “obat gosok” yang bisa dipakai untuk semua persoalan atau kegiatan yang tidak ada di zaman Nabi.
Ada pun amaliyah-amaliyah baik yang bersandar pada semangat keislaman, tentu tidak termasuk pada bidah yang sesat menyesatkan. Misalnya, berziarah ke makam orang tua, orang-orang saleh, dan berkunjung ke kuburan sebelum masuk bulan Ramadhan. Dengan berziarah, seseorang bisa dengan mutlak mengingat kematian, yang kata Nabi Muhammad adalah sebaik-baik nasehat.
Ada pula amaliyah membaca Al-Qur’an sampai khatam di sebuah rumah, sebagai rasa syukur karena akan ada pernikahan di sana. Atau sebagai upaya agar keinginan si empunya rumah dapat dikabulkan. Laku-laku serupa itu adalah bentuk ikhtiar. Membaca Al-Qur’an jelas merupakan kebaikan. Sedangkan Allahu Ta’ala menyukai kebaikan. Jadi masuk akal, kalau membaca Al-Qur’an diposisikan sebagai bentuk rasa syukur, atau pun cara penguat doa. Belum lagi, kalau disandarkan pada dalil-dalil hadist tentang keutamaan Al-Qur’an yang sekian banyak jumlahnya.
Dengan cara memilah dan memilih tradisi seperti itu, Islam bisa disebarkan dengan lebih masif. Terbukti, organisasi Islam terbesar di dunia, bisa eksis hingga kini dengan performa yang tidak kunjung menurun, karena mengadopsi perspektif tersebut. Padahal, ada banyak organisasi Islam lain yang lebih tua, tapi tidak jua mencapai titik yang sama apalagi menyaingi.
Di situlah cermin kelenturan dalam beragama. Sehingga orang beragama dengan bahagia. Namun ingat, tetap dalam kaidah-kaidah prinsip akidah. Kalau berlebihan, dibuat-buat, dan diakal-akali, itu namanya bukan lentur melainkan ngawur. Kengawuran serupa itu biasanya dimiliki para pemikir yang orientalis dan liberalis sentris.
Penulis adalah dosen Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua