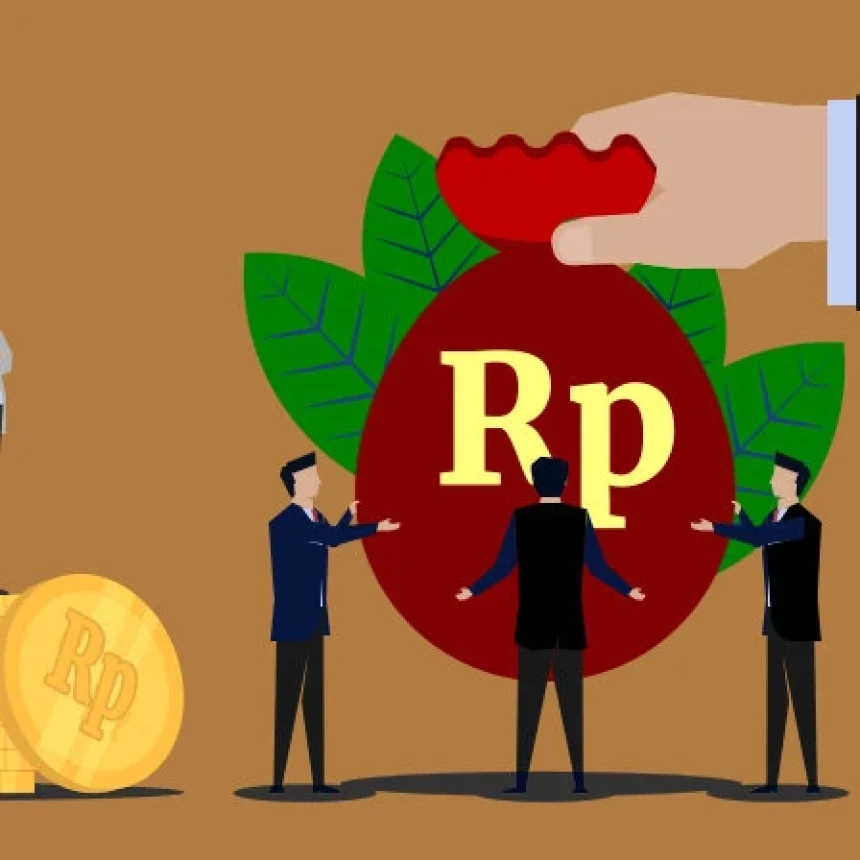Merayakan Angka: Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dan 80 Tahun Kemerdekaan
NU Online · Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:41 WIB
Muhammad Aras Prabowo
Kolomnis
Bangsa Indonesia pada Agustus ini merayakan 80 tahun kemerdekaan. Tentu saja masyarakat bergembira dan bersyukur atas perjuangan leluhur bangsa ini yang berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah selama ratusan tahun. Secara kebetulan, di awal bulan ini juga, ada kegembiraan lain, yaitu pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan capaian di triwulan II-2025 sebesar 5,12% secara tahunan (yoy). Angka 5,12% menunjukkan laju tercepat dalam dua tahun terakhir,
Sekilas 5,12% merupakan kegembiraan bersama dan seolah menegaskan stabilitas di tengah gejolak global. Namun, di balik kebanggaan statistik tersebut, tersembunyi sebuah pertanyaan mendalam: apakah angka pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan kegembiraan substantif yang dicita-citakan?
Delapan dekade merdeka seharusnya bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum evaluasi kritis. Apakah pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran lima persen ini sudah cukup menjadi bukti bahwa seluruh rakyat telah merasakan kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial? Amanat kemerdekaan menuntut lebih dari sekadar statistik makro; ia menuntut keberanian untuk keluar dari jebakan pertumbuhan "setengah hati" dan memastikan setiap keluarga Indonesia merasakan arti merdeka dalam kehidupan ekonominya sehari-hari.
Angka Produk Domestik Bruto (PDB) boleh jadi memberi kebanggaan, tetapi amanat kemerdekaan menuntut lebih jauh — keberanian untuk keluar dari jebakan pertumbuhan setengah hati, memperkecil ketimpangan, serta memastikan setiap keluarga Indonesia merasakan arti merdeka dalam kehidupan ekonominya sehari-hari.
Pertumbuhan 5,12%
BPS pada awal Agustus 2025 mengumumkan kabar yang, sekilas, terdengar menggembirakan: pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II-2025 mencapai 5,12% secara tahunan (yoy). Angka ini adalah laju tercepat dalam dua tahun terakhir, dan sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2024 (5,05%), meskipun masih di kisaran “5-persenan” yang sudah kita kenal selama beberapa tahun.
Kalau kita mundur ke belakang, pertumbuhan Q2 Indonesia selama empat tahun terakhir menunjukkan pola yang relatif stabil: 2022 sebesar 5,44%, 2023 di angka 5,17%, 2024 mencapai 5,05%, dan kini 2025 di 5,12%. Bedanya, motor penggeraknya tiap tahun agak bergeser. Tahun 2022 didorong oleh booming komoditas dan lonjakan transportasi pasca-pembukaan pembatasan pandemi. Tahun 2023, transportasi dan belanja pemerintah jadi penopang. Tahun 2024, sektor akomodasi dan makan-minum memimpin berkat pariwisata yang bergairah. Dan di 2025, “jasa lainnya” dan ekspor barang-jasa menjadi bintang.
Bagi orang awam, angka pertumbuhan ini sering terasa abstrak. Nyatanya, di balik 5,12% ada cerita musiman dan kebiasaan kita. Q2-2025 dibantu oleh momen Lebaran di awal April: mudik besar-besaran, belanja baju dan makanan, padatnya transportasi, serta kunjungan keluarga yang berarti uang berputar cepat di sektor jasa, kuliner, dan perdagangan. Ekspor juga ikut menyumbang dorongan, terutama karena perbaikan perdagangan di kawasan, sementara investasi domestik menunjukkan tanda-tanda membaik.
Kalau dibandingkan dengan negara tetangga di periode yang sama, posisi Indonesia ini cukup tangguh. Vietnam melesat 7,96%, Filipina di 5,5%, Singapura 4,4%, Malaysia 4,5%. Di luar kawasan, Tiongkok tumbuh 5,2% meski dibayangi krisis properti, Amerika Serikat mencatat pertumbuhan kuartalan yang solid, sementara Thailand malah lesu dengan proyeksi setahun hanya 1,8%. Jadi, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, angka Indonesia masih terbilang kompetitif.
Realitas di Balik Angka
Di atas kertas, ya — angka ini selaras dengan momen Lebaran, perbaikan ekspor, dan investasi yang mulai pulih. Tetapi kalau kita menengok ke jalanan dan dompet masyarakat, ceritanya tidak selalu semanis itu. Beberapa indikator lain, seperti penjualan mobil, arus investasi asing, indeks manufaktur, dan bahkan laporan PHK, memberi sinyal pelemahan di sejumlah sektor. Artinya, pertumbuhan 5,12% mungkin belum dirasakan merata.
Apakah kebijakan saat ini cukup responsif terhadap perbedaan antara data makro dan realitas mikro? Pertumbuhan tinggi akan kehilangan makna jika tidak disertai pemerataan manfaat. Di sisi lain, pemerintah sering menonjolkan angka PDB sebagai bukti keberhasilan, padahal kesejahteraan publik juga diukur dari daya beli, lapangan kerja, dan rasa aman secara ekonomi. Narasi optimisme memang penting, tapi transparansi dan pengakuan atas tantangan yang ada sama pentingnya.
Kalau kita telisik empat tahun terakhir, pemicu pertumbuhan cukup jelas: Musim Lebaran yang selalu mengangkat konsumsi triwulan II; Ekspor — di 2022 karena harga komoditas melonjak, di 2025 karena membaiknya perdagangan regional; Investasi dan infrastruktur yang menjaga permintaan agregat saat ekspor goyah.
Namun, ada juga faktor penahan yang tak kalah kuat: Pelambatan global akibat tarif perdagangan, krisis di beberapa negara, dan gejolak pasar; Indikator mikro yang tidak sejalan dengan makro, yang membuat sebagian masyarakat merasa pertumbuhan ekonomi “hanya angka” yang tak singgah di meja makan mereka.
Kritik untuk pemerintah di sini adalah soal arah kebijakan. Jika selama ini pertumbuhan Q2 sebagian besar ditopang faktor musiman seperti Lebaran, bagaimana dengan kuartal-kuartal lain? Apakah strategi pertumbuhan jangka panjang kita terlalu bergantung pada konsumsi domestik musiman, atau sudah mengarah ke peningkatan produktivitas, diversifikasi ekspor, dan penguatan industri padat karya? Tanpa pergeseran strategi, kita berisiko terjebak di angka “5-persenan” selamanya.
Pertumbuhan 5,12% di Q2-2025 sahih, kredibel, dan cukup membanggakan di tengah kondisi global yang sulit. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang relatif resilien di kawasan. Komposisinya — jasa yang menguat, ekspor pulih, investasi membaik — sesuai dengan fenomena Lebaran dan perbaikan eksternal terbatas.
Namun, di balik itu, ada jarak antara data makro dan pengalaman mikro. Sebagian besar warga mungkin tidak langsung merasakan dampak 5,12% dalam bentuk harga yang stabil atau pendapatan yang naik. Ini tantangan yang harus diakui, bukan disamarkan.
Kalau ingin pertumbuhan lebih bermakna, pemerintah harus: Mengurangi ketergantungan pada faktor musiman seperti Lebaran; Mendorong ekspor berorientasi nilai tambah dan memperluas basis industri padat karya; Memperkuat jaring pengaman sosial agar daya beli masyarakat terjaga di tengah gejolak global; Menyelaraskan narasi optimisme dengan pengakuan realitas, supaya kebijakan benar-benar menjawab masalah yang dirasakan masyarakat.
Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya akan jadi angka di laporan BPS, tapi juga denyut yang terasa di setiap rumah tangga — dari pasar tradisional di kota kecil, hingga pusat perbelanjaan di ibu kota.
Muhammad Aras Prabowo, Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua