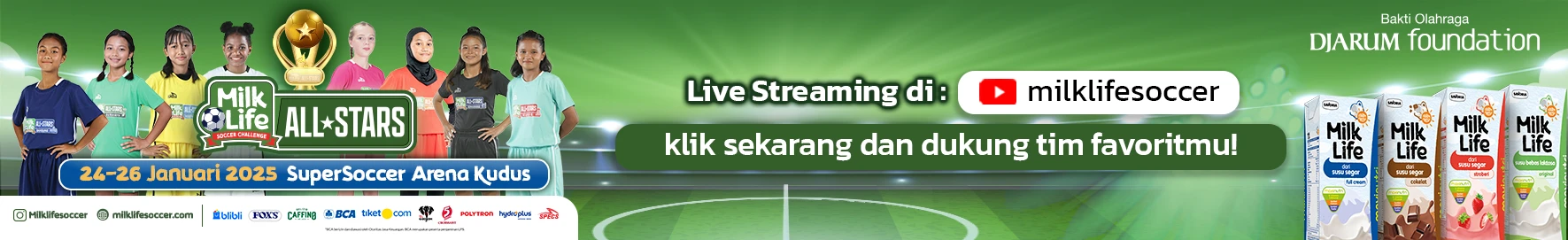MS Wibowo
Kolomnis
Setiap kali ada kasus orang tua melaporkan guru ke polisi karena tak terima dengan cara mendidik anaknya, mayoritas masyarakat bersimpati pada guru atau tenaga pengajar. Meski demikian, fenomena serupa tak henti terus bermunculan. Seolah ada kesan masyarakat punya sikap bahwa guru zaman sekarang boleh menertibkan siswa yang bengal, asal itu bukan anakku sendiri.
Terbaru, kasus Ahmad Zuhdi 60 tahun, seorang guru Madrasah Diniyah di Demak Jawa Tengah, yang harus membayar Rp 25 juta rupiah kepada orang tua siswa karena telah menampar anaknya.
Bermula saat mengajar di kelas pada 30 April 2025. Zuhdi mendengar suara ribut dari kursi belakang. Ketika menengok ke belakang, kepala Ahmad Zuhdi dilempar sandal oleh seorang murid berinisial D. Spontan, Zuhdi menampar D.
Tak terima, D mengadu ke ibunya, Siti. Sontak, Siti marah tak terima dan menyatroni Ahmad Zuhdi. Mediasi pun dilakukan dan berakhir damai. Tapi beberapa minggu kemudian, Siti kembali mendatangi Zuhdi dengan memberikan surat panggilan kepolisan dari Polres Demak.
Zuhdi diharuskan membayar Rp 25 juta kepada Siti sebagai bentuk denda atau uang damai. Padahal gajinya hanya Rp 450 ribu setiap empat bulan. Dari total uang yang Siti minta, Zuhdi hanya sanggup memberikan Rp 12,5 juta. Itu pun hasil pinjaman dari rekan-rekan sesama guru dan menjual sepeda motor.
Atas kejadian yang menimpanya, Zuhdi panen simpati. Kasusnya viral, hingga membuat Siti berbalik minta maaf serta ingin mengembalikan uang Rp 12,5 juta yang telah diberikan Zuhdi sebagai uang damai beberapa hari lalu sebelumnya.
Namun dalam pertemuan kembali yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025, Zuhdi menolak untuk menerima uang dari Siti. Ia mengaku ikhlas mengeluarkan uang tersebut sehingga, menurutnya, tidak perlu dikembalikan.
Kasus serupa yang menimpa Zuhdi telah banyak dialami para guru lainnya di Indonesia. Mereka dilaporkan ke polisi dengan motif yang rata-rata seragam. Coba saja ketik di Google “guru dilaporkan polisi”, maka muncul banyak berita tentang guru-guru dari berbagai daerah di Indonesia dilaporkan ke polisi dengan motif yang kurang lebih sama, gara-gara mendisiplinkan siswa.
Jika kita menengok ke masa lalu, kasus seperti ini sangat jarang terdengar. Salah satu penyebab utamanya adalah pada masa itu guru dan orang tua memiliki titik temu nilai yang sama. Nilai yang antara lain hormat kepada guru, tanggung jawab dalam belajar, dan pentingnya kedisiplinan. Nilai-nilai ini, meski tak tertulis, menjadi semacam kode etik bersama yang mengatur relasi pendidikan di masyarakat.
Guru dianggap orang tua kedua. Menegur siswa adalah bentuk kasih sayang, bukan kekerasan. Saat orang tua memasukkan anaknya ke sekolah atau madrasah, ia menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada guru. Sehingga ketika murid mendapat hukuman di sekolah, orang tua tidak serta merta menyalahkan guru, karena memahami bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat.
Zaman berubah. Nilai-nilai tradisional dari falsafah hidup bangsa kita secara natural mengalami modernisasi yang mengedepankan hak-hak individu, termasuk hak murid, dibandingkan nilai kolektif dalam masyarakat.
Setiap terjadi kasus guru vs orang tua murid, kita seperti disuguhkan realitas berupa benturan antara nilai lama yang jadi pedoman guru dan nilai baru yang diwakili orang tua murid.
Guru dan orang tua tampak hidup dalam realitas sosial yang berbeda. Guru dibentuk oleh nilai-nilai profesi kependidikan dan pengalaman kolektif di ruang kelas. Sementara banyak orang tua membentuk cara pandangnya dari media sosial, pengalaman pribadi, atau narasi populer tentang hak asasi anak. Akibatnya, mereka tidak lagi berdiri di atas fondasi nilai yang sama.
Meski demikian, bukan berarti pandangan nilai-nilai lama di dalam masyarakat telah mati sama sekali. Besarnya simpati publik kepada guru dalam setiap kasus “orang tua melaporkan guru ke polisi” menunjukkan bahwa nilai-nilai moral kolektif dari memori budaya lama itu masih hidup.
Masyarakat masih menyimpan keyakinan bahwa guru adalah sosok yang berjasa dan pantas dihormati. Tindakan menegur dan mendisiplinkan siswa merupakan bagian dari cara mendidik, bukan kekerasan. Justru anak zaman sekaranglah yang dianggap “terlalu dimanjakan”, sementara guru “tidak punya ruang untuk mendidik dengan tegas”.
Artinya di sini, secara narasi sosial, guru masih dianggap berada di pihak yang benar.
Masalahnya, meski nilai kolektif membela guru tapi nilai personal sebagai orang tua sering lebih dominan. Di sinilah muncul paradoks. Kita sedang hidup di masa ketika nilai kolektif lama masih hidup secara simbolik, tapi dalam praktik keseharian telah digantikan oleh nilai-nilai individualistik, emosional, dan instan.
Situasi ini melahirkan standar ganda dari pihak orang tua yang seakan menyatakan bahwa "apa yang dilakukan guru itu benar, asal bukan ke anakku."
Faktor pemicu standar ganda ini antara lain insting protektif orang tua terhadap anaknya yang lebih kuat daripada rasionalitas nilai umum. Sehingga saat tidak terlibat langsung dalam kasus, mereka mendukung guru. Tapi ketika anak mereka yang ditegur, reaksi emosional langsung mengambil alih, bahkan dengan ancaman hukum.
Faktor lainnya adalah ego sosial dan gengsi orang tua modern. Banyak orang tua merasa harga diri atau status sosial mereka ikut dipertaruhkan ketika anaknya dimarahi atau didisiplinkan. Alih-alih introspeksi, mereka membela anak demi “menjaga muka” keluarga.
Banyak juga orang tua memposisikan anak sebagai pusat kebenaran, dengan asumsi bahwa anak tak boleh disalahkan. Masyarakat yang makin mengedepankan hak individu, termasuk hak anak, sering kali tak diimbangi pemahaman akan tanggung jawab sosial. Akibatnya, cenderung melindungi anak secara berlebihan, bahkan ketika anak salah.
Kemudian, ada pula anggapan bahwa sekolah, termasuk guru, hanya sebatas pihak “penyedia layanan pendidikan”, yang posisinya setara atau bahkan lebih rendah sebagai “pelayan” siswa dan orang tua yang merupakan “konsumen”.
Akhirnya, guru kerap merasa kehilangan otoritas dan ruang untuk mendidik dengan tegas. Peranannya tereleminasi. Martabat dan kemuliannya runtuh saat membela haknya untuk didengar, diperhatikan, dan dihormati sebagai pengajar. Apalagi ketika harus dihadapkan dengan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan atau bahkan dihadapkan di muka persidangan.
Masalah kasus-kasus guru vs orang tua siswa ini tak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan regulasi. Persoalannya bukan hanya tentang hukum, tapi terkait nilai yang dijunjung bersama. Karenanya tak sekadar butuh buku aturan panduan etika atau SOP kaku, tapi pembiasaan nilai secara kultural. Perlu ada rumusan nilai atau filosofi baru yang bisa dipahami, diterima, dan diyakini baik oleh guru, orang tua, dan masyarakat.
Sedikit menengok masa lampau, kita memiliki tradisi dan institusi pendidikan dengan filosifi dan nilai yang mengakar kuat, yakni pesantren. Di sana, ada kitab Ta’limul Muta’allim yang jadi rujukan utama atau aturan dalam kegiatan belajar mengajar. Kitab ini ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, seorang ulama yang juga praktisi pendidikan, dan diakui secara bottom-up karena isinya menyentuh langsung kenyataan adab dan praktik belajar.
Namun, efektivitas Ta’limul Muta’allim dalam dunia pesantren bukan semata-mata karena tertulis eksplisit seperti undang-undang, aturan, atau semacamnya, melainkan karena nilai-nilai di dalamnya dijunjung tinggi bersama, menjadi budaya yang hidup dalam keseharian pesantren. Bahkan masyarakat umum, sekali pun tidak membaca kitab ini setiap hari, mereka melihat adab itu hidup di pesantren, diteladankan oleh guru, diulang lewat nasihat, dijadikan panutan, dan ditegakkan oleh komunitas.
Dalam konteks Indonesia modern, kita juga memiliki warisan pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Filosofinya "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani," menyiratkan pendekatan pendidikan yang menyeluruh dan manusiawi. Guru di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat bersama, dan di belakang memberikan dorongan. Falsafah ini bukan sekadar slogan, melainkan bentuk ideal relasi antara pendidik dan peserta didik, serta gambaran dari nilai kepemimpinan yang melekat dalam proses belajar.
Mungkin kita tidak bisa menerapkan isi kitab Ta’limul Muta’lim ataupun serta merta dari falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara di kehidupan modern ini. Tapi yang pasti, kita butuh memiliki nilai dan falsafah yang disepakati dan dijujung tinggi bersama secara ikhlas dan sukarela. Selanjutnya, kita mesti menghidupkan nilai yang disepakati itu, bukan sekadar melalui hukum, tapi melalui kesadaran, pembiasaan, tradisi dan budaya.
Peran semua pihak mutlak dibutuhkan. Dari filsuf, pakar pendidikan, tokoh agama sampai lapisan masyarakat bawah perlu terlibat sebab pendidikan bukan urusan kelas semata. Ia adalah proyek peradaban.
MS Wibowo, pengajar di Madrasah Diniyah Bahrul Ulum, Sukoharjo, Sekampung, Lampung Timur
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Jadilah Manusia yang Menebar Manfaat bagi Sesama
2
PBNU Soroti Bentrok PWI-LS dan FPI: Negara Harus Turun Tangan Jadi Penengah
3
Khutbah Jumat Hari Anak: Didiklah Anak dengan Cinta dan Iman
4
Khutbah Jumat: Ketika Malu Hilang, Perbuatan Dosa Menjadi Biasa
5
Khutbah Jumat: Menjadi Muslim Produktif, Mengelola Waktu Sebagai Amanah
6
Khutbah Jumat: Jadilah Pelopor Terselenggaranya Kebaikan
Terkini
Lihat Semua