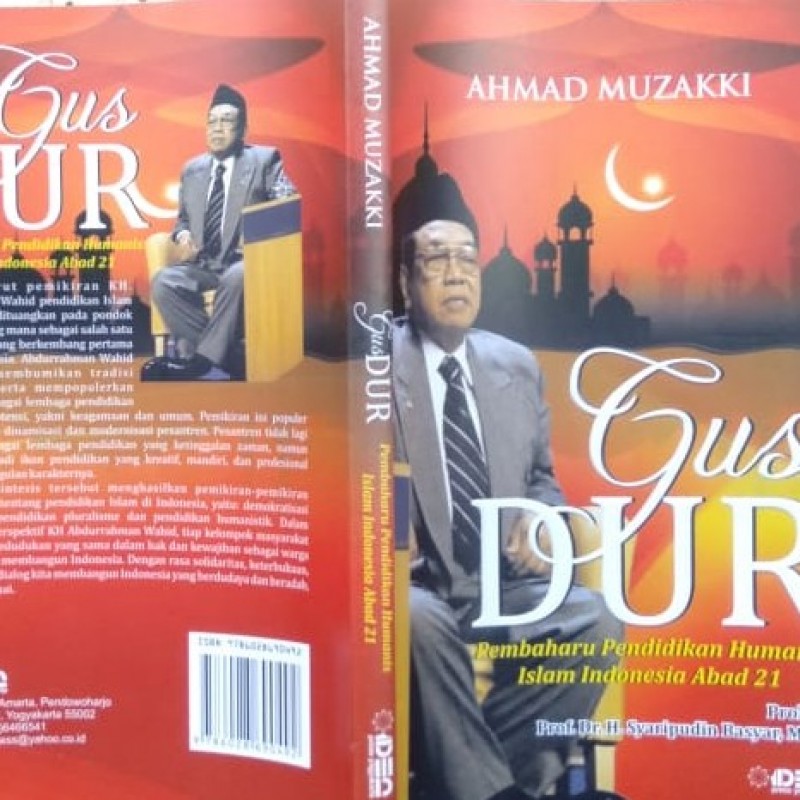Nyai dalam Diskursus Pesantren
NU Online · Senin, 8 Maret 2021 | 05:45 WIB
Muhammad Syakir NF
Penulis
Zamakhsyari Dhofier menyebut salah satu elemen pesantren adalah kiai. Elemen ini merupakan yang paling esensial di antara lainnya, yakni pondok, masjid, pengajian kitab, dan santri. Pasalnya, kiai memegang peranan penting dalam keberlangsungan pesantren.
Intelektual yang menamatkan studinya di Canberra, Australia itu mendefinisikan kiai dalam lingkungan pesantren sebagai sebuah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Kiai juga, lanjutnya, sering disebut sebagai seorang alim, yakni orang yang pengetahuan agamanya sangat mendalam. (Lihat Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. 1982. H. 55).
Meskipun dalam ta’rif (definisi) tersebut tidak menyebutkan laki-laki dan perempuan, tetapi makna kiai yang berlaku umum di tengah masyarakat hanya ditujukan untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Buktinya, tidak ada perempuan yang disebut kiai.
Padahal, banyak di antara mereka yang juga mumpuni di bidang agama. Perempuan di pesantren juga memberikan pengajaran kepada para santrinya. Mereka tidak saja bertugas mendampingi dan melayani kebutuhan kiai, melainkan juga terjun langsung dalam mengurus para santri.
Di kalangan pesantren, perempuan yang demikian itu dikenal dengan sebutan nyai. Namun, definisi nyai sebagai seorang yang ahli di bidang agama Islam, mengajar para santri di pesantren, atau sekadar pendamping kiai tidak masuk dalam pengertian yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V. Lema nyai dalam KBBI V memiliki empat arti berikut.
1. n panggilan untuk perempuan yang belum atau sudah kawin
2. n panggilan untuk perempuan yang usianya lebih tua daripada orang yang memanggil
3. n gundik orang asing (terutama orang Eropa)
4. n gelar jabatan untuk putri di keraton
Barangkali, sebutan nyai itu berasal dari pengertian yang keempat. Pasalnya, sebagaimana diketahui, pesantren berasal dari keraton-keraton di Jawa. Buntet, Gedongan, Balerante, Benda Kerep, dan beberapa pesantren lain di Cirebon, misalnya, berasal dari keraton di Cirebon.
Para kiai di pesantren-pesantren tersebut memiliki garis keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ada kemungkinan lain, nyai di pesantren berasal dari pengertian kedua. Tua dalam pengertian di atas bukan saja secara usia, melainkan juga mencakup kedewasaan dalam bersikap atau kematangan dalam pengetahuan.
Lepas dari pengertian tersebut, nyai di kalangan pesantren merupakan terminologi yang cukup jauh berjauhan dari empat pengertian di atas. Sebab, konteks yang melatari hingga peran yang dilakoni juga berbeda, bukan sekadar usia lebih tua atau jabatan putri keraton.
Oleh karena itu, sudah semestinya nyai dalam pengertian yang dimaksud memiliki tempat khusus di KBBI. Pun dalam dunia pesantren, nyai juga mestinya masuk dalam elemen yang tidak terpisahkan. Kalangan mereka juga memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan pesantren.
Nyai di Pesantren
Syafiq Hasyim menjelaskan bahwa pada mulanya, gelar nyai secara otomatis diperoleh seorang perempuan yang menikah dengan kiai. Ia menyebutnya sebagai sebuah kategori kebudayaan yang tidak berkaitan dengan keilmuan dan keagamaan, melainkan dengan dunia perkawinan. Namun, dewasa ini, lema tersebut berkembang ke arah keilmuan dan keagamaan juga, tidak hanya perkawinan. Pasalnya, para nyai juga, sebagaimana disebut di atas, memiliki peran strategis di pesantren dengan mengajar atau bahkan menduduki jabatan tertentu. (Syafiq Hasyim, Bebas dari Partriakhisme Islam, Depok: Katakita. 2010).
Lebih dari itu, tak jarang juga nyai mengemban tugas sebagaimana kiai. Ia menjadi aktor sentral dalam mengembangkan pesantren. Umumnya, peran tersebut harus dimainkan manakala nyai ditinggal wafat kiainya. Muyassarotul Hafidzoh menjelaskan peran nyai sebagai pemain sentral dalam pengembangan pesantren dalam novelnya yang berjudul Hilda: Cinta, Luka, dan Perjuangan (Yogyakarta: Pustaka 1926 dan Cipta Bersama. 2020).
Tokoh yang disebutnya sebagai ummi menjadi pengasuh pesantren yang dihuni tokoh utama, Hilda. Ummi berperan penting dalam membangun intelektualitas Hilda sebagai seorang santri. Ia bahkan mengizinkan santri kesayangannya itu melanjutkan studinya di jenjang magister. Hal demikian di kalangan pesantren masih tabu.
Syafiq menyebut bahwa memang di masa lalu, santri perempuan bukan disiapkan untuk menjadi seorang intelektuil yang ahli dalam bidang agama, melainkan hanya untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri yang salehah.
Nyai juga terkadang memainkan peran penting dalam pengembangan pesantren kala kiainya masih ada. Hal itu disebabkan sang kiai memiliki kesibukan di luar pesantren sehingga nyai yang memiliki intensitas lebih di dalamnya menunaikan tugas suaminya. Hal ini digambarkan Khilma Anis dalam novelnya yang berjudul Hati Suhita (Yogyakarta: Telaga Aksara dan Mazaya Media. 2019).
Kiai Hannan, mertua Alina Suhita (tokoh utama), sangat aktif di luar pesantren. Istrinya mengambil peran di pesantren dengan mengomandoi segala pengorganisasian dan manajemen pesantren. Pun di generasi berikutnya.
Putranya, Gus Birru, menjelma sebagai seorang aktifis sehingga dunia pesantren tidak lagi akrab dengannya. Karenanya, orang tuanya memilih Alina Suhita sebagai menantunya. Suhita juga yang menggantikan peran istri Kiai Hannan dalam mengelola dan mengembangkan pesantren Al-Anwar.
Bahkan, beberapa tahun belakangan, para nyai membuat forum khusus yang membahas peranannya dalam mengembangkan pesantren. Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Timur menggelar forum tersebut secara nasional, Silaturahim Nasional (Silatnas) Bu Nyai Nusantara pada Juli 2019 di Surabaya.
Hal tersebut diadaptasi para nyai di Jawa Barat dengan membuat Silaturahim Daerah (Silatda) Bu Nyai Nusantara Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini digelar di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon pada November 2019. Jauh sebelum Silatnas dan Silatda, para Bu Nyai juga menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, pada April 2017.
Oleh karena itu, peran perempuan tidak bisa lagi dinafikan dalam pesantren. Aktifitasnya dalam mengorganisasi dan mengembangkan pesantren tidak lagi diragukan. Pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi mereka menjadi sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan dalam rangka memperluas cakupan dakwah Islam.
Penulis adalah alumnus Pondok Buntet Pesantren Cirebon
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
3
Khutbah Jumat: Sesuatu yang Berlebihan itu Tidak Baik, Termasuk Polusi Suara
4
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
5
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
6
Sejumlah SD Negeri Sepi Pendaftar, Ini Respons Mendikdasmen
Terkini
Lihat Semua