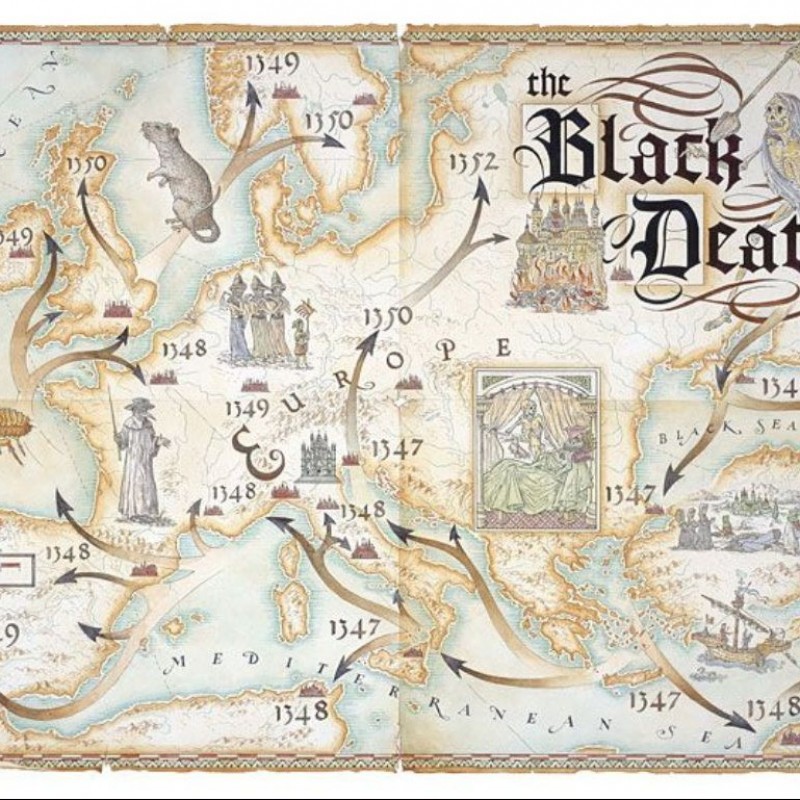40 Tahun Wafat KH Bisri Syansuri (3): Mendirikan Pesantren Perempuan
NU Online · Kamis, 30 April 2020 | 13:30 WIB
Baca: 40 Tahun Wafat KH Bisri Syansuri (2): Ketundukan kepada Guru
Bagi Gus Dur, percobaan Kiai Bisiri itu sngat menarik jika didudukkan pada konteks zamannya. Hampir tiada kiai yang menerima santri putri waktu itu, khususnya di Jawa Timur. Selain itu, menjadi menarik pula karena selama ini, Kiai Bisri selalu mengkonsultasikan lebih dulu dengan gurunya, yakni Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Sementara saat ia menerima santri perempuan, tidak melakukan hal itu.
KH Abdussalam Shohib dalam buku Kiai Bisri Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengutip pendapat cucu Kiai Bisri, Nyai Aisyah Hamid, dalam bukunya itu:
“KH Bisri Syansuri dan Hj. Chodidjah membuat keputusan berani dengan membuka kelas khusus perempuan, sekitar tahun 1920 di Pondok Pesantren Denanyar. Menurut pengakuan Hj Aisyah Hamid Baidlowi, langkah ini yang pertama di kawasan Jawa Timur. “Santrinya adalah anak tetangga sekitar, yang diajar di beranda belakang rumah beliau,” Tulis Gus Abdussalam yang mewawancarai Nyai Aisyah Hamid, di kediamannya, 31 Oktober 2012.
Langkah yang dianggap kurang sesuai di mata ulama pesantren itu, juga tidak luput dari penga– matan gurunya, Kiai Hasyim Asy’ari, sehingga pada suatu hari sang guru datang melihat sendiri per– kembangan yang terjadi di pesantren bekas murid nya itu. Sebagaimana yang diungkapkan Gus Dur, sang guru ternyata tak memberikan izin, tapi juga tak melarangnya.
Meski demikian, walaupun tidak memperoleh izin spesifik dari sang guru, KH Bisri Syansuri memilih melanjutkan pengajaran itu, karena juga tidak ada larangan datang dari guru yang ditundukinya.
Ketetapan hatinya untuk meneruskan percobaan adalah suatu perubahan sikap cukup besar dalam diri KH. Bisri Syansuri. Diterimanya perempuan menjadi santri dalam sebuah pesantren, waktu itu bukanlah hal yang lazim dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Perlahan namun pasti, pesantren yang diasuh oleh Kiai Bisri mengalami perkembangan cukup pesat.
KH Bisri Syansuri kemudian membagi wewenang pengawasan terhadap para santri. Kiai Bisri harus mengasuh dan memberi pelajaran sehari-hari kepada santri putra, sementara istrinya, Hj Chodidjah, mendapat wewenang untuk mengawasi santri putri.
Pembagian wewenang di atas bukan semata-mata disebabkan oleh perkembangan pesantrennya saja, melainkan juga karena perhatian KH Bisri Syansuri, yang mulai tersita. Pada masa ini, sebagai– mana dikisahkan Dahlan dalam buku Sholihah A. Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan, ia banyak disibukan oleh dinamika sosial dan politik seperti awal pembentukan NU sebagai organisasi Islam.
Dalam catatan Aziz Masyhuri disebutkan, ber– kat kegigihanya memperjuangkan perempuan dalam pendidikan pesantren, KH. Bisri Syansuri dan istrinya kemudian membuka Madrasah Diniyah yang santrinya khusus perempuan, di tahun 1930.
Dalam pendidikan pesantren perempuan, KH. Bisri Syansuri memberikan identitas tersendiri bagi para santri perempuannya yaitu mengenakan atasan berupa kebaya dan bawahan berupa jarik “sewek” atau sarung kemudian menggunakan kerudung se– bagai penutup aurat (rambut) yang hanya diselem– pangkan.
Model berpakaian yang demikian ini, menurut Dahlan, merupakan kebiasaan yang digunakan oleh Nyai Hj Chodijah, yang kemudian dipakai sebagai acuan para santri perempuannnya dalam melaksa-nakan pendidikan di pesantren. Ini menandakan adanya identitas baru untuk kaum perempuan dalam pesantren. Sehingga identitas tersebut menjadi khas dikalangan pesantren.
Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
5
Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
Terkini
Lihat Semua