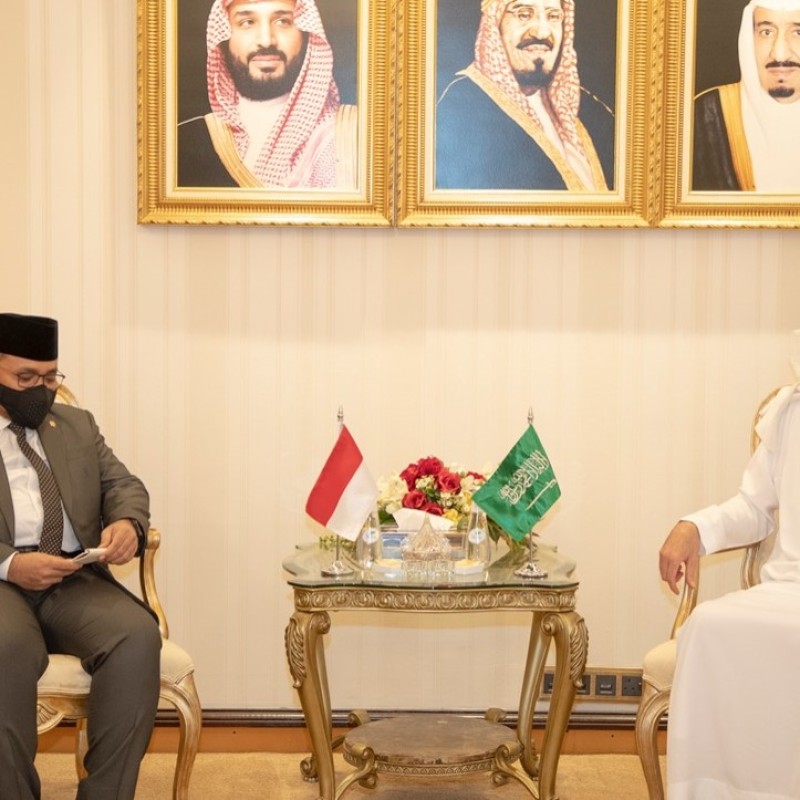Muhammad Syakir NF
Penulis
Ibadah haji merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan bagi Muslim yang memiliki kemampuan. Kemampuan ini dilihat dari segi fisik Kesehatan jasmani dan rohani, juga dari sisi finansialnya, yakni berupa ongkos perjalanan pergi dan pulang, serta biaya hidup keluarga yang ditinggalkannya.
Namun, hal ini menjadi satu kendala tersendiri di zaman dahulu. Pasalnya, perjalanan haji di masa lalu cukup memakan waktu mengingat masih menggunakan kapal api, bahkan kapal layer yang hanya mengandalkan cuaca alam. Perkiraan biaya yang dihabiskan pun sulit untuk ditaksir. Tak pelak, hal ini membuat banyak jamaah haji kehabisan ongkos di tengah jalan.
Dalam catatan Dien Madjid pada bukunya Berhaji di Masa Kolonial (2008: 85), banyak jamaah haji dari Jawa dan Madura yang sudah kehabisan bekal perjalanannya manakala baru sampai di pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Sumatra, seperti Aceh, Padang, atau bahkan baru tiba di Palembang. Hal ini membuat perjalanan ibadah mereka harus berhenti dan tidak dapat dilanjutkan lagi.
Para jamaah haji ini terpaksa harus banting tulang guna melanjutkan misinya dalam menyempurnakan keislaman mereka dengan menunaikan rukun Islam yang kelima. Untuk sampai dianggap cukup sebagai bekal kelanjutan perjalanannya, tentu mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tak kurang dari dua tahun mereka mengumpulkan pundi-pundi demi niat yang sudah ditekadkan bulat-bulat sejak keberangkatannya dari rumah itu terlaksana.
Setelah dirasa bekalnya sudah cukup, mereka akan berlayar menuju Penang (saat ini Malaysia) atau pun ke Singapura. Dua kota tersebut saat itu masuk dalam tanah jajahan Inggris. Dari kedua pelabuhan itu, barulah mereka menumpangi kapal yang dapat mengantarkannya menuju tanah suci.
Namun, tidak semudah itu mereka dapat melanjutkan perjalanan. Pasalnya, harga tiket perjalanan itu tidak murah. Terlebih beban hidup yang harus ditanggung dan dihadapi di daerah pelabuhan memang cukup menguras tenaga dan emosi.
Persoalannya bukan hanya jamaah haji yang memang salah menaksir biaya perjalanan. Namun, di antara mereka juga ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari perantara. Mereka dimanfaatkan dan diambil keuntungannya saja tanpa perlawanan karena ketidakberdayaan mereka. Hal ini termaktub dalam catatan Eric Tagliacozzo pada bukunya The Longest Journey: Southeast Asians and The Pilgrimage to Mecca (Oxford: 2013, 77).
Tak ayal, banyak di antara para jamaah itu akan bekerja di Singapura, di Malaysia, atau pun di tanah suci sendiri selama bertahun-tahun guna menggenapi ongkos perjalanan mereka. Dalam catatan Tagliacozzo, ada juga di antara para jamaah haji yang pada akhirnya terlilit utang sehingga tidak dapat lari dari pekerjaannya.
Penderitaan calon jamaah haji ini tidak berhenti di situ. Jika pun mereka berhasil menaiki kapal untuk perjalanan ke tanah suci, di kendaraan itu pun tak lepas dari penderitaan. Fasilitas yang mereka dapatkan tidak sesuai yang diharapkan. Boro-boro kamar tidur, toilet pun tidak memadai. Namun, mereka menganggap bahwa hal itu menjadi bagian dari suatu cobaan bagi mereka sebelum sampai ke tanah suci.
Mereka yang dapat sampai ke tanah suci tentu sangat bersyukur. Pasalnya, beberapa kawannya masih tertinggal di Singapura. Bahkan di antara mereka terpaksa harus mengubur mimpinya untuk dapat menjalankan ibadah haji dan memilih untuk kembali ke kampung halamannya.
Banyak orang kampungnya yang tidak mengetahui, bahwa calon jamaah haji itu tidak benar-benar telah menunaikan rukun Islam kelima. Mereka hanya sampai di Singapura. Karena itu, dalam terminologi Dien Madjid, mereka disebut ‘Haji Singapura’.
Penulis: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi Muhammad dan 5 Tugas Kenabian
2
Khutbah Jumat: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Bersyukur atas Kelahiran Rasulullah
3
Peristiwa Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Polisi Picu Perlawanan Rakyat Lebih Besar
4
Khilaf dan Kurang Cermat, PBNU Minta Maaf Telah Undang Peter Berkowitz
5
Kesejahteraan Guru Terancam, Kemendikdasmen Hanya Dapat 7% dari Rp757 Triliun Anggaran Pendidikan
6
Kapolda Metro Jaya Diteriaki Pembunuh oleh Ojol yang Hadir di Pemakaman Affan Kurniawan
Terkini
Lihat Semua