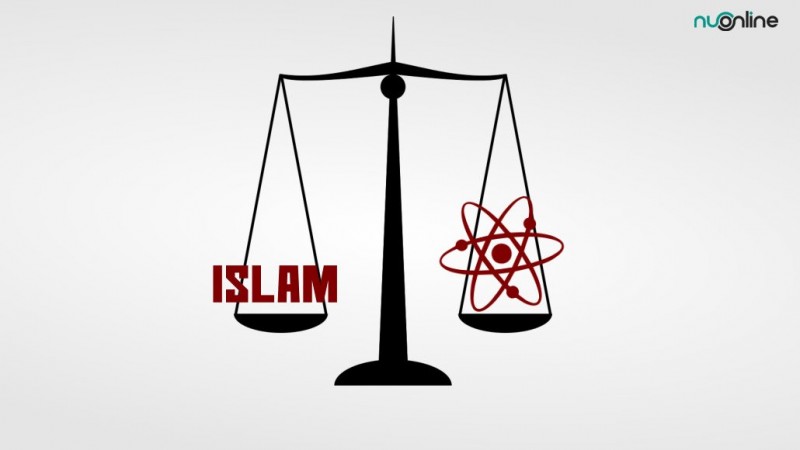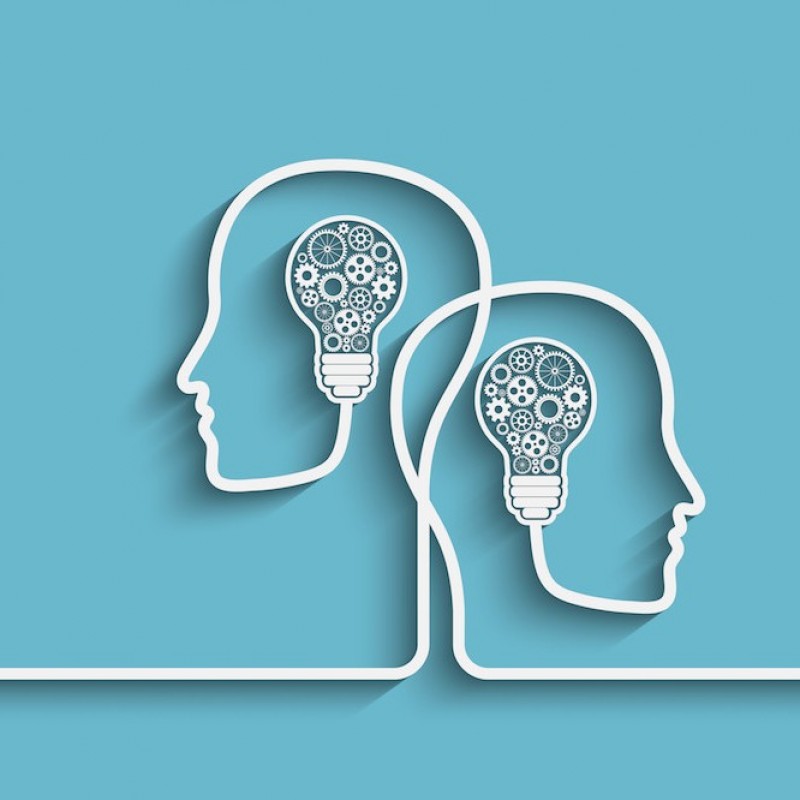Oleh Achmad Murtafi Haris
Ada berita yang mencengangkan dalam rentetan aksi mahasiswa menolak rancangan undang-undang yang akan disahkan DPR September 2019, yaitu ditangkapnya Abdul Basith dosen Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB). Penangkapan itu terkait dengan temuan 28 bom molotov di rumahnya untuk nanti digunakan dalam aksi demo. Jikalau yang membuat adalah mahasiswa atau anak muda barangkali bisa dimengerti karena anak muda mudah emosi dan membuat bom molotov adalah bagian dari emosionalitas itu. Tapi untuk seorang dosen, yang dewasa dan lebih hati-hati dalam berbuat, tentu hal ini mengagetkan banyak pihak.
Tulisan pun bermunculan di media sosial menanggapi kenyataan itu. Di antaranya ada yang mengatakan tidak kaget dengan apa yang terjadi sebab di IPB sebab gejala radikalisme agama memang sering dijumpai di kampus tersebut. Simbol-simbol agama tampil di ranah publik juga begitu terasa, seperti ada dosen yang mengajar pakai jubah, kelas laki-laki dan perempuan dipisahkan, dan penerimaan mahasiswa baru tanpa tes bagi penghafal Al-Qur’an.
Selain IPB, perguruan tinggi umum (bukan agama seperti UIN, IAIN atau STAIN) sudah pernah diekspos oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang fenomena radikalisme di sana. Penangkapan dosen itu pun semakin menguatkan hasil temuan BNPT. Tanpa menuduh bahwa mereka yang dari disiplin keilmuan umum potensial terjangkit radikalisme, seperti yang tampak dalam fenomena global pada pemimpin Alqaeda, Ayman Alzawahiri yang dokter ahli bedah atau Usamah bin Laden yang insinyur, setidaknya menarik untuk dikaji kasus terjangkitnya radikalisme di kalangan mahasiswa umum.
Dalam pembagian ilmu pengetahuan, ia terbagi dalam natural science (ilmu alam) dan social science (ilmu sosial). Ilmu alam mengurus objek gejala-gejala alam sedangkan ilmu sosial mengurus perilaku manusia baik individual maupun kelompok dan hubungan mereka satu sama lain. Karena gejala alam cenderung statis maka apa yang disimpulkan darinya lebih eksak atau pasti jika dibandingkan perilaku manusia yang berubah-ubah dan beragam. Yang terjadi pada tanaman, hewan, tubuh manusia, cuaca, gunung, laut dan udara memiliki keajekan yang tinggi berdasarkan siklus dan hukum kausalitas. Sementara perilaku manusia tidak selalu merespons sesuatu secara sama. Pikiran manusia tidaklah sama. Kata pepatah: rambut sama hitamnya, dalam hati siapa tahu.
Selain itu, tindakan manusia melibatkan emosi yang lagi-lagi tidak sama antara satu dengan yang lain. Di sana terdapat motif dari tindakan manusia yang menjadi pencarian praktisi ilmu sosial. Seperti dalam kajian ilmu hermeneutika, ia berusaha memburu motif dari penulis teks tentang apa yang ditulisnya. Sebuah teks tidak bisa hanya dipahami secara harfiah. Ia muncul sebagai respons atas sesuatu yang bisa jadi akan lain jika kondisinya berbeda. Karena motif lebih bersifat batiniyah, maka apa yang disimpulkan darinya sangatlah relatif.
Ilmu agama pun demikian, ia mengandung relativitas di dalamnya seperti halnya ilmu sosial. Meski kebenaran agama bersifat mutlak dan transendental di luar jangkauan akal manusia, tapi ketika dikaji, ia mengikuti prosedur nalar yang juga relatif. Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Kebenaran (al-Haq) adalah dari Tuhanmu maka janganlah kamu ragu.” Larangan meragukan kebenaran yang datang dari Tuhan menunjukkan kebenaran mutlak ajaran agama. Masalahnya, mereka yang meyakininya ternyata beragam. Di dalam Islam ada banyak paham dan aliran dan bahkan pada doktrin tauhid yang paling fundamental ternyata pandangan tentang sifat Tuhan tidaklah sama. Perbedaan itu terjadi lantaran perbedaan sudut pandang dan jangkauan nalar dalam menafsirkan teks terkait sifat Tuhan. Jadilah di sini, kebenaran agama yang mutlak menjadi relatif pada tataran keilmuan. Sementara kemutlakan kebenarannya berada pada tataran keyakinan atau keimanan.
Mereka yang berangkat dari ilmu alam atau ilmu pasti, ketika berinteraksi dengan dunia keagamaan, degree kepastian kebenaran meningkat. Ilmu alam yang tingkat kebenarannya tinggi bertemu dengan kebenaran mutlak agama sehingga semakin meningkatkan kepastian kebenaran. Di sinilah potensi ekstremitas muncul tanpa menyadari bahwa secara ilmu, agama juga berada pada kebenaran relatif seperti halnya ilmu-ilmu yang lain.
Objek kajian keagamaan yang mencakup banyak aspek duniawi dan ukhrawi yang secara fiqih berada pada lima tingkat hukum yang lima: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, dipukul rata menjadi hanya wajib dan haram. Masalah sosial dan politik yang secara hukum bersifat fleksibel dipandang sebagai sesuatu yang saklek tanpa boleh ditawar. Ajaran agama yang sebenarnya warna-warni, terbukti dengan banyaknya pilihan dengan zona abu-abu yang luas menjadi hanya hitam-putih.
Pandangan tentang aqidah yang tidak boleh diganggu gugat diterapkan pada pandangan politik yang sebenarnya longgar dan dinamis. Jadilah pandangan politik Islam oleh sebagian kelompok dianggap sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan hidup mati. Padahal, apa yang ada, sudah mengakomodasi nilai-nilai politik Islam meski dengan nomenklatur non- Arab seperti Pancasila. Demikian juga dengan ide khilafah (dunia Islam di bawah satu kepemimpinan) yang sebenarnya sudah ada padanannya yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menghimpun seluruh negara-negara Islam (57 negara) di bawah kendali seorang chairman ditolak karena beda nomenklatur.
Mereka yang berlatar belakang pendidikan umum sering terjebak dalam pandangan politik Islam semacam ini karena dianggap bagian dari doktrin agama yang tidak bisa diubah (tawqifi). Padahal, ia bisa berubah bentuksejauh tidak melanggar prinsip-prinsip tertentu (ijtihadi). Meski demikian, harus diakui bahwa dari kalangan pendidikan umum telah banyak muncul da’i-da’i yang sukses. Kemampuan mereka dalam menjelaskan pandangan Al-Qur’an tentang fenomena alam (al-ayat al-kawniyyah) dan ayat-ayat medis seperti tentang proses pertumbuhan janin patut mendapat apresiasi yang tinggi. Sebut saja Zakir Naik (dokter ahli bedah yang menggeluti ilmu perbandingan agama) asal India, Mustafa Mahmoud (dokter pengasuh acara TV Mesir‘al-Ilm wa al-Iman’dan Harun Yahya penolak teori Evolusi Darwin asal Turki adalah muballigh kelas dunia yang mampu mengorespondensikan pandangan Al-Qur’an dan temuan sains. Di Indonesia terdapat Agus Mustofa yang berlatar belakang teknik nuklir dengan karya-karya yang produktif.
Di balik prestasi dakwah ilmiah itu, banyak fenomena para akademisi ilmu-ilmu umum yang tergiring masuk dalam gerakan Islam politik yang berseberangan dengan pemerintah. Ulama tradisional dan pandangan mereka ditolak karena dianggap berselingkuh dengan penguasa yang berideologi sekuler. Padahal sistem pemerintahan di negara-negara Islam telah menjadikan Islam sebagai sumber hukum berbeda dengan di Barat yang memang sengaja menjauhkan agama dari urusan duniawi. Sulitnya memahami akomodasi ajaran Islam dalam bentuk yang lain, salah satu faktornya adalah penerapan kebenaran mutlak di ranah yang salah. Ranah politik adalah ranah ijtihadi yang kebenarannya relatif. Ia bukan absolut yang tidak ada tawar-menawar di situ apalagi diperjuangkan hingga membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Penulis adalah dosen UIN Sunan Ampel Surabaya