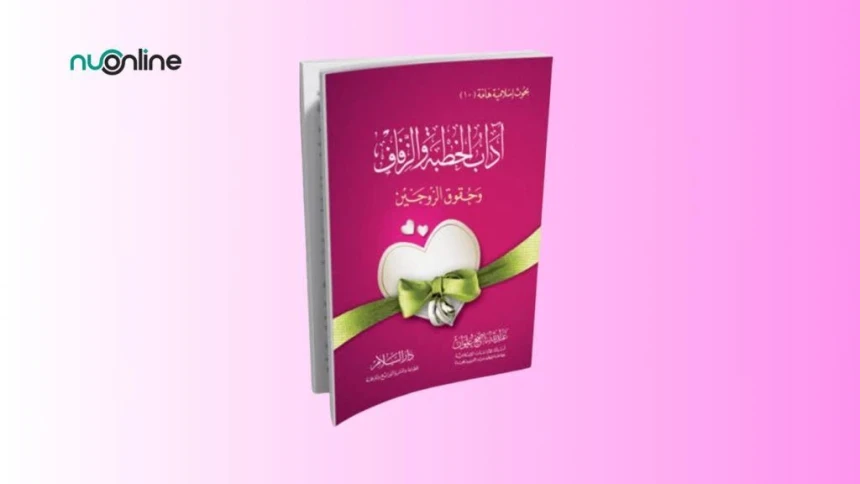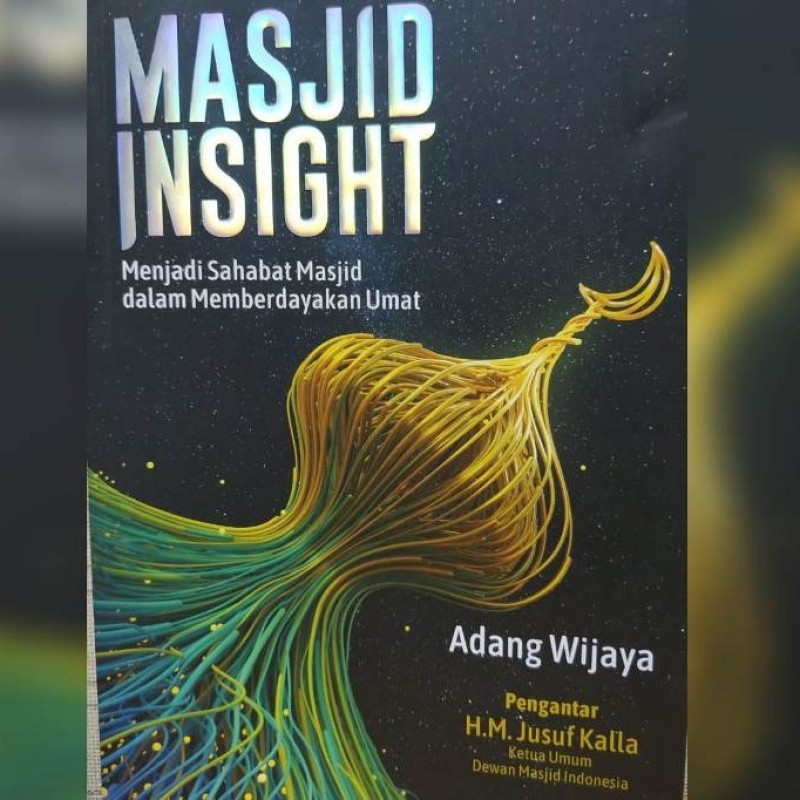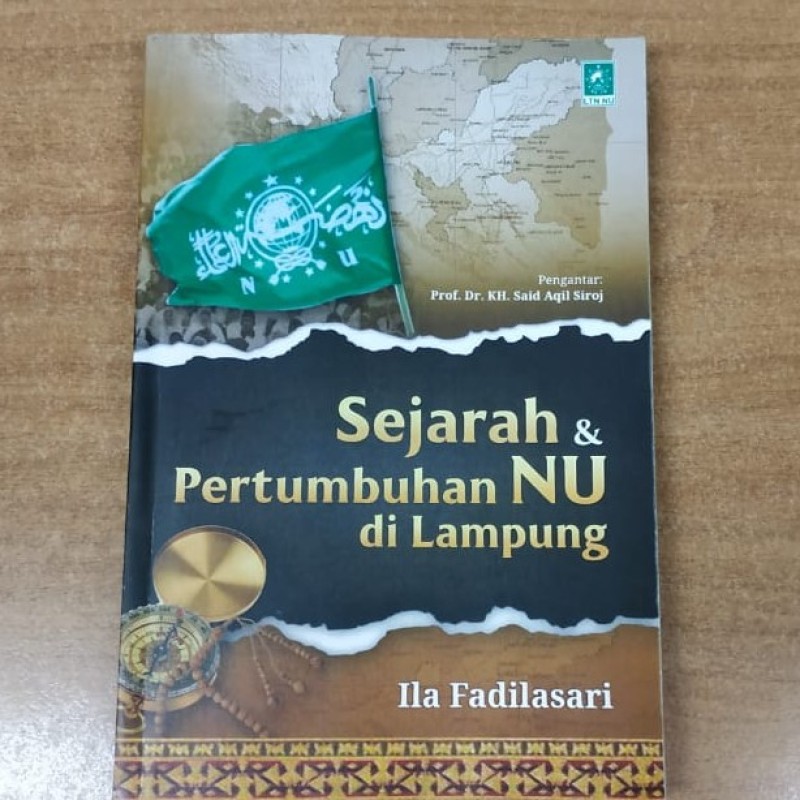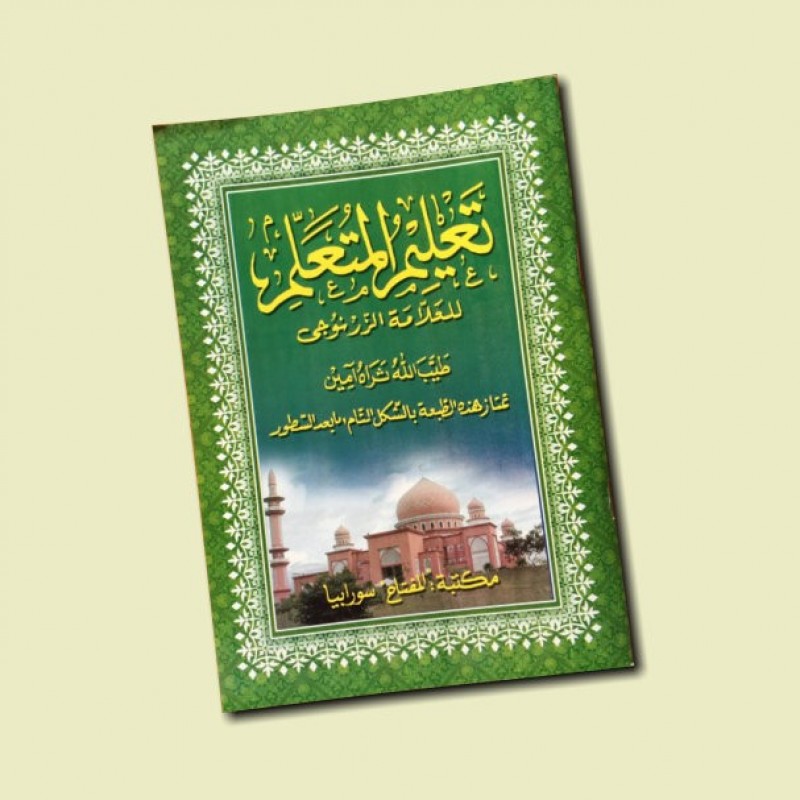Adabul Khitbah waz Zifaf, Kado Pernikahan yang Relevan dengan Zaman
NU Online · Jumat, 9 Februari 2024 | 17:00 WIB
Muqoffi
Kolomnis
Di era modern ini, konsep pernikahan perlu disajikan lebih elegan. Tidak hanya berdasarkan nash A-Qur’an dan hadits sebagai rujukan primer, tapi perlu data-data penunjang yang rasional dan faktual untuk membangun kesadaran umat dalam mengaktualisasikannya. Indikator ini ditemukan cukup memadai dalam kitab Adâbul Khitbah waz Zifâf wa Huqûquz Zaujain karya Abdullah Nashih Ulwan.
Abdullah Nasih Ulwan berasal dari Syria yang lahir pada tahun 1928 H di Bandar Halb. Pada usia 15 tahun, Abdullah Nasih Ulwan sudah menguasai bahasa Arab dengan baik serta hafal Al-Qur’an 30 Juz. Ia lulus di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1952. Gelar doktornya diperoleh pada tahun 1982 dari sebuah Universitas di Pakistan, yaitu Universitas al-Sand. (Parina, Orang Tua sebagai Pendidik Dalam Perspektif Abdullah Nasih Ulwan, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 14, No. 1, 2021, halaman 18-20).
Kitab Adâbul Khitbah waz Zifâf mengurai sepuluh pembahasan tentang etika suami-istri, mulai dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam, tips ideal memilih pasangan, etika berhubungan intim, pelaksanaan walimatul ‘urs, hak-hak suami-istri dan rehabilitasi problem-problem rumah tangga. Dalam setiap pembahasan penulis menyajikan pendahuluan, materi inti kemudian penutup.
Baca Juga
Menikah Bukan Ibadah
Kitab Adâbul Khitbah waz Zifâf wa Huqûquz Zaujain memiliki karakteristik yang tidak banyak ditemui di beberapa kitab fikih. Pertama, Al-Qur’an dan hadits sebagai dalil istinbath hukum dikuatkan dengan data valid dan representatif dari ilmu kedokteran. Contoh, dalam menjelaskan larangan melakukan jima’ ketika haid selain merujuk pada ayat Al-Qur’an:
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ
Artinya, ”maka jauhilah istri ketika haid”. (QS. Al-Baqarah: 22).
Dan hadits Nabi Muhammad Saw:
مَنْ أَتَى حَائِضًا ... فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ
Artinya, ”barangsiapa yang menjima’ istri ketika haid, maka sungguh kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.”
Juga dikuatkan dengan temuan klinis bahwa melakukan jima’ pada waktu haid dapat menghadirkan penyakit yang membahayakan, seperti merusak alat reproduksi wanita, infeksi rahim, kemandulan, penyakit sifilis dan lain sebagainya. Bahkan temuan itu merupakan hasil konsensus dari para dokter. (Adâbul Khitbah waz Zifâf..., halaman 57).
Berbeda dengan kitab-kitab lain, misalnya kitab Tuhfatut Thullab yang hanya menjelaskan keharamannya (Zakariya bin Muhammad al-Anshari, Tuhfatut Thullab, [Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971], halaman 35). Interpretasi lafaz أذى dalam kitab-kitab tafsir sebagai illat diharamkannya jima’ ketika haid juga tidak dirinci dengan macam-macam penyakitnya, misalnya Tafsir Ar-Razi yang hanya menjelaskan أذى sebagai قذر (kotoran). (Muhammad ar-Razi Fakhru ad-Din, Tafsir Ar-Razi, [t.t.: Dar al-Fikir, 1981], halaman 68).
Begitu juga anjuran dalam hadits untuk menikahi wanita subur (الولود) disempurnakan dengan data kedokteran yang menjabarkan manfaat-manfaatnya, yaitu menikahi wanita subur pada umumnya menjadi istri yang sehat dan kuat. (Adâbul Khitbah waz Zifâf..., halaman 22).
Dengan pola ini, maka hukum fikih yang ditetapkan lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh umat Islam modern, karena Islam dihadirkan lebih komunikatif dengan menjabarkan manfaat logis dari konklusi hukum fikih yang ditentukan, tidak terkesan hanya bersifat dogmatis dan otoritatif dari syari’.
Kedua, penyajian fikih suami-istri tidak hanya bersifat teoretis dari sumber Islam yang primer maupun yang sekunder tapi juga diperdalam dengan bukti otentik dari kondisi sosio-kultural yang memiliki relevansi dengan konten yang dibahas.
Misalnya dalam larangan berstatus jomblo, Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan data akurat tentang bahaya-bahayanya di masyarakat. Menurutnya, status jumblo sudah menyebabkan banyak orang Amerika yang terdeteksi penyakit homoseksual dan lesbian, bahkan di kota New York saja, orang yang terang-terangan membuka identitas diri mencapai setengah juta jiwa. (Adâbul Khitbah waz Zifâf..., halaman 12).
Ketiga, ketentuan hukum yang dijabarkan lebih sistematis sejalan dengan problematika hukum yang dihadapi masyarakat saat ini. Contoh, dalam mengurai pembahasan khitbah (pertunangan), penulis kitab melengkapinya dengan ketentuan hukum menggunakan cincin tunangan yang haram karena dua unsur: tasyabbuh dan menggunakan cincin bagi laki-laki. (Adâbul Khitbah waz Zifâf..., halaman 27), di mana tukar cincin menjadi seremonial wajib dalam acara pertunangan yang tidak dibahas tuntas dalam kitab lain di materi pertunangan.
Dalam kitab lain dijelaskan haramnya laki-laki memakai cincin emas tapi tidak haram bagi wanita, seperti dalam kitab Fathul Mu’in, Fathul Qarib dan kitab-kitab familiar lainnya di pondok pesantren. Dalam kitab I’anatut Thalibin dijelaskan anak kecil itu sama dengan wanita dalam bolehnya menggunakan cincin emas. Adapun waria itu tidak sama, yang sama adalah dengan laki-laki yang diharamkannya. (Muhammad Syattha ad-Dimyathi, I’anatut Thalibin, [t.t.: Dar al-Fikr, 2019], halaman 180).
Kitab Fathul Mu’in, Fathul Qarib, I’anatut Thalibin dan kitab-kitab sejenisnya, selain penjelasan tentang itu tidak ditemukan dalam bab pertunangan, juga tidak cukup memberi argumentasi terhadap budaya tukar cincin dalam pertunangan. Karena keharaman budaya tersebut tidak hanya dari unsur menggunakan cincin bagi mempelai pria tapi juga karena aspek tasyabbuh.
Keempat, dalam menjelaskan pekerjaan domestik, Abdullah Nashih Ulwan menguraikan sangat elegan dengan menyebutkan sebagai unsur tugas yang relevan dengan spesialisasi dan karakteristik seorang wanita (Adâbul Khitbah waz Zifâf..., halaman 6) sebagaimana ia ungkapkan:
فَالْمَرْأةُ تَعْمَلُ ضِمْنَ اخْتِصَاصِهَا ومَا يَتَّفِقُ مَعَ طَبِيْعَتِهَا وَأنُوْثَتِهَا. وَذلكَ فِي الْقِيَامِ بِحُقُوْقِ الزَّوْجِ وَالإشْرَافِ عَلى إدَارَةِ الْبَيْتِ وَالْقِيَامِ بِوَاجِبِ الْحَضَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ
Artinya, “Wanita bekerja sesuai dengan potensinya, karakter dan sifat kewanitannya. Itu adalah melaksanakan hak-hak suami, mengatur pengelolaan rumah dan melaksanakan kewajiban pengasuhan dan pendidikan.”
Narasi yang dipakai akan memberi lecutan semangat kepada kaum ibu untuk tetap konsisten menjalankan sesuai dengan tradisi yang sudah mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Sekaligus menjadi praktik yang lebih utama, sebagaimana pandangan Syâfi’iyyah, Hanâbilah dan sebagian Mâlikiyah bahwa yang lebih utama mengikuti tradisi yang sudah berlaku, yaitu mengerjakan semua tugas rumah tersebut. (Wizârah al-Auqâf wa as-Syu’ûn al-Islâmiyah, al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kuwitiyyah, [Kuwait: Dzât al-Salâsil, 1986], halaman 44).
Kitab-kitab lain yang tidak memilih pola itu bahkan menjelaskan pekerjaan domestik sebagai tanggungjawab yang tidak wajib dilaksanakan oleh istri tanpa penjabaran lebih rinci dan mendalam akan berdampak negatif kepada kaum ibu untuk tidak semangat bekerja di dapur dan sumur atau bahkan bisa mengabaikannya, seperti kitab Uqûdul Lujjayn yang justru menyampaikan bahwa pekerjaan domestik seperti memasak makanan, menyiapkan roti, mencuci pakaian, dan menyusui anak-anak bukan kewajiban para istri. (Syekh Nawawi,‘Uqûdul Lujjayn, [Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971], halaman 11).
Namun dalam kitab ini terdapat penjelasan yang kurang rinci dan berpotensi membuat umat merasa kesulitan. Misalnya, dalam mengemukakan diskursus nikah muhallil, penulis kitab hanya menyampaikan bahwa nikah muhallil itu batil (haram). (Adâbul Khitbah waz Zifâf..., halaman 77-78).
Hal itu merupakan konklusi hukum fikih yang cukup memberatkan, mengingat nikah muhalil kadang dipraktikkan oleh umat Islam saat ini dan menjadi solusi untuk menyatukan cinta kembali. Berbeda dengan kitab lain yang mengulas secara rinci: selain yang haram juga praktik-praktik yang sah dan boleh, seperti dalam kitab al-Hawi al-Kabir diuraikan bahwa nikah muhallil sekali pun mensyaratkan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh suami yang pertama itu hanya makruh dan akad nikahnya sah.
Nikah muhallil yang tidak sah itu jika setelah dihalalkan kemudian dinyatakan tidak ada pernikahan lagi antara keduanya, sehingga dipastikan bercerai dengan sendirinya. (Al-Mawardi Al-Bashri, Al-Hawi Al-Kabir [Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971], halaman 331).
Identitas Kitab
Penulis: Abdullah Nashih Ulwan
Penerbit: Dar as-Salam.
Tempat terbit: Mesir.
Tahun Terbit: 2013.
Tebal: 80 halaman.
Ustadz Muqoffi, Dosen IAI NATA Sampang Madura - Guru Pon-Pes Gedangan
Terpopuler
1
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
2
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
3
Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Ketum PBNU Ajak Bangsa Teguhkan Persatuan
4
Kiai Miftach Jelaskan Anjuran Berserah Diri saat Alami Kesulitan
5
Tali Asih untuk Veteran, Cara LAZISNU Sidoarjo Peduli Pejuang Bangsa
6
Gerakan Wakaf untuk Pendidikan Islam, Langkah Strategis Wujudkan Kemandirian Perguruan Tinggi
Terkini
Lihat Semua