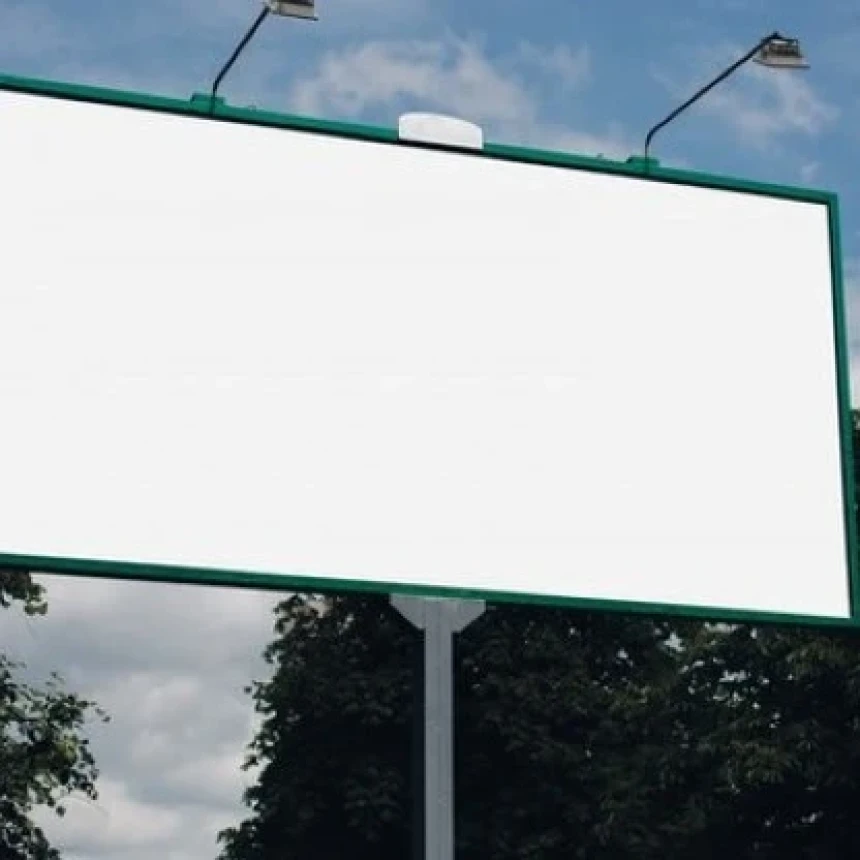Cerita Pendek Pensil Kajoe
Seorang laki-laki berkemeja putih bersepatu pantofel turun dari mobilnya, tepat di gerbang cungkup tempat orang-orang yang pernah menjadi bagian dari sejarah hidupnya bersemayam menunggu keputusan Sang Pencipta. Beberapa orang yang melintas dekat pekuburan kampung itu saling berbisik dengan temannya.
"Itu kan Mas Temon, yang dulu pernah di-momong Ni Rawen?" ujar pria yang melilitkan sarungnya di pinggang sambil memanggul cangkul.
"Dari mana kamu tahu, Kang?" orang yang di sebelahnya balik bertanya.
Baca Juga
Pernikahan Rasmin
"Ya, aku yakin kalau itu memang Temon teman mainku waktu kecil. Dulu kami sering memanjat pohon sawo kecik di sana," ujarnya sambil membenarkan tudungnya.
"Ohh, hebat ya Temon yang sekarang? Dia bisa jadi orang sukses."
Laki-laki itu ternyata Temon, anak susuan Ni Rawen. Dia sudah menjadi orang sukses di kota. Saat rindu kampung halaman, Temon yang kini dipanggil Pak Bos selalu menyempatkan diri untuk pulang, tak lupa dia menziarahi makam orang tua dan kakek neneknya, Ki Kartomiardjo dan Nini Kartomiardjo.
Dukuh Pekowen ikut andil mengisi jiwanya. Di depan batu nisan Ni Rawen, dia menangis sesenggukan teringat betapa penderitaan perempuan yang menyandang predikat sebagai pemain ebeg perempuan. Tangannya terlihat meletakkan sesuatu: karangan bunga.
Baca Juga
Baliho
Dia paham betul dan masih terekam dalam kepalanya saat dia berumur enam tahun, selalu diajak memetik bunga kesayangan di pinggir pematang sawah di tanah kelahirannya. Di sebelahnya nisan Ki Nartam, sang pemusik calung tampak tak terawat. Nisan yang hanya berupa balok kayu sudah ditumbuhi lumut dan jamur. Tak terlihat lagi tanggal lahir dan wafatnya musisi calung.
Langit di atas cungkup tua mulai meredup. Hawa dingin mulai berembus di sekeliling makam. Nisan-nisan beku, bergeming. Seolah menatap pada sosok pria yang pernah dikenalnya. Seorang anak kecil kurus dengan ingus yang meleleh dari hidungnya kini telah tumbuh menjadi seorang laki-laki gagah.
Temon menengadah ke langit, di tatapnya awan kelabu yang berarak ke atas pekuburan di pedukuhan itu. Dia beranjak bangkit, sambil mengibaskan tangan di celananya, menyingkirkan rerumputan dan tanah yang menempel.
Dia pun melangkah pelan di antara mereka yang tengah tertidur di pembaringan abadi. Tiba di gerbang cungkup, dia kembali memalingkan wajahnya menatap deretan makam yang seolah berseru agar dia jangan pergi. Ada sesak di dadanya yang membuat kedua matanya memanas oleh air mata yang mengembang. Disekanya dengan punggung tangan.
Baca Juga
Peci Hitam Kiai
Dengan berat hati dia harus pergi. Pulang ke rumah barunya di kota. Di sana, istri dan kedua anaknya menunggu.
Mobil sedan berwarna hitam metalik meluncur di jalan kampung. Jalan yang dulu hanya berupa tanah kini sudah berlapis aspal. Di sebuah sungai kecil yang tak jauh dari cungkup, dia menghentikan laju mobilnya dan berjalan keluar dari dalam mobil.
Airnya masih bening, sama seperti waktu aku mandi di sini bersama Sikun, Dirman dan Narto. kata batinnya sambil mengempaskan napas, melepaskan sesuatu yang menyesak di dadanya.
Setelah menyambangi beberapa sudut kenangan di kampungnya, Temon kembali melanjutkan perjalanan. Dia harus segera tiba di kota, sebab besok dia harus masuk kerja lagi.
Kenangan masa lalunya kembali bersliweran dalam benaknya. Film tentang kehidupan di masa lalunya kembali diputar dengan runutnya tanpa terjeda sedikitpun. Pahit getirnya pengalaman masa kecil mengantarkannya menjadi sosok yang tegar dan sukses seperti sekarang.
**
Baca Juga
Golok Penghabisan
Perjalanan yang ditempuhnya lebih kurang dua jam, akhirnya Temon tiba kembali di kota tempat tinggalnya sekarang. Kota yang selalu dibisingkan oleh deru jalan raya, asap-asap karbondioksida menyebabkan sesak dan sakit kepala, kota yang selalu disibukkan dengan rutinitas orang-orang yang mengejar kebahagiaan dunia. Sangat jauh berbeda dengan kampung kelahirannya. Kampung dengan suasana magis, berudara sejuk dengan orang-orangnya yang polos jauh dari kata hedonism. Hiburan satu-satunya yang berkesan kala, ebeg; bintang ebeg perempuan paling terkenal dan menjadi primadona siapa lagi kalau bukan Ni Rawen, perempuan paling ayu pada zamannya yang pernah ikut berjasa menggendongnya.
Halaman rumah Temon cukup luas, tanahnya dilapisi paving diselingi rumput-rumput yang dirawat rapi, lampu-lampu taman menyala di beberapa sudut halaman. Mendengar deru mesin mobil suaminya, seorang perempuan cantik menyambutnya di depan pintu diiringi dua orang anak laki-laki kembar, usianya baru lima tahun. Sedangkan anak ke tiganya ada dalam gendongan istrinya, dia seorang bayi perempuan usianya baru dua tahun.
"Kok sampai malam, Pah?” tanya istrinya.
"Tadi mampir sebentar ke Dukuh Pekowen. Kangen rasanya,” jawab Temon.
Baca Juga
Seraut Wajah Perempuan Baliho
“Yaah, kok adek nggak diajak?” rengek dua anak kembarnya.
Temon terseyum, kedua tangannya mengelus kepala anaknya, dia masuk ke dalam rumah dan menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa.
***
Kehadirannya di Dukuh Pekowen menjadi buah bibir orang-orang yang mengenalnya, informasi itu di dapatkan oleh Kang Sujadi yang waktu itu pernah melihatnya sedang berada di cungkup.
Baca Juga
Aku Ingin Menjadi Atlet Lari Kursi Roda
“Kenapa kamu tak menyapanya, Jad?” ujar Man Sutar.
“Saya ragu, Man. Takut tak dijawab. Sebab sekarang dia sudah jadi orang kaya,” jawab Sujadi.
“Kamu jangan berprasangka buruk begitu, belum tentu Temon seperti itu,” Lastri menimpali.
Perempuan penjual rujak sejak Ni Rawen masih tenar menjadi penari ebeg.
Baca Juga
Percakapan-percakapan yang Tertinggal
“Aku saksinya,Temon itu anak yang baik. Aku mengenalnya saat dia masih kecl.”
"Kalau dia lupa, tidak mungkin dia akan datang menziarahi makam leluhur kampung ini. Mungkin dia sedang sibuk, doakan saja semoga lain waktu kita bisa bertemu dengannya lagi,” ujar Lastri.
“Mas Temon…,” suara Ningsih tercekat. Perempuan yang pernah menaruh hati padanya tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Cintanya harus kandas, bukan berarti laki-laki pujaan hatinya menolak, tapi kedua orang tuanya sudah menjodohkannya dengan amtenar yang punya lahan perkebunan luas di kampung itu.
***
Temon tidak juga memejamkan matanya, perasaannya masih terpaut dengan kenangan di kampung kelahirannya. Dia ingin kembali ke tempat itu menemui sahabat-sahabatnya yang masih hidup.
Telinganya berasa panas, konon kalau telinga panas berarti ada orang lain tengah membicarakannya. Memang benar, Temon telah menjadi berita hangat di Dukuh Pekowen, tanah kelahirannya. Kampung yang menampung segala eksotisme ebeg Ni Rawen, kampung yang menjadi rahim bagi kelahirannya.
Baca Juga
Obrolan di Teras Mushala
Tumiyang,08082021
Pensil Kajoe, adalah nama pena dari Didit Kristianto lahir di Banyumas, 27 Januari. Tulisan-tulisannya baik cerpen maupun puisinya sudah dimuat di berbagai koran cetak dan online tanah air. Telah membukukan 21 antologi tunggal dan lebih kurang 50 antologi bersama. Saat ini menjadi kolumnis majalah Djaka Lodang, Yogyakarta.
Terpopuler
1
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
2
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
3
Rais 'Aam PBNU Ajak Umat Islam Tanggapi Masa Sulit dengan Ilmu
4
Ketua PBNU Nilai BPKH Penting Tetap sebagai Lembaga Independen
5
Tidak Hanya Pelajar, BGN juga Targetkan MBG Menyasar Ibu Hamil dan Menyusui
6
Penerapan Sumpah dan Bukti di Pengadilan Islam: Studi Qasamah dalam Kasus Pembunuhan
Terkini
Lihat Semua