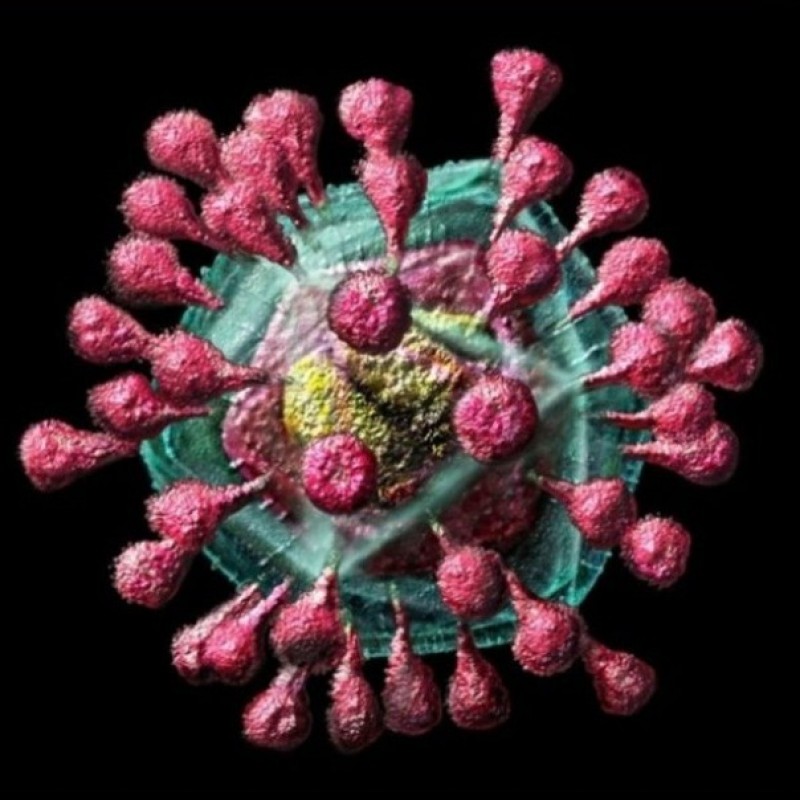Hal ini tentu bukan tanpa alasan, IPNU bisa berkembang dengan cepat di sana. Organisasi NU ternyata memang sudah mengakar kuat dan bahkan sudah lama dikenal oleh masyarakat Wonopringgo, jauh sejak awal NU didirikan pada tahun 1926.
Hal ini bisa dibuktikan dari jejak keterlibatan beberapa nama kiai asal Wonopringgo, yang kala itu ikut menjadi utusan dari Nahdlatoel ‘Oelama’ Tjabang Pekalongan, yang kala itu belum terbagi menjadi dua wilayah yakni kota dan kabupaten, di perhelatan kongres/muktamar NU.
Terlebih pada saat Pekalongan menjadi tuan rumah Muktamar ke-V pada tahun 1930, para kiai asal Wonopringgo yang terlibat, sebagaimana tercatat di majalah Swara Nahdlatoel ‘Oelama’, antara lain Kiai Mansoer dan Kiai Dimjati. Keduanya, kebetulan merupakan ayah dan anak, dan berasal dari Desa Rowokembu.
Selain keduanya, tentu ada kemungkinan nama ulama lainnya yang berasal dari Wonopringgo di perhelatan Muktamar NU di Pekalongan tersebut. Namun dari penelusuran yang penulis lakukan, sejauh ini baru kedua nama tersebut yang diketahui sebagai kiai asal Wonopringgo.
Dari catatan riwayat singkat yang ditulis KH Sofwan Naim di buku Keluarga Besar Mas KH Mansoer (1994), Kiai Mansoer yang sebelumnya memiliki nama Soerjadi, kemudian berganti nama setelah menunaikan ibadah haji di tahun 1925. Dalam berdakwah, Kiai Mansoer menggunakan terbangan (rebana) dan shalawatan untuk menarik minat masyarakat setempat.
Semasa hidupnya, Kiai Mansoer dikaruniai putra-putri, di antaranya Sadeli, Rahmat, dan Hajin (baca: Hayin) yang kemudian ikut menjadi penggerak NU Wonopringgo. Juga para menantunya antara lain Kiai Haji Soebki (ayah KH A. Taufiqurrahman, Pengasuh Pesantren At Taufiqiy Wonopringgo).
Salah satu putra Kiai Mansoer yang bernama Rahmat (lahir 1895 M), menimba ilmu ke Mambaul Ulum Surakarta, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1905. Di sekolah yang alumninya dipersiapkan untuk menjadi imam pengelola masjid dan pengulu itulah Rahmat mendapatkan perpaudan ilmu agama dan umum, dan yang tidak kalah penting jaringan persahabatan dengan para santri yang berasal dari berbagai daerah.
Seperti halnya yang dilakukan sang ayah, Rahmat kemudian mengganti namanya menjadi Dimjati (baca: Dimyati). Dugaan penulis, pergantian nama menjadi Dimjati, yang oleh orang Jawa biasanya dilakukan seusai menikah atau melakukan ibadah haji tersebut, merujuk kepada nama Dimjati (Kiai Haji Dimyati Candrawiyata) yang menjadi salah satu guru di Mambaul Ulum Surakarta. Bisa pula pergantian nama tersebut, ngalap berkah dari ulama tersohor asal Tremas Kiai Haji Dimjati at-Tarmasi.
Sepulang dari Surakarta, Dimjati dijadikan sebagai nadlir, imam, mulang ngaji, dan secara perlahan menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh ayahnya, Kiai Mansoer, yang sudah sepuh. Termasuk estafet peran yang ia emban, tentu untuk mengabdi dan berjuang dalam wadah Nahdlatul Ulama.
Dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, Kiai Dimjati juga berperan besar, salah satunya pada tanggal 3 Oktober 1945 ketika ia bersama para tokoh pejuang lainnya di Pekalongan, ikut memimpin pasukan untuk menyerbu markas tentara Jepang yang berada di sebelah Masjid Syuhada (monumen) Pekalongan, untuk melucuti senjata mereka.
Penulis: Ajie Najmuddin
Editor: Abdullah Alawi
2. Wawancara Tsaqiful Ghofur, cicit Kiai Dimyati Rowokembu. 25 Maret 2020.
Terpopuler
1
Santri Kecil di Tuban Hilang Sejak Kamis Lalu, Hingga Kini Belum Ditemukan
2
15 Ribu Pengemudi Truk Mogok Nasional Imbas Pemerintah Tak Respons Tuntutan Pengemudi Soal ODOL
3
Perbedaan Zhihar dan Talak dalam Pernikahan Islam
4
Sound Horeg: Pemujaan Ledakan Audio dan Krisis Estetika
5
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
6
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
Terkini
Lihat Semua