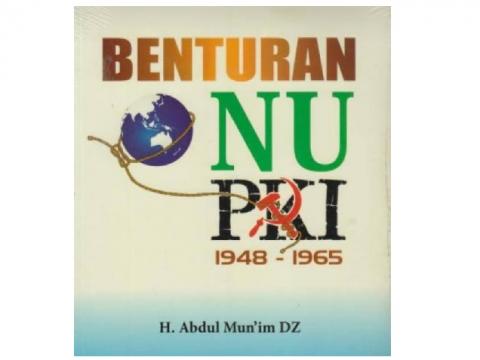Mewaspadai Isu PKI sebagai Jualan Politik
NU Online · Ahad, 27 September 2020 | 12:00 WIB

Persoalan terbesar kita sebagai bangsa terkait dengan PKI adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi dengan baik.
Achmad Mukafi Niam
Penulis
Dahulu, isu Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya ramai pada bulan September mengingat pada bulan tersebut terjadi gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Namun belakangan, isu tersebut terus-menerus didengungkan; kapan pun dan di mana pun dengan narasi bahwa saat ini telah terjadi ancaman serius bangkitnya kekuatan PKI. Para kadernya digambarkan sedang menyusup ke lembaga-lembaga strategis di lingkungan pemerintahan, ormas, atau lembaga penting lainnya.
Benarkah PKI sebagai pengusung ideologi komunis akan kembali bangkit? Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab ketika berkembang spekulasi tentang kebangkitan PKI. Ideologi komunis sendiri sudah runtuh di dunia. Perang Dingin telah berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya. Uni Soviet sebagai negara pengusung komunisme sudah bubar dan wilayahnya terpecah dalam banyak negara. China secara resmi menganut negara satu partai dengan ideologi komunis, namun sektor ekonominya menganut kapitalisme negara.
Kini, tinggal beberapa saja yang tetap setia dengan komunisme, tetapi situasinya sangat memprihatinkan. Salah satunya adalah Korea Utara. Komunisme terbukti gagal dalam mewujudkan impiannya berupa masyarakat tanpa kelas yang sejahtera. Komunisme identik dengan negara tertutup, otoriter, dan terbelakang, yang tak lagi senapas dengan perkembangan zaman yang menuntut kesejahteraan dan kebebasan. Akibatnya, ideologi ini tidak lagi populer. Negara yang masih mempertahankan ideologi tersebut sebenarnya lebih karena ambisi kelompok berkuasa untuk terus bertahan.
Kecurigaan atas kebangkitan PKI lebih sebagai sebuah isu yang diembuskan kelompok tertentu dan kemudian digunakan untuk menuduh orang-orang yang secara politik tidak disukai dengan label PKI. Siapa saja bisa diberi label seperti itu, termasuk Banser yang jelas-jelas pembela ulama. Tuduhan tersebut juga dialamatkan kepada Joko Widodo dan ramai diperbincangkan pada masa kampanye. Banyak kasus serupa di masyarakat meski tidak semua mencuat ke publik.
Pada masa Orde Baru, orang-orang yang sebelumnya diidentifikasi sebagai PKI dan para keturunannya diberi identitas khusus. KTP-nya diberi keterangan tambahan ET (Eks-tapol) Mereka tidak dapat menjadi pegawai negeri atau anggota TNI dan Polri. Secara sosial mereka terus dihukum dengan stigma-stigma negatif sekalipun pemberontakan tersebut sudah selesai puluhan tahun sebelumnya. Para keturunan PKI yang tak tahu apa-apa ikut menjadi korban.
Pemerintah Orde Baru beralasan, ketentuan tersebut dibuat supaya para keturunan PKI tidak bangkit lagi untuk memberontak sebagaimana terjadi beberapa kali sebelumnya. Karena itu, mereka mesti diawasi dengan ketat. Masyarakat menerima saja aturan seperti itu karena selalu ditunjukkan kekejaman PKI di masa lalu yang telah melakukan pemberontakan selama dua kali.
Setelah reformasi, ketentuan khusus bagi eks-PKI dan keturunannya dihapuskan. Mereka memiliki hak sebagaimana warga negara yang lainnya. Namun, stigma buruk yang sudah berlangsung selama beberapa puluh tahun dan telah berada di alam bawah sadar masyarakat tidak dengan mudah dihapuskan. Situasi psikologis ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan serangan politik pada orang lain.
Persoalan terbesar kita sebagai bangsa terkait dengan PKI adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi dengan baik. Jangan sampai kita terus-menerus merawat permusuhan yang mengakibatkan generasi baru yang tak tahu apa-apa tersebut turut menjadi korban. Mereka merupakan bagian dari bangsa ini yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain.
Nahdlatul Ulama memiliki hubungan kelam dengan PKI ketika banyak kiai yang dibunuh dalam pemberontakan Madiun 1948. Periode 1960 awal berisi tentang provokasi-provokasi yang dilakukan oleh PKI terhadap para kiai yang menyebabkan terjadinya ketegangan di tingkat akar rumput. Hal tersebut akhirnya meledak pasca-Gerakan 30 September. Namun, usai periode gelap tersebut, para kiai NU melakukan upaya rekonsiliasi secara kultural dengan mendidik anak-anak eks-PKI di berbagai pesantren. Mereka akhirnya menjadi Muslim yang baik. Proses rekonsiliasi yang tak perlu gembar-gembor tapi memberi hasil yang nyata.
Upaya politisasi isu PKI dengan memberi label orang atau kelompok tertentu yang tidak disukai, sebagai PKI jelas-jelas sikap yang tidak sesuai semangat untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung sekian dekade ini. Selain tak produktif, penggunaan isu PKI menunjukkan ketidakmampuan untuk merancang tema yang lebih baik untuk meraih simpati publik.
Peristiwa yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih ini, dan terus diulang-ulang narasinya menunjukkan bahwa hal ini belum sepenuhnya selesai. Karena itu penting untuk mendidik publik tentang sejarah masa kelam perjalanan bangsa Indonesia tersebut secara lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai sebuah pelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan. Hal ini untuk menjadikan kita sebagai bangsa yang lebih kuat dan kokoh sembari memastikan bahwa proses rekonsiliasi yang telah berlangsung secara alamiah ini tidak diganggu oleh ulah segelintir orang yang ingin menggunakan isu-isu komunisme sebagai bahan jualan politik.
Kini kita juga masih menghadapi persoalan nyata berupa semakin tinggi kesenjangan antara orang kaya dan kelompok miskin. Sebuah masalah yang ternyata tak mampu diatasi oleh komunisme yang menginginkan masyarakat utopis berupa kesejahteraan bersama. Inilah problem besar yang perlu kita pikirkan bersama untuk dicarikan solusinya dengan pendekatan baru, daripada terus-menerus menebarkan ilusi ketakutan. (Achmad Mukafi Niam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
5
Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
Terkini
Lihat Semua